(1)
Mama Eta

Oleh: SILVESTER PETARA HURIT, 30 April 2023
Mengapa kesulitan terus datang sedang hidup sudah susah? Mama Eta menyalakan lilin, berlutut di depan foto Tuan Ma dengan Rosario kayu cendana di tangan. Ia berdoa dengan lutut gemetar dan air mata yang terus menggenangi kedua kantong matanya. Digenggamnya erat rosario warisan ibunya, didekapnya lebih erat ke dada.
”So tiga taon ni Mama Bunda te jalan kelua lia nagi. Lia kita pung susah.(Sudah tiga tahun ini Mama Bunda tak jalan keluar lihat kampung. Lihat saya punya susah).”
Praaaak! Daun pintu dibanting keras. Disusul dengan gedebuk tubuh yang rebah di sofa tua ruang tengah rumah.
Begitulah hari-hari Besa Betu, suami Mama Eta. Pulang tengah malam atau dini hari dalam keadaan mabuk berat, apalagi kalau kalah bermain kartu.
”Mama Bunda, saya pamit sejenak. Besa Betu sudah pulang.”
Mama Eta menunduk lalu mundur dengan lututnya kemudian berdiri mengambil selimut, membuka pintu kamar menuju sofa tua yang sudah sobek di mana-mana.
”Besa Betu e….”
Mama Eta membungkus tubuh suaminya. Kalau saja masih kuat, ia ingin bopong suaminya ke kamar. Dingin. Kilat dan guntur susul-menyusul. Hujan sebentar lagi akan sangat lebat. Dipandangnya lekat wajah suaminya lalu kembali tanpa menutup lagi pintu kamar.
Di depan foto Tuan Ma, Mama Eta kembali berlutut. Spontan ibu jarinya menggerakkan biji-biji kontas. Nyala lilin meliuk-liuk ditiup angin.
”Mama Bunda, ampun salah-dosa Besa Betu”.
Air matanya mengalir lebih deras. Mama Eta tahu suaminya orang baik. Baru tiga bulan Besa Betu minum arak dan main kartu sampai sepayah ini.
***
Tiga tahun berturut-turut tanpa prosesi Jumat Agung seperti Sion dalam ratapan Nabi Yeremia pada setiap lamentasi Rabu Trewa di Katedral Reinha Rosari Larantuka. Jalan-jalan diliputi dukacita, tak ada peziarah, sunyi senyap seluruh pintu gerbang dan imam-imam berkeluh kesah.
Sudah ratusan tahun Patung Tuan Ma diarak keliling kota setiap Jumat Agung dalam tradisi Semana Santa di Larantuka. Ribuan umat khusyuk dengan lilin di tangan, doa-doa dan nyanyian sepanjang malam. Tak peduli hujan, tak peduli badai ataupun situasi genting perang.
Tuan Ma memilih Larantuka kampung tepi pantai sebagai miliknya. Ia datang sendiri jauh sebelum datangnya para misionaris dari Eropa menyebarkan agama Katolik. Mula-mula, seorang nelayan bernama Resi melihat perempuan asing di pagi buta. Bercampur panik dan takut, ia pergi memberi tahu kepala kampung. Ketika mereka ke pantai, ia sudah menjelma patung. Mereka membawanya ke korke menyimpan dan menghormatinya dengan sepenuh kasih.
Ibarat rahim, korke menyimpan segala teduh-damai. Semua yang asing dan berbeda-beda menjadi satu. Walau para misionaris yang datang kemudian menyebutnya sebagai rumah berhala, Tuan Ma memilih tinggal di sana lebih dari satu abad. Mama Eta percaya Bunda yang penuh kasih merangkul semua di dadanya. Tak peduli agama apa yang dianut dan seperti apa cara masyarakat Larantuka tempo dulu beribadah.
****
Tahun ini Mama Eta dan semua warga kota bergembira karena tradisi Semana Santa,terutama prosesi Jumat Agung, boleh berlangsung lagi. Namun Mama Eta sangat sedih karena Besa Betu harus kehilangan pekerjaan. Ia salah satu dari 2.859 tenaga kontrak yang diberhentikan di awal tahun karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Padahal sejak pulang merantau dari Malaysia, sudah 15 tahun ia bekerja sebagai penata taman. Gaji Besa Betu 800 ribu tiap bulan dijatah buat cicilan utang di bank sejumlah 785 ribu. Masih lagi 3 tahun.
Tujuh tahun lalu Besa Betu dan Mama Eta nekat mengajukan pinjaman dengan rumah dan sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk biaya syukuran pentahbisan dan misa perdana Pater Vincent, anak semata wayang mereka. Kini ia bertugas sebagai misionaris di Mogincual Keuskupan Nacala Mocambique. Tak soal berutang bahkan punah keturunan. Yang penting mereka bisa mempersembahkan yang paling berharga bagi Tuhan dan Gereja.
Susah memang sudah biasa. Namun, beban utang dan ancaman rumah disita bank bikin galau. Semana Santa makin dekat. Hotel-hotel sudah di-booking habis sejak beberapa bulan lalu. Penginapan susteran dinaikkan 3 kali lipat menjadi 800 ribu per kamar. Juga rumah susun bantuan pemerintah untuk keuskupan dinaikkan menjadi 650 ribu per kamar. Harga yang sulit dijangkau untuk peziarah dari pulau atau wilayah sekitar. Sudah biasa setiap tahun Mama Eta menerima peziarah sekitar belasan orang di rumahnya tanpa dipungut sesen pun. Semana Santa, menurut pesan leluhur, adalah hari baik buat serewi nagi tana.
****
”Beras tinggal satu kali masak. Uang cicilan di bank 2 hari lagi jatuh tempo,” kata Mama Eta mengingatkan Besa Betu. Mama Eta merapikan lilin yang dibuatnya sendiri dari bekas lelehan lilin yang dikumpulnya selama beberapa bulan terakhir.
”Besok kita kedatangan 3 orang, 3 hari hari lagi 9 orang tamu. Beras di pasar sudah naik lagi. Lima belas ribu rupiah per kilo.”
Besa Betu tak mengeluarkan sepatah kata pun. Seperti biasa ia pergi keluar rumah. Mama Eta pun bergegas ke pekuburan untuk pasang lilin dan berdoa. Jiwa-jiwa tersesat menerima terang oleh doa-doa. Dan leluhur suci mendoakan anak-cucunya yang masih berziarah di dunia.
Setelah melipat pakaian dan merapikan peralatan dapur, Mama Eta menunggu Besa Betu yang belum pulang-pulang. Sudah pukul 23.30. Sepi sekali rasanya. Ia membayangkan seandainya anaknya tak jadi Pastor mungkin mereka tak sesusah sekarang. Tinggal mengasuh cucu. Mama Eta segera sadar. Tak boleh ada penyesalan. Harus selalu setia mendukung anaknya menjadi imam Tuhan dengan doa yang tak henti-henti.
”Mama Bunda, ampun salah-dosa kami, ampun salah dosa kami.”
Entah sudah berapa kali kalimat itu keluar dari mulut Mama Eta. Semakin malam, semakin khusyuk ia berdoa. Besok perayaan hari Minggu Ramu di mana Yesus disambut masuk kota Yerusalem. Sambutan mengawali pengkhianatan dan penyangkalan dari muridnya sendiri. Mama Eta harus pergi misa pertama pukul 06.00. Sambil memikirkan besok 3 orang tamu peziarah datang, beras habis, cicilan bulan ini lusa akan jatuh tempo, ia pun tertidur.
Mama Eta kaget pukul 05.00. Spontan ia membuat tanda salib lalu sujud pada foto Mama Bunda. Segera ia keluar mengecek Besa Betu yang tertidur mabuk di Sofa. Ia meraba pipi Besa Betu dengan sedih. Tak tega ia bangunkan suaminya. Bergegas ia ke dapur membuatkan kopi dan pisang goreng. Dengan hati-hati, ia letakkan di meja dan menutupnya dengan tudung saji. Mama Eta meraih handuk dan langsung ke kamar mandi.
Di Gereja Katedral, Mama Eta duduk tepat berhadapan dengan Patung Bunda Maria. Ia berdoa buat anaknya di tanah misi serta para imam, biarawan dan biarawati, suami yang belakangan suka mabuk, tamu peziarah yang akan tiba, kelancaran perayaan Semana Santa serta semua yang sakit dan bersusah.
”Mama Bunda, beras kami habis, cicilan bulan ini besok batas jatuh tempo dan sebentar 3 tamu peziarah sudah tiba di rumah….”
Doa Mama Eta terpotong oleh lagu perarakan ”Hosana Putera Daud” yang dinyanyikan dengan meriah oleh kor dari lingkungan Kristus Salvator. Sepanjang misa Mama Eta coba berkonsentrasi penuh, namun tak selalu berhasil.
Beres misa, sebagaimana biasa Mama Eta membantu menghitung uang kolekte. Waktu makin kasip. Uang belanja belum ada. Ia masih harus ke pasar, pun belum masak buat makan siang. Saat ini ia pegang uang kolekte di tangan. Uang umat, uang paroki, uang gereja. Pinjam rasanya tidak mungkin. Romo Paroki lagi sibuk bersiap mendampingi Yang Mulia Bapak Uskup untuk misa kedua. Ia memejamkan matanya.
”Mama Bunda, saya pinjam pakai uang ini 300 ribu. Begitu dapat uang saya ganti”, katanya dalam hati sambil tangannya menyelipkan uang 300 ribu di saku bajunya.
Mama Eta gemetar. Keringat mengalir dari wajah, leher dan tangannya. Ia menyetor uang yang lain. Menggabungkan dengan yang dihitung oleh Ibu Udis dan Mama Katarina lalu pulang dan terus ke pasar. Pulangnya langsung masak. Sebagian ikan dan sayur dititipkan pada kulkas tetangga. Kulkas Mama Eta rusak dan belum diperbaiki.
Rupanya apa yang dilakukan Mama Eta tadi dilihat oleh Ibu Udis. Hanya dalam hitungan jam tersebar kabar bahwa Mama Eta mencuri uang kolekte.
”Pasti hal itu dilakukannya selama ini. Baru kali ini ketahuan.”
”Anaknya Pastor, Mamanya begitu. Bikin malu saja,” sambung Ketua Lingkungan begitu mendengar cerita dari Mama Katarina.
”Pelayan di Kapela Mama Bunda kalau tabiat macam itu baiknya dipecat saja.”
”Dasar tai terada! Punya Tuhan saja diembat.”
Mendengar istrinya demikian, Besa Betu langsung pergi ke saudarinya di Adonara tanpa memberi tahu Mama Eta. Ketika ke Kapel Tuan Ma semua mencibir Mama Eta. Ia lalu ke Pastoran untuk mengakui dan menjelaskan apa yang diperbuatnya, namun Romo Paroki tak memberi muka. Tetangganya mengembalikan ikan dan sayur yang ia titipkan. Katanya, mereka tak mau simpan barang haram di kulkasnya. Nanti bisa bau rumahnya. Mama Eta hanya menangis. Tangis yang ia sembunyikan dari tamu peziarah yang inap di rumahnya.
Daripada bikin orang tak nyaman, Mama Eta memilih tak bertugas sebagaimana biasanya di kapel. Ia hanya menangis di hadapan foto Tuan Ma di kamarnya.
Mama Eta merasa seorang diri. Tanpa suami dan anak di samping. Bagai pesakit di hadapan tetangga, teman, dan keluarga. Ia mengikuti rangkaian prosesi Jumat Agung dari dalam kamarnya. Doa, ratapan, nyanyian terdengar jelas dari pengeras suara. Mama Eta merasa bagaimana hati Mama Bunda mengikuti jalan salib putranya. Anak semata wayang jadi musuh banyak orang. Musuh agama dan negara. Dihukum mati dengan cara disalib sebagai penjahat. Mama Bunda merasakan setiap hinaan, cercaan, siksa yang dialami sang putra. Setia sampai memeluknya dalam keadaan tak bernyawa setelah diturunkan dari salib. Tak ada tempat buat pemakaman. Hanya seorang Yusuf dari Arimatea yang merelakan makam keluarganya bagi kubur sang putera. Semua disimpan dalam hatinya.
”Mama Bunda…”
Air mata Mama Eta terus mengalir.
***
Lewotala, Maret 2023
Catatan: Tuan Ma: Bunda Maria Ibu Yesus
Mama Bunda: Sapaan (akrab) orang Larantuka terhadap Tuan Ma
Semana Santa: Pekan Suci dalam rangkaian perayaan Paskah
Korke: Rumah adat kampung suku Lamaholot
Serewi nagi tana: Melayani/mengabdi kampung halaman
Minggu Ramu: Minggu Daun-Daun
Tai terada: Tak punya apa pun (secara materi)
***
Silvester Petara Hurit. Alumnus Jurusan Teater STSI Bandung (ISBI sekarang). Menulis cerpen, esai, dan lakon. Mendirikan Nara Teater. Bergiat mengembangkan iklim teater dan sastra di Flores Timur NTT.
Trie Aryadi Harijoto, lahir di Bandung, 1984. Pendidikan: 2002 Seni Grafis FSRD ITB. Aktif sebagai seniman di Bandung. Sejak 2005 hingga 2023 terlibat dalam bebebrapa pameran, antara lain pameran bertajuk Preliminaries di Orbital Dago Bandung tahun 2023 dan pameran Human + Space Galeri di Soemardja, Bandung tahun 2005.
***
(2)
Tak Dinyana

Oleh: HOTMA DI HITA L TOBING, 29 April 2023
Dengan semangat pemuda itu pamit kepada ibunya. Siap-siap mau pergi ke Kopeda menemui Juwita pujaan hatinya. Kemudian Hendra sudah ada di dalam bis mini Sampagul, meninggalkan Kopela menuju Medan. Kotanya berjarak 119 km dari Kopela ke kota Kopeda. Angkutan berisikan penumpang: tua dan muda, menembus jalan penuh pengkolan. Lagu-lagu karaoke-nostalgia mengiringi perjalanan mereka. Indah nian lagu-lagu yang diputar. Pikiran Hendra jauh melayang ke Juwita, gadis yang akan ditemuinya di Kopeda.
Hendra menyadari bahwa sudah waktunya mengakhiri masa mudanya. Maka sejak Juwita dikenalnya delapan bulan lalu di Jakarta, mereka kerap makan siang bersama karena kantor mereka berdekatan. Bicaranya sopan dan sikapnya yang tegas, kerjanya lugas dan tuntas membuat orang segan. Lagi pula dia mau pula dikunjungi tiap malam Minggu. Karena itu dia semakin terpikat. Begitulah anggapan Hendra pada mulanya. Paras Juwita ayu, tawanya renyah. Hendra acap mengajaknya bercanda ria dan bincang tentang masa depan. Di pikiran Hendra bahwa Juwita-lah calon istrinya kelak. Betapa tidak, Juwita bekerja di perusahaan penerbangan keren. Dapat fasilitas gratis naik pesawat dua kali setahun. Orangtua dapat diskon 75 persen sekali perjalanan. Enak bukan? Begitulah angan-angan Hendra.
Suatu malam Hendra pernah mengatakan serius dengan Juwita. Dari pergaulan mereka selama ini, Hendra terus terang menginginkan Juwita menjadi ibu dari anak-anaknya, dan menjadi menantu ibunya. Sudah waktunya mereka berbicara lebih lanjut kepada orangtua.
”Jadi maksudnya serius nih? Hendra mau melamarku? Begitu maksudmu?” tanya Juwita.
”Ya, jangan lama-lama lagilah. Buat apa lagi kita buang-buang waktu,” jawab Hendra.
”Datanglah ke Kopeda pada awal tahun baru ini. Kita bertemu dengan ibuku secara pribadi. Aku ini milik ibuku. Semoga ibuku setuju. Selanjutnya mari kita lihat,” kata Juwita.
”Ya tanggal satu malam Januari, saya janji datang ke rumahmu.”
Sebagai PNS di masa itu. Bulan Desember, Hendra mengambil cuti akhir tahun pulang ke Sibolga, Sumatera Utara, melalui kapal laut KM Gunung Rinjani. Dia akan berbicara kepada orangtua Juwita, bahwa dia mau menikahinya. Karena itu pada malam Tahun Baru dia telah ungkapkan kepada ibunda tentang calon menantunya. Hendra ingat tadi malam perkataan ibunya.
”Sudah berapa jauh kau mengenalnya, Hendra? Apa buktinya dia mencintaimu?”
”Kau tak pernah cerita. Terbaik adalah dia tidak sayang kepadamu saja. Tetapi sayang kepada keluarga. Jangan langsung percaya begitu saja. Hati-hati, Nak. Bila tak berhasil. Cari yang lain.”
”Percayalah, Inang. Juwita pastilah jadi calon menantumu yang baik.”
Memang ada beberapa pesan teman-teman Hendra di Jakarta, memberi saran. Konon Juwita itu hobi main kartu remi Zorro semalaman. Tak peduli main kartu dengan siapa saja. Suka ke diskotek sampai pagi. Kabarnya dia itu wanita berpantat bensin. Tetapi apa pun komentar teman-temannya. Hendra yakin segala kebiasaan masih muda dapat diubah setelah menikah nanti. Apa pun kata orang tentang gadis itu, Juwita tetaplah pilihannya. Tetap melangkah dengan jatmika.
Pukul 18.30 dia tiba di rumah kekasihnya itu Kopeda. Angin berembus dingin. Hendra mengancingkan jaketnya mengurangi rasa dingin. Sepi sekali suasana sekitar. Hendra mengetuk pintu. Tiada yang menyahut. Kembali dia ketuk. Kali ini lebih keras. Lalu lampu menyala. Pintu terbuka. Seorang ibu sepuh berjaket biru tersenyum padanya. Seorang gadis remaja ikut mendampinginya.
”Horas, Inang. Selamat malam,” sapa Hendra. Mereka saling bersalaman.
”Selamat malam. Gerangan siapakah yang datang,” sembari memperbaiki letak kacamatanya.
”Saya Hendra, Inang. Ompung Taronggal, kan? Saya temannya Juwita dari Jakarta.”
”Ya betul, saya Ompung Taronggal. Langsung dari Jakarta-kah?”
”Tidak, Inang. Ke Kopela dulu ber-Tahun Baru dengan keluarga,” jawab Hendra.
Setelah berbincang sekejap, ibu itu langsung pergi ke dapur. Sehingga memberi waktu bagi Hendra memandang sekitar. Dinding yang penuh dengan foto-foto keluarga. Namun, matanya tiba-tiba terbelalak melihat sesuatu. Dia langsung berdiri menuju dinding di mana benda itu dipajang. Sebuah jam dinding dan etiket dengan cap berwarna putih lusuh masih tertempel di bagian dalam jam itu. Si ibu mempersilakan tamu mencicipi dodol, kembang loyang, dan minuman panas.
”Apa yang kau lihat, Nak?” tanya si ibu. Hendra menjadi kaget.
”Maaf, Inang. Jam dinding itu saya ingat betul,” imbuhnya.
”Terus apa yang menarik perhatianmu di jam dinding tadi,” selidik tuan rumah.
”Oh itu, Inang. Karena pada jam dinding itu dan merek pembeliannya.”
”Oh begitu ya? Tiga puluh tahun yang lalu,” kata si ibu.
Tapi karena gayanya Hendra bercerita. Akhirnya Ompung Taronggal itu ingat akan jam dinding yang dibelinya di Kopela. Jadi ceritalah Hendra, ketika masa SMP dulu membantu di toko milik orangtuanya tiga puluhan tahun di Kopela. Sementara si ibu kala itu adalah pedagang kain antarkota. Dalam pikiran Hendra, ini bisa jadi suatu pertanda akan mulusnya rencana, menikahi Juwita.
Sementara Hendra sudah mulai curiga karena Juwita tidak nongol-nongol batang hidungnya. Lagi keluar rumahkah? Atau lagi tidur. Di dalam hatinya timbul tanda tanya besar. ”Ngomong-ngomong kita sudah lama bicara,” kata Hendra.
”Oh ya. Apa maksud kedatanganmu Nak kemari?”
”Tapi ya dari tadi Juwita kok tidak muncul, Inang. Saya datang untuk ketemu Juwita.”
”Oh Juwita ke luar kota, Nak,” kata ibu dengan tenang. Tapi pemuda itu mulai terperanjat.
”Ke luar? Sudah lama ke luar kotanya, Inang?” Hendra makin heran.
”Terus terang. Saya datang ke Kopeda ini dan bertemu dengan Inang secara pribadi. Mau bicara serius tentang rencana pernikahan kami,” kata Hendra.
Wajah ibu semakin heran dan bingung. Jantungnya berdegup kencang.
”Saya tidak tahu sama sekali rencana itu,” jawabnya sambal geleng-geleng kepala.
”Itulah sebabnya saya datang ke Kopeda ini, Inang. Jadi nanti, keluargaku akan bertemu dengan keluarga di sini,” kata Hendra dengan tegas.
”Mau bertemu keluargaku dan keluargamu?” tanya ibu itu heran.
”Ya. Betul sekali, Inang. Saya kira sudah diberi tahu Juwita, Inang.”
”Wah Juwita. Permainan macam apa yang dilakukan putriku? Sungguh tak dinyana.”
”Ke luar kota dengan siapa Juwita?”
”Ya dengan pacarnya, Liberti, pergi ke kota turis,” kata ibu itu terus terang.
”Dengan Liberti, pacarnya?” ucap Hendra emosional. Tak menyangka jawaban sang ibu.
”Mereka sudah berhubungan lama,” ucap sang ibu lagi.
Kesal rasanya bagi Hendra. Sungguh tak dinyana. Seakan-akan dipermainkan Juwita. Mengapa ini bisa terjadi. Lalu si ibu memanggil gadis remaja yang sejak tadi berada di dapur.
”Oh Salmina. Salmina.”
”Ya, Ompung,” jawab gadis remaja itu sigap.
”Tolong dipanggil Nan Toho tukang husuk di sebelah. Bilang cepat suruh kemari.”
”Maaf, Inang. Apakah mereka masih lama pulang?” tanya Hendra.
”Titi… dak tahu ya, Nak,” kata ibu itu terbata-bata, sambil menekan dada.
”Saya jadi pusing, Nak. Jantung saya kambuh. Tolong! Tolong saya.”
Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang ibu masuk menemui Ompung Taronggal. Mereka berdua tampak bicara serius. Ompung Taronggal menekan dadanya. Wajahnya memelas.
Dia dibaringkan segera ke sebuah rusbang, sebuah tempat tidur di ruang tamu itu. Nan Toho tampaknya segera mau meng-husuk. Akhirnya orang tua itu berkata dengan terbata-bata.
”Tolong tinggalkan saya, Nak Hendra. Maaf tak sanggup memikirkan hal ini. Maafkan perbuatan Juwita.”
”Ya benar itu, Nak. Saya mau urut Ompung Taronggal biar cepat sembuh,” kata Nan Toho.
”Apakah kita tidak bawa ke rumah sakit, Inang? Biar saya ikut bantu,” kata Hendra.
”Untuk ini, Anda tidak usah ikut campur dulu. Mengerti bukan?” kata Nan Toho lebih tegas.
Hendra mulai resah gelisah. Tidak menyangka akan mengalami hal ini. Tetapi dia harus terima kenyataan. Lagi pula sudah ada orang lain bersama mereka. Soal Juwita nanti dulu. Ingin segera meninggalkan kedua ibu itu. Hendra pun pamit dan segera kembali ke losmen tempat dia menginap.
Kemudian Hendra segera pergi ke kafe. Memesan minuman hangat. Mencari meja yang sepi. Dia menghindari gerombolan orang di tempat itu.
Dia mencium minuman keras. Mereka bernyanyi dengan diiringi pemain gitar. Meski tak pas, dengan suara fals. Mereka bernyanyi lagu-lagu masa kini.
Baru duduk sebentar, seorang lelaki sepuh menghampiri Hendra.
”Kok sendiri, Lae.”
”Ya biasalah, Lae,” jawab Hendra. Dan lalu menatap lelaki tua itu.
”Kok wajahmu bermuram durja, Nak? Apa yang terjadi? Nama saya Ompung Saurdot.”
Timbul kaget dan tetap diam seribu bahasa. Lelaki itu menyulut rokoknya dengan tenang.
”Baru berantem dengan pacar, ya,” langsung to the point pula.
Karena didesak, Hendra pun berterus terang tentang apa yang terjadi. Setelah memesan minuman kamput, lelaki sepuh itu kemudian bercerita tentang kehidupan di dunia. Asyik sekali bercerita orang tua itu. Tetapi sesekali dia batuk-batuk.
”Terus. Sudah berapa puluh juta rupiah, uang kau berikan kepada dia,” lelaki itu menyelidik.
”Tidak ada, Lae. Hanya saya kecewa sekali,” terang anak muda itu sejujurnya.
”Nah belum ada bukan! Hanya kecewa saja!” lelaki itu lalu merentangkan kedua tangannya. ”Ya sudahlah. Pulanglah kau segera ke kampungmu. Cari yang lain aja,” kata lelaki sepuh itu.
”Diskusilah dengan ibumu. Doa ibu pasti manjur,” sambil menepuk-nepuk bahu Hendra.
Dengan langkah buru-buru lelaki itu segera pergi ditelan malam. Hendra diam seribu bahasa. Dia merenung, betul juga. Kecewa cinta jangan dibawa minuman keras. Benar juga kata inang pangintubu bila gagal. Jangan kecewa. Jodoh takkan ke mana. Mengenai Juwita. Nantilah diselesaikan di Jakarta saja. Buat apa dia terlalu memikirkan gadis yang tidak jelas. Bagaimanapun dia harus dapat restu dari ibunda tercinta.
Besok paginya, Hendra jalan-jalan ke pelabuhan danau Kopeda. Dinikmatinya pemandangan yang belum pernah dilihatnya itu. Anak kapal menurunkan barang dagangan: bawang merah, kacang tanah, cabai merah, asam, kepundung. Menaikkan barang kelontong, sembako, barang-barang kebutuhan sehari-hari ke atau dari atas kapal. Pedagang-pedagang dari Bakara, Tipang, Nainggolan. Anak-anak kecil pun berlomba mencari uang logam yang dilemparkan ke dalam Danau Toba.
Di Jakarta Hendra mau menemui Juwita. Tetapi selalu tidak berhasil. Ditemui ke tempat kos. Sudah pindah kos katanya. Ditelepon ke Kopeda, tidak diangkat-angkat. Suatu ketika, diangkat. Oleh seseorang mengatakan salah sambung. Menurut teman-teman sekantor, Juwita lagi diklat ke luar negeri.
Karawaci-Cinere-Banten, 6 April 2023
Catatan:
– Kopela: kota pelabuhan laut
– Kopeda: kota pelabuhan danau
– Inang: ibu
– Ompung: nenek
– Meng-husuk: memijat
– Lae: ipar
– Kamput: kambing putih
– Inang pangintubu: ibu yang melahirkan kita
***
Hotma Di Hita L Tobing, lahir di Tarutung, 8 Juni 1959. Alumnus dari STIA LAN, pensiunan PNS. Menikah dengan TSSU Siringoringo. Telah dikarunia tiga anak dan seorang cucu. Di masa mudanya menulis puisi, cerpen, dan artikel dalam bahasa Inggris di buletin IEC, Hello English Magazine, The Indonesia Times. Sebanyak 20 puisi, sejumlah cerpen, dan artikel dalam bahasa Inggris dimuat di Tintota.com di Australia dan Faithwriters.com. Cerpennya dimuat di Analisa, SIB, Koran Sindo, Jurnal Medan, Mimbar Umum, majalah Suara HKBP, SP Immanuel, SP INA. Cerpennya dimuat di Antologi Rebana 1 (2006), Rebana 2 (2007), diterbitkan harian Analisa, Medan. Kumpulan cerpen Perempuan di Kapal Terakhir (2012) diterbitkan LeutikaPrio, Yogyakarta.
***
(3)
Nyanyian Maritim Nusantara

Oleh: ELIZABETH GABRIELA, 27 April 2023
Hari Selasa, malam datang lebih cepat. Bulan separuh bulat menggantung tinggi dengan taburan debu-debu bintang mengelilinginya. Awan tipis diarak angin layaknya sebuah karnaval, menghasilkan bayangan besar-besar di bawah pepohonan. Gendis menatap suaminya yang sudah siap dengan seragam kebanggaannya, Bisma baru saja dilantik bulan lalu.
Bisma mengambil topi putih berhias gambar jangkar di bagian atas, dipasangkannya ke kepala istrinya seraya bernyanyi kecil, ”Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung samudra, menerjang ombak tiada takut!”
”Suamiku seorang pelaut, gagah berani, tak kenal takut!” Gendis mengganti liriknya.
Bisma nyengir, ”Aku akan berlayar selama enam hari.”
Gendis mengangguk, mengantar sang suami ke depan rumah.
”Tunggu aku ya,” Bisma mengecup kening Gendis.
”Pasti Mas,” Gendis melambai kepada Bisma yang mulai menghilang di balik mobil jemputan. Namun, Bisma kembali lagi, dia berjongkok sedikit agar tingginya setara dengan perut istrinya yang mulai membuncit. Diciumnya perut Gendis. ”Kalian harus menungguku.”
Gendis menatap Bisma sebentar, mengusap pipinya sayang. ”Selalu.”
”Sampai kapan pun?” Bisma bangkit, memberikan jari kelingkingnya.
Gendis balas mengaitkan kelingkingnya juga. ”Selamanya.” Lalu dipeluknya Bisma erat, ”Sekarang laksanakanlah tugasmu prajurit bangsa!”
Barulah setelah itu Bisma pergi, ”Aku akan kembali. Sampai jumpa!”
Hidup Bisma didedikasikan untuk bersisian dengan Ibu Bumi. Bisma masih mengingat pertama kalinya ia melihat sebuah kapal berlabuh di dermaga dekat tempat tinggalnya saat masih kecil. Kala itu matahari baru saja mulai terbenam, pantulan dari warna jingga tua bercampur kuning yang hampir redup menerangi badan kapal. Hadir sekelumit rasa yang tak tergambarkan di dadanya, Bisma jatuh cinta kepada laut. Ia begitu mencintai lautan hingga ingin menjadi salah satu dari bagiannya, dari situ ia bersumpah kepada dirinya sendiri akan menjaga sang Ibu Bumi milik Nusantara sampai kapan pun. Maka di sinilah Bisma bersama Baladewa-210421.
”Selamat pagi Komandan!” kelima jemari tangan kanan Bisma terangkat menuju pelipis.
Komandan Sutasoma mengangguk, ”Serda Bisma, kau terlihat sangat bersemangat.”
Di sudut lorong muncul Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Heru. ”Cuaca baik?”
”Semuanya baik,” Komandan Sutasoma membuat hormat, menjawab.
Baladewa-210421 berdiri kokoh di atas perairan Pulau Dewata bagian utara. Kokoh, siap untuk menjalankan latihan perang dalam rangka penguatan pertahanan negara.
”Kondisi laut bisa diprediksi, tapi itu bukan suatu kepastian. Selalu siaga dan berhati-hati,” seru Laksamana Heru yang kemudian pergi ke ruang monitor, ”sampai jumpa lagi Prajurit!”
Rabu subuh, langit bagai penuh permata. Angkasa diterangi bintang gemintang kekuningan yang menciptakan konstelasi megah pada latar belakang semesta yang kosong. Bintang-bintang itu berserakan di antara dua yang tak terbatas: laut dan langit.
Bayu, sesama serda, melambaikan tangan kepada Bisma. ”Hei Bisma, kemari!”
”Pagi,” Bisma balas menyapa. ”Apa yang terjadi? Wajahmu terlihat penuh kebahagiaan?”
Bayu tersenyum sangat lebar, ”Kekasihku menerima lamaranku. Kami akan menikah setelah aku pulang!”
Selalu begitu, setiap hendak berlayar pasti ada saja cerita-cerita menyenangkan untuk memulai pelayaran.
”Lapor Komandan, Baladewa-210421 sudah siap!” Mayor Arya datang.
Komandan Sutasoma menatap anak-anak buahnya, ”Kenapa kalian semua terlihat senang sekali hari ini?”
Mayor Arya nyengir, ”Istri saya baru saja melahirkan.”
Bisma ikut menjawab, ”Hari ini kehamilan istri saya menginjak usia tiga bulan.”
Sang Komandan mengucapkan selamat sekilas, lalu ia juga bercerita sedikit, ”Putri sulung saya akan diwisuda minggu depan.”
Percakapan singkat tak pernah absen sebelum mengarungi samudra. Menjadi tentara angkatan laut memberikan banyak kesamaan di antara para anggota maritim. Satu, mereka memiliki cinta tanpa batas terhadap daerah kelautan Nusantara. Dua, tali-temali kekeluargaan yang terjalin erat. Tiga, dedikasi tinggi tidak hanya terhadap bangsa, tapi juga kehidupan rakyat di dalamnya.
Hari ini Baladewa-210421 akan membawa 53 prajurit untuk berlatih seperti hari-hari sebelumnya. Setelah semua awak siap di posisi masing-masing, sedikit demi sedikit badan kapal perang turun dari permukaan, masuk ke dalam air, dan meninggalkan deburan ombak yang mencium bibir pantai.
”Izin turun ke kedalaman 13 meter,” Mayor Arya berucap kepada radio.
”Izin diterima,” balas suara tim penjejak.
Semuanya berada dalam keadaan baik. Akan tetapi, mendadak kapal terasa lebih berat dari seharusnya. Sebuah getaran datang mengguncang seisi kapal.
”Ada apa?” Mayor Arya menatap rekan-rekannya, ”periksa seluruh bagian kapal!”
Gagang periskop yang Bisma pegang juga bergetar. Setelah itu guncangan semakin hebat.
***
Hampir jam empat subuh ketika Roni yang bertugas menjadi salah satu bagian dari tim penjejak sea rider tidak menemukan lampu pengenal Baladewa-210421. ”Di mana mereka?”
Laksamana Heru bergegas melihat layar, seharusnya sekarang mereka sudah meminta otorisasi untuk penembakan torpedo. Namun, periskop kapal lenyap dari pandangan. ”Baladewa-210421 apakah kalian mendengar aku?” ia mengambil mikrofon.
Tidak ada jawaban.
Laksamana Heru dan seluruh tim penjejak terus memanggil, tapi sampai pukul empat tetap nihil. ”Radio kita terputus,” Roni menatap layar pemantau yang menjadi hitam.
Lima belas menit setelah itu helikopter diterbangkan, tak ada hasil. Mendekati pukul tujuh akhirnya Laksamana Heru membuat pernyataan, ”Baladewa-210421 hilang kontak. Tunda semua latihan, sekarang kirim pasukan untuk mencari putra-putra bangsa kita!”
***
Laut, si Ibu Bumi memang begitu indah, tapi juga mematikan dengan sejuta misteri mahaluas di baliknya. Perairan permukaan setenang kaca, tanpa riak sedikit pun, tapi nun jauh di bawahnya tiada arus yang dapat dikendalikan. Lampu di seluruh kapal berkedap-kedip, tanda ada yang tak beres. Guncangan-guncangan tadi sudah berhenti, tapi badan kapal menjadi miring.
”Tetap bertahan di posisi masing-masing! Kita tunggu bantuan datang!” Komandan Sutasoma berusaha menghubungi radio yang sudah terputus.
Seluruh awak kapal mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Namun, gelombang kedua hadir. Kali ini satu, tapi sangat kuat. Gelombang soliter menghantam, keseimbangan semakin kacau seiringan dengan tekanan di bawah laut yang terus membesar.
”Berapa lama lagi kita dapat bertahan?” tukas Bisma.
Kondisi di dalam kapal mulai pengap, badan Bayu bercucuran keringat dingin. ”Tujuh puluh dua jam jika listrik tak mati.”
Akan tetapi, itu tidak berarti apa pun karena arus kuat dari bawah laut kian mengencang. Momentumnya berlangsung dalam sekon yang tak terhitung, posisi kapal terus semakin miring. Bunyi partikel yang terlepas dari luar bercampur dengungan akibat tekanan air. ”Kenakan baju pengaman!” teriak Mayor Arya.
Kadang ada saat di mana waktu tidak dapat berlabuh pada satuan hitung mana pun, saat itu waktu tidak berarti banyak karena agaknya sang Waktu seolah menyatakan bahwa mereka hanya bisa sampai di sini. Keadaan di dalam kapal menjadi gelap, lampu mati, hanya menyisakan lampu darurat. Keadaan kaos, teriakan, jeritan bercampur dengan bunyi air. Menarik satu sama lain agar setidaknya tetap melekat pada apa pun yang bisa dijadikan pegangan. Komandan Sutasoma terbanting ke belakang, merosot di atas lantai.
”Komandan!” Bisma menariknya, ”bertahanlah!”
Komandan Sutasoma menggeleng, itu bukan berarti ia menolak pertolongan Bisma, tapi karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri.
Di antara bilik-bilik ruang sempit badan kapal, para awak berada dalam posisi tidak karuan. Ada yang tiarap sambil mencengkeram bagian bawah kursi, berpegangan pada tiang, berlutut karena terjatuh. Tangisan serta doa terucap di bibir dan hati. Kecepatan los. Kapal terjun bebas, terus melesat dan mereka semua tahu…, tidak ada jalan keluar.
Terlintas di benak Bisma, wajah Gendis dan bayi mereka yang tak akan pernah dapat ia lihat. Mayor Arya tidak akan bisa mendampingi pertumbuhan anaknya. Cinta Bayu terhadap calon istrinya yang ia bawa ke dasar laut. Komandan Sutasoma yang tak akan hadir di hari wisuda putri sulungnya. Semua kasih dari 53 prajurit kepada orang-orang yang mereka cintai. Terlepas dari segalanya, seluruh awak Baladewa-210421 berharap mereka masih memiliki kesempatan untuk menjaga lautan Nusantara untuk waktu yang lebih lama. Namun, memang inilah risiko sebagai abdi negara di atas atas nama cinta terhadap Tanah Air.
”Lapor Komandan, oksigen akan segera habis,” Bisma membaca alat pengukur udara.
Komandan Sutasoma membalas dengan senyuman.
”Kenapa Komandan tersenyum?” tanya Bayu yang berpegangan di salah satu panel pintu.
”Saya memulai pilihan menjadi prajurit lautan Nusantara dengan senyuman, maka ketika akhir datang saya juga akan tersenyum,” katanya.
Mayor Arya ikut tersenyum, ”Ini bukan akhir. Tidak akan ada akhir untuk kita karena setelah ini kita akan berlayar untuk selamanya.”
Komandan Sutasoma menatap seluruh awak, ia membuat hormat. ”Terima kasih.”
Serentak, semua membalas hormat. Lalu Bayu menyiulkan sebuah melodi. Mendengar rangkaian tangga nada itu, bibir Bisma bernyanyi bersama semua prajurit:
”Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdi
Bagimu negeri jiwa raga kami”
Air asin mendobrak. Pintu-pintu terlepas, jendela yang bocor kini pecah. Di bawah kedalaman 830 meter dari permukaan air laut, Baladewa-210421 terus berlayar menuju keabadian.
***
Percakapan singkat tak pernah absen sebelum mengarungi samudra. Menjadi tentara angkatan laut memberikan banyak kesamaan di antara para anggota maritim. Satu, mereka memiliki cinta tanpa batas terhadap daerah kelautan Nusantara. Dua, tali-temali kekeluargaan yang terjalin erat. Tiga, dedikasi tinggi tidak hanya terhadap bangsa, tapi juga kehidupan rakyat di dalamnya.
Dari ufuk timur sampai ufuk barat, kemilau surya menyambut. Nuansa warna hitam berubah menjadi warna-warna kilau menyala pada lapisan cakrawala, memantul bagai jutaan prisma. Sebuah kapal muncul di atas garis pemisah antara langit dan bumi. Baladewa-210421 telah berlabuh di dermaga pada dimensi tanpa batas, kekekalan di antara awan-awan keabadian tabir semesta. Pintu kapal didorong terbuka oleh Mayor Arya, luapan cahaya terang benderang menyapa. Bersamaan semuanya melangkah keluar, mereka menjejak di atas genangan bagai kaca. Gumpalan awan halus berwarna oranye lembut dan merah muda mengelilingi ruang kekal tersebut.
Komandan Sutasoma membenarkan posisi topinya, ”Ayo kita jaga terus lautan Nusantara untuk selamanya!”
”Siap, laksanakan!” sahut semua awak. Kemudian dalam suka cita penuh cinta menjaga Tanah Air, mereka berlarian menyambut cahaya tersebut.
***
Mereka yang tenggelam di dalam perairan semesta akan terus menghuni ruang semesta dalam misi menjaga samudra Nusantara.Namun, sesungguhnya mereka tak pernah benar-benar pergi karena jiwa mereka tetap hidup dalam setiap jengkal Tanah Air. Entah itu pada dimensi yang tersentuh atau yang tidak, cinta para prajurit akan selalu berlayar.
Di belahan dimensi yang lain, Laksamana Heru berdiri di atas sebuah podium, wajahnya dibasahi air mata. ”Kapal Baladewa-210421 dinyatakan telah melakukan patroli abadi bersama 53 awak di dalamnya.”
**
Kisah ini terinspirasi dari tragedi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada 2022.
***
Elizabeth Gabriela merupakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang baru lulus tahun 2022. Saat ini ia bekerja di United Nations Development Programme (UNDP). Ia memiliki hobi menulis sejak kecil, Elizabeth bermimpi bahwa suatu saat tulisannya bisa diangkat ke layar lebar dan menginspirasi banyak orang.
***
(4)
Kutukan Kartu Lebaran

Oleh: KARISMA FAHMI Y, 27 April 2023
Murni tak pernah menyangka ia akan membaca kembali kartu Lebaran di malam Lebaran seperti ini. Ia seperti dihujani doa. Bibirnya terkatup menahan senyum yang tak dapat menahan isi perasaannya. Dibukanya satu per satu kartu-kartu berisi tulisan cakar ayam dan gambar warna-warni yang ditempel acak itu dengan mata berkaca. Sesekali ia tersenyum membaca puisi, doa, atau pula ungkapan sederhana yang ada di kartu-kartu itu.
”Gunting bagian bawah, lalu dilipat seperti ini…,” suara Murni menggema di ruang kelas. Ia menggunting kertas dengan cermat. Anak-anak di kelas sibuk mengukur dan melipat kertas. Kelas menjadi hening, hanya terdengar suara gunting dan beberapa anak yang sibuk bertanya-tanya pada yang lain untuk mengejar.
”Begini, Bu?” Evi mengangkat kertasnya.
”Iya. Dirapikan lagi!” kata Murni menoleh sebentar, lalu kembali mengelilingi kelas, memperhatikan satu per satu kartu buatan anak-anak itu. Sesekali ia merapikan dan membantu tangan-tangan mungil itu meluruskan lipatan dan guntingan.
Selama bulan Ramadhan sekolah tidak mewajibkan pelajaran penuh. Beberapa jam pelajaran digeser menjadi kegiatan ibadah dan prakarya seperti membuat kartu ucapan Lebaran. Murni merancang kartu dua dimensi itu untuk dua jam pelajaran. Kartu ucapan sederhana dengan guntingan gambar dari kertas koran atau majalah bekas, seperti diorama. Anak-anak mengikutinya dengan semangat.
”Bu, kartu ini untuk apa?” tanya Mutia sambil terus sibuk menempel gambar dan merapikan garis pinggiran kartu.
Murni terdiam lama memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Mutia. Ia benar, saat ini kartu Lebaran sudah bukan lagi hal yang biasa dilakukan orang untuk mengucapkan selamat Idul Fitri atau meminta maaf. Di toko-toko sekalipun, sudah jarang ia temukan kartu Lebaran. Ucapan selamat berlebaran akan secara langsung disampaikan melalui pesan singkat atau bahkan jejaring sosial yang lebih mudah, murah, dan praktis. Sedang di daerah terpencil ini, orang hanya merayakan Lebaran dengan bersalam-salaman, berkumpul dengan saudara sekampung, atau bertukar masakan dan ketupat. Tak ada yang mengirim kartu ucapan.
”Silakan menulis puisi, doa, atau ucapan di kartu kalian. Kalian bisa mengirimkan kartu itu untuk orang tua atau untuk orang yang kalian sayangi,” katanya.
Anak-anak pun menurut. Kelas yang tadinya riuh kini kembali hening. Anak-anak mulai menunduk menulisi kartunya. Beberapa anak tampak sedang berpikir keras.
Murni tersenyum memandang tatapan polos anak-anak di kelas itu. Tiga tahun sudah ia menghabiskan waktunya mengajar di sekolah itu, sekolah dasar yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sekolah itu hanya memiliki beberapa ruangan kelas. Tidak semua murid mengenakan seragam atau juga sepatu. Hanya beberapa di antara mereka yang mengenakan seragam lengkap. Sebagian besar masih mengenakan sandal atau bahkan tak mengenakan alas kaki sama sekali.
Menjadi guru bukan cita-citanya. Cita-citanya menjadi bidan harus kandas karena biayanya yang tinggi. Namun kini, ia begitu menikmati dunianya. Dunia anak-anak yang berwarna-warni, yang selalu mengingatkan dirinya akan kehangatan masa kanak-kanaknya yang riuh.
”Bu, kapan kartu ini boleh diberikan?” suara Mutia kembali mengisi kelas.
Murni kembali terdiam. Ia sendiri tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan kartu itu.
”Saat malam takbiran,” katanya.
”Mengapa lama sekali? Kalau pulang sekolah nanti diberikan, boleh?” tanya Husna, siswa yang paling manja.
Pertanyaan Husna membuatnya terdiam lama. Sebuah kenangan kembali melintas di kepalanya. Lagi-lagi bibirnya mencoba tetap tersenyum. Di dadanya bergemuruh badai besar.
Sebentar lagi Lebaran tiba. Sejak kecil ia terbiasa menantikan malam Lebaran dengan dada berdebar penuh kegembiraan. Malam Lebaran adalah peristiwa yang selalu dinantikan Murni dan keluarganya. Banyak hal yang akan mereka lakukan untuk menyambut hari raya. Seluruh keluarganya, ayah, ibu, kakak, serta adiknya akan berkumpul di ruang makan untuk membuka hadiah dan parcel yang mereka terima saat takbir pertama berkumandang pada malam itu.
Ayahnya pegawai bagian pencatatan di kantor pemerintahan. Sebagai PNS, setiap menjelang Lebaran ayahnya selalu pulang membawa parcel dari kantor. Meski parcel itu diterimakan tiga hari sebelum lebaran, namun ayahnya selalu bersikeras untuk membukanya di malam takbiran. Dalam hati Murni menyimpan penasaran dengan isi kardus yang tertutup rapat itu. Kardus bergambar masjid itu bertuliskan: Selamat Hari Raya Idul fitri, Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Tulisan itu membuat hatinya berdebar mengingat bayangan-bayangan hari Lebaran.
Mereka berasal dari keluarga pas-pasan. Dengan gaji PNS di masa Orde Baru yang tak seberapa, ayahnya harus mencukupi dan menyekolahkan Murni dan tiga saudaranya. Ibu Murni pun seperti ibu-ibu yang lain di desanya, ibu rumah tangga biasa yang sesekali menerima pesanan jahitan untuk menambah penghasilan. Pesanan jahitan pun hanya akan ada ketika tahun ajaran baru, itu pun tidak terlalu banyak. Untuk menambah penghasilan yang lain, mereka masih memiliki dua petak sawah yang masih bisa ditanami sebagai tambahan kebutuhan sehari-hari.
Mendekati Lebaran, teman-teman Murni sering bercerita mengenai kue-kue yang telah disiapkan di rumah mereka untuk menyambut Lebaran. Isi parcel biasanya akan ikut menghiasi meja mereka untuk menyambut tamu. Namun, ayahnya tetap bersikeras untuk membukanya pada malam takbiran sehingga ia tak bisa bercerita pada teman-temannya apa saja kue-kue yang ada di rumah. Seperti Ranti, tetangga sebelah rumah, bercerita ia dan ibunya membuat kue kering dengan hiasan cengkeh di atasnya, atau Maryam, yang menyiapkan nastar buatan ibunya, atau pula Rahma yang menghabiskan waktu seharian untuk membuat kue mawar.
Murni tak bisa menceritakan apa-apa kecuali kacang bawang dan kacang telur buatan ibunya. Kacang bawang dan kacang telur bukan makanan istimewa. Setiap orang di desanya menanam kacang di kebun. Dan memang, kacang-kacang itu sengaja disisihkan ibu untuk persiapan Lebaran.
Murni selalu gelisah menunggu ayahnya pulang dari masjid, dan begitu ayahnya pulang, mereka pun menyerbu meja makan. Ayah akan meletakkan kardus parcel di salah satu kursi makan. Ada satu lagi kebiasaan yang mereka tunggu. Mereka telah bersiap untuk berlomba mengambil apa saja dari dalam kardus. Begitu isi kardus terbuka, kakak dan adik Murni berebut menjumput sesuatu dari dalam kardus. Siapa cepat dia dapat, adalah prinsip ketika berebut isi parcel.
Mereka akan memegang benda yang diperolehnya dan saling berpandangan, melihat apa saja yang diperoleh dari dalam kardus. Adiknya membawa sebungkus kotak permen berbentuk ketupat dan kaleng sarden. Abangnya memegang kaleng biskuit dan sekotak teh celup, kakak perempuannya memegang gula di tangan kiri dan kaleng wafer di tangan kanan, ayahnya mengangkat sebotol sirup, sementara Murni sendiri hanya kebagian kartu ucapan Lebaran. Berkali ia melongokkan kepala ke dalam kardus, namun nihil. Tak ada lagi benda yang tersisa di dalam kardus. Semua saling berpandangan, dan pandangan terakhir tertuju pada Murni.
Saudara-saudaranya menertawakan Murni yang menatap kartu Lebaran di tangannya. Kartu Lebaran itu berisi ucapan selamat Lebaran lengkap dibubuhi tanda tangan kepala kantor ayahnya. Kartu ucapan Lebaran bukan benda yang diinginkan dari isi kardus itu. Saking tidak pentingnya kartu itu, semua menertawakan nasib sial Murni, termasuk ayah dan ibunya. Hal itu sering kali terjadi pada Murni. Barangkali karena kurang cekatan, barangkali juga karena postur tubuhnya yang lebih mungil dari kakak dan juga adiknya, hingga beberapa kali di setiap Lebaran ia mendapat bagian kartu Lebaran, bukan benda yang lain.
Abangnya berseloroh, ”Sepertinya kau akan menjadi kolektor kartu Lebaran.”
Murni tak pernah merasa sakit hati atas olok-olok abangnya itu, toh semua isi parcel akan dibagi rata dan sebagian akan menjadi kue Lebaran untuk para tamu. Namun ternyata ucapan abangnya itu ada benarnya. Sekarang ia menjadi guru, dan harus mengajari murid-muridnya membuat kartu Lebaran. Sebuah profesi yang tak pernah terlintas dalam bayangannya.
”Bu, kartunya boleh diberikan nanti sepulang sekolah?” suara Husna kembali membuyarkan lamunannya. Murni tergeragap. Ia banyak melamun.
”Tidak. Silakan diberikan saat malam takbiran,” tegas Murni dengan jenaka.
”Harus diberikan pada orang yang kita sayangi atau keluarga?”
”Iya,” jawab Murni. Matanya mengerling bibirnya tersenyum mengembang, menutupi bening-bening kristal yang hampir jatuh di matanya.
*
Murni menatap sekali lagi amplop besar coklat itu dengan hati penuh haru. Ia tak menyangka akan mendapatkan kartu-kartu ucapan itu kembali saat ini. Sejak pemerintah menetapkan pegawai negeri tidak boleh menerima parcel Lebaran, ayahnya tak pernah lagi pulang membawa parcel. Tahun-tahun berlalu dan tak ada lagi kejutan membuka parcel. Mereka pun kehilangan ritual membuka parcel di malam Lebaran, dan ia merasa lepas dari kutukan kartu ucapan selamat Lebaran dari kardus parcel. Keluarga yang dicintainya pun kini telah tiada. Kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa mereka saat bus yang mereka tumpangi melintasi jalur kereta. Mereka akan berangkat mengikuti wisuda Murni saat itu. Hanya ia dan abangnya yang tidak ada di dalam bus itu. Ia berada di kampus hari itu, sedangkan abangnya telah menikah dan tinggal di Jakarta.
Lima tahun sudah ia melewati Lebaran tanpa keluarganya. Malam itu, di tangannya sebuah amplop besar dengan pita warna-warni terbuka di bagian atasnya. Di dalamnya menyembul kartu-kartu buatan tangan dengan tulisan yang belum rata. Murid-murid mengumpulkan kartu ucapan Lebaran dan mengirimkan kartu-kartu itu untuknya.
”Kartu ini untuk ibu guru yang kami sayangi, Bu Murni. Bu Murni keluarga kami. Bu Murni adalah ibu kami. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bu Murni selalu bahagia dan sehat. Kami sayang Bu Murni” tulisan cakar ayam di atas amplop itu adalah tulisan Mutia, si juara kelas.
Dipandanginya langit di luar jendela. Suara takbir menggema. Ia kembali teringat peristiwa bersama keluarganya berpuluh tahun lalu, saat ia masih anak-anak. Sekali lagi ia tersenyum haru. Kutukan kartu Lebaran itu masih berlaku padanya hingga hari ini. Kini baginya, kartu ucapan dan doa-doa itu melebihi parcel mana pun. Berlahan bibirnya merapal takbir yang berkumandang di kejauhan. Matanya kembali berkaca-kaca.
Juni 2016-Maret 2022
***
Karisma Fahmi Y, lahir di kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Aktif mengajar di SD Takmirul Islam Inovatif Surakarta. Esai, cerpen, dan puisi-puisinya pernah dimuat di Kompas.id, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Majalah Sastra Horison, Koran Tempo, dan harian Media Indonesia. Buku kumpulan cerpennya adalah Pemanggil Hujan dan Pembaca Kematian diterbitkan oleh penerbit Basabasi, dan satu cerpennya ada dalam buku Antologi Kumpulan Cerpen Koran Tempo 2016.
***
(5)
Tentang Dapur

Oleh: FARRA YANUAR, 22 April 2023
Kau tak akan pernah tahu, bagaimana dapur bisa mempengaruhi kehidupanmu. Begitu kata bapak, sambil menatapku dalam, dan sungging di ujung bibirnya. Ketika aku bertanya mengapa bapak begitu mencintai dapur. Waktu itu, aku masih belum genap delapan belas tahun dan kata-kata bapak adalah desir angin, menerpa lembut wajahku, terasa dingin, tapi kemudian begitu saja kuabaikan.
Aku meraih weker di samping tempat tidur dan dengan susah payah membuka mata untuk melihat angka-angkanya. Masih pukul 06.00, baru satu jam selepas shalat Subuh dan usahaku mencoba tidur setelah mengerjakan beberapa tugas semalaman. Tapi suara dari arah dapur membuatku urung kembali terlelap.
Dengan langkah belum ajek aku menuju dapur, menyambar segelas air di atas meja makan yang entah milik siapa, mereguknya perlahan, mencoba menghilangkan kantuk yang masih bergelayut di kedua mata. Kemudian duduk di samping bapak yang sedang melumuri ikan-ikan dengan bumbu campuran kunyit dan rempah lainnya.
”Tadi suara apa Pak.”
”Itu, ikan-ikan yang Bapak beli di pasar tadi, masih hidup dan melompat dari keranjang belanjaan, ibumu berteriak karena terkejut.”
”Ganggu aku tidur,” kataku menggerutu.
Bapak tersenyum, bertukar tatapan dengan ibu yang juga tertawa kecil.
”Sering-seringlah masuk ke dapur supaya kamu bisa belajar untuk mencintai dapur, kamu sudah besar.”
Aku hanya menarik bibirku sambil mengangkat bahu dan mengerling ke arah bapak. Itu sebuah saran yang belum juga sanggup kuturuti meski sekarang usiaku sudah bertambah. Kau tak akan pernah tahu, apa yang bisa dilakukan dapur ke dalam kehidupanmu, dan untuk mengetahuinya, kau harus memulai dengan mencintainya. Kalimat itu, sudah berkali-kali dikatakan bapak di sepanjang hidupku. Dan, aku masih saja bergeming.
Bapak dan ibuku mencintai dapur. Begitu cintanya, ibu mengenal setiap lekuk dapur seperti memahami tubuhnya sendiri. Dengan hanya terpejam, ibu dapat mencium dan membedakan aroma jahe, kunyit, kencur, kemiri, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Jika waktu memasak tiba, ibu seolah dapat merasakan bagaimana pisau-pisau dapur berbaris seperti serdadu, menunggu perintah untuk mengiris, memotong, mencincang. Kata ibu, mereka punya tugas berbeda sesuai dengan bentuknya. Wajan-wajan melonjak girang ketika dialiri minyak dan kompor, begitu bersemangat untuk segera dinyalakan.
Tentang dapur, bapak tak terlalu berbeda dengan ibu, bapak memperlakukan semua benda di sana seperti makhluk hidup. Bapak mahfum bagaimana caranya membuka lemari es dengan lembut dan merasakan kesepian kulkas yang kosong, mendengar teriakan gas yang nyaris habis atau tetes terakhir deterjen, padahal masih harus membersihkan setumpuk piring-piring dan peralatan dapur lainnya.
Bapak jugalah yang memilih rancangan kitchen counter, desain yang dibuat sedemikian untuk menyatukan dapur dan meja makan sehingga ada banyak orang yang bisa duduk bersama untuk makan atau sekadar menyaksikan semua kegiatan di dapur sebelum semua bahan mentah diolah menjadi hidangan.
Di dapur, ibu menjelma dewi, keelokannya menawan hati bapak tak henti. Dapur adalah tempat paling nyaman untuknya berlama-lama menemani ibu. Bukan sekadar memuji kepiawaian ibu meracik bumbu, memasak, dan menghidangkan makanan. Tetapi dapur seolah menjadi tempat paling sensual, membuat bapak mengumbar kegenitan. Menggoda ibu, mengoleskan adonan tepung di hidungnya, memercikkan air dari wastafel ke wajah ibu , atau bahkan pernah suatu kali aku memergoki bapak membisikkan sesuatu di telinga ibu sambil mengerling ke arah betis ibu. Sambil memerah di kedua pipinya, ibu hanya tersipu. Itu hampir mirip adegan dapur Brad Pit dan Angelina Jolie dalam film Mr and Mrs Smith.
Bapak dan ibuku mencintai dapur. Begitu cintanya, ibu mengenal setiap lekuk dapur seperti memahami tubuhnya sendiri. Dengan hanya terpejam, ibu dapat mencium dan membedakan aroma jahe, kunyit, kencur, kemiri, ketumbar dan rempah-rempah lainnya. Jika waktu memasak tiba, ibu seolah dapat merasakan bagaimana pisau-pisau dapur berbaris seperti serdadu, menunggu perintah untuk mengiris, memotong, mencincang. Kata ibu, mereka punya tugas berbeda sesuai dengan bentuknya. Wajan-wajan melonjak girang ketika dialiri minyak dan kompor, begitu bersemangat untuk segera dinyalakan.
Tapi tentu bukan hanya itu, dapur juga menyimpan rahasia pertengkaran yang coba disembunyikan bapak dari aku dan kedua adikku. Walaupun seingatku kemudian, semuanya selalu mereda ketika bapak membuat wedang jahe untuk ibu dan menggenggam tangannya sambil mengucapkan banyak janji, lalu ibu yang selalu lebih mudah emosi, menyerah saja dari setiap perdebatan jika bapak kemudian memenuhi kulkas dan karung beras.
Begitulah kira-kira kecintaan itu dibangun dan coba ditularkannya kepadaku. Lewat setiap gesture sederhana ketika bapak dengan khidmat mendengar ibu menyebut bumbu-bumbu untuk pepes ikan, lewat ketulusan ibu mengulek semua rempah menjadi satu, melalui kecerdasan ibu yang terus berpikir membuat hidangan terbaik ketika bahan panganan menjadi terlalu mahal untuk dibeli. Lewat kesetiaan bapak yang sigap membantu ibu kapan saja.
Maka, jika kau bertanya kepadaku apa itu cinta, aku akan menyebut dapur sebagai kata yang menyempurnakan kalimat lainnya. Dapur menjadi muasal aku memahami bahwa cinta adalah sesuatu yang akan terus mengantarkanmu pada rasa nyaman dan rindu. Aroma dari segala rempah bercampur dengan senyum ibu, tawa bapak juga rengek adik-adikku yang tak sabar menunggu masakan matang sempurna adalah cinta yang nyata, kerinduan yang akan terus menarikku untuk pulang.
**
Aku sedang berada di kota lain, di sebuah kamar kos dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Buku-buku berjajar rapi di rak yang kokoh, gorden bercorak kembang sepatu, harum pewangi pakaian, kasur yang cukup empuk di atas sebuah dipan tua yang terbuat dari jati, membuat kamar kosku jauh lebih mewah dari kamar kos temanku yang mana pun. Harganya lumayan, tentu saja aku bisa tinggal di sini bukan karena aku anak orang kaya, tapi karena suami ibu Eti Lambri sang pemilik kos adalah teman baik bapak selama kuliah.
Ibu Eti Lambri, yang parasnya manis meski tak muda lagi, adalah seorang ningrat keturunan tanah Banten. Menurut bapak, bu Eti adalah orang yang kerap menolong perjuangan mereka dari segi keuangan di zaman-zaman demonstrasi dahulu. Bahkan pernikahannya dengan teman bapak yang bernama Prayitno dilakukan di tengah perjuangan, menjadi bagian dari perjuangan. Sebab, ada saat ketika bapak, Prayitno dan teman-teman lain menjadi buron pemerintah kala itu, keluarga ibu Eti Lambri yang kaya raya menyediakan mereka tempat untuk bersembunyi.
Ketika Prayitno dan beberapa teman bapak lainnya dinyatakan hilang. Ibu Eti Lambri tak pernah lagi menikah. Tidak juga kembali kepada keluarga besarnya di Banten. Dia menjadi salah satu orang yang menginisiasi gerakan kamisan, sebuah ajang silaturahmi anggota keluarga yang hilang sejak mereka dilabeli sebagai buron pada rezim pemerintahan dahulu. Rumahnya ini sering dijadikan tempat pertemuan itu.
Ibu Eti sebatang kara, itulah mungkin yang membuat ia menyayangi semua penghuni kos, memperlakukan kami seperti anggota keluarga. Acara makan malam bersama atau sarapan gratis sering kali dikirimkannya untuk kami. Membuat semua merasa kerasan. Tapi seperti pepatah, rumah bukanlah sebuah tempat, rumah adalah seseorang di dalamnya. Maka, biasanya hanya karena ibu Eti lambri membuat sebuah telur dadar dengan taburan bawang daun. Aku rindu ibu dan bapak. Aku akan segera pergi ke terminal menunggu bus terakhir untuk membawaku pulang. Seperti waktu itu.
Setelah empat jam di perjalanan aku sampai hampir tengah malam, ibu sudah terlelap saat bapak membukakan pintu dan keningya berkerut.
”Kenapa pulang malam-malam begini.”
”Aku kangen Pak.”
Bapak tak bisa mendebatku, meski sedikit marah karena rasa khawatir. Malam itu aku bergegas tidur, hanya untuk menunggu hari segera pagi dan memasuki dapur dengan segala kegiatan dan masakan yang akan ibu hidangkan esok .
Berkali-kali aku melakukan itu, tiba-tiba pulang, tanpa terlebih dahulu berkabar dan mengejutkan ibu dan bapak. Itu hanya karena kerinduanku pada seluruh aktivitas di dapur.
**
Tapi pada sebuah hari, ketika siaran berita cuaca mengabarkan bahwa angin muson mulai bertiup dari Benua Australia, bukan Sabtu atau Minggu pagi. Bukan juga karena tiba-tiba aku merindukan masakan ibu, tapi setelah mendengar kabar bahwa bapak sedang kritis di rumah sakit. Ditabrak kendaraan seseorang tak dikenal dalam aksi demonstrasi para buruh yang dipimpinnya. Aku pulang ke kotaku dengan gamang.
Sampai di rumah sakit aku bahkan tak sempat menyapa bapak, mengatakan bahwa aku datang, mencium punggung tangannya seperti biasa. Bapak sudah dimandikan, ditutup kain putih dan bersiap untuk disemayamkan di rumah kami. Yang kemudian menggema di telingaku adalah raungan kedua adikku dan gambaran tak pernah lekang tentang paras ibu, layu dengan kedua mata menampung pilu.
Setelah malam itu, hari-hari kami begitu akrab dengan kesedihan. Isak tangis dari balik pintu kamar ibu, sunyi dari tempat tidur kedua adikku dan tentu saja kehampaan di setiap lekuk dapur. Kehangatan dan keceriaan rumah, seperti bunga mekar yang dipetik dengan kasar.
Seisi rumah menjadi begitu asing. Penghuni dan perkakasnya seperti tak bertautan. Bahkan, dapur yang selalu menjadi tujuan kami dahulu, tidak lagi menjadi tempat menyenangkan, sebab di sana kenangan tentang bapak terus berkelindan dan menyiksa perasaan. Masakan ibu pun menjadi kurang sedap. Selalu terasa lebih asin, seolah ditambahkan air mata ke dalam setiap kudapan yang dibuatnya. Minggu pagi, yang semasa bapak masih ada selalu kami tunggu, menjadi sebuah hari yang sebisa mungkin kami abaikan kehadirannya.
Aku sendiri benar-benar kehilangan alasan untuk pergi ke dapur, sekadar untuk mengambil makanan, aku akan menyuruh adikku melakukannya. Dapur menjadi belantara hutan, sunyi dan ngeri. Jika sangat terpaksa memasukinya, aku harus mengumpulkan nyali juga sebuah keahlian. Seolah hendak berhadapan dengan desis binatang melata, serangga-serangga beracun, suara langkah mengendap dalam gulita atau bayangan seram berkelebatan tiba-tiba.
Maka daripada menghabiskan seluruh energiku menghadapi semua itu, aku memilih menghindarinya, menjauh dan diam-diam membencinya kemudian. Aku menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan dapur kepada ibu dan kedua adikku.
**
Tahun-tahun berlari seperti seekor cheetah menangkap buruannya, secepat adik-adikku bertumbuh. Di tahun ketiga aku berhenti kuliah, memilih menjadi seorang buruh di pabrik tekstil. Keputusanku membuat ibu semakin murung. Tapi aku tak punya pilihan lain. Ibu juga paham, perlu bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan masa depan adik-adikku.
Setiap hari, sejak matahari masih berada di balik bukit-bukit itu hingga dia kembali ke sana saat senja luruh, aku tenggelam dalam keharusan-keharusan di bawah telunjuk para kapitalis. Karena alasan itu juga, aku tak hanya bekerja, aku belajar banyak hal dengan menjadi aktivis buruh, memperjuangkan hak-hak kami dengan berbagai cara, hingga berdemonstrasi melawan tirani yang berlindung di balik undang-undang. Aku melanjutkan apa yang diperjuangkan bapak hingga akhir hayatnya.
Dan di jalan perjuangan ini perlahan aku menjadi paham, dapur bukan semata tempat di mana bisa kutemukan piring-piring, gelas, cangkir, sendok. Di mana aroma opor masakan ibu atau telur dadar bawang daun iris racikan bapak selalu memanggilku pulang ketika sedang berada di mana pun. Tapi dapur adalah salah satu alasan mengapa bapak dan kawan-kawannya turun ke jalan, dapur adalah sumber keceriaan yang selalu bapak hidupkan di hari-hari kami, muasal kemurungan ibu yang bapak hindari seumur hidupnya, dapur adalah suara perih lambungku dan adik-adikku.
Maka sebisa mungkin aku menjadi pembelajar yang cepat. Setelah bekerja dan menjadi bagian dalam begitu banyak aksi buruh di organisasi hingga turun ke jalan, aku kembali memasuki dapur dengan perkasa. Mewarisi keahlian bapak, memprediksi deterjen atau gas yang hampir habis dan derap pisau-pisau yang berbaris, merajuk ingin segera mengiris.
Dan aku berjanji kepada semesta akan belajar lebih keras untuk bisa mencintai dapur, memahaminya perlahan seperti cara bapak melakukannya. Menghadirkan kembali ruh hari-hariku melalui senyum ibu, membawa renyah tawa adik-adikku di setiap lekuk dapur dan terus memelihara kenangan tentang bapak melalui aroma rempah-rempah kesukaannya dahulu. Walau janji itu masih jauh panggang dari api.
Sebab hari ini dan mungkin hari-hari selanjutnya, aku masih akan memulai pagi dengan turun ke jalan meneriakkan tuntutanku, memperjuangkan hakku!
***
Farra Yanuar menulis puisi dan cerpen. Karyanya disiarkan di berbagai media cetak dan daring. Buku terbarunya Tubuh Perempuan (Pustakakipress, 2021) baru saja terbit.
***
(6)
Ikan Tua dan Laut

Untuk Ernest Hemingway
Oleh: NURAISAH MAULIDA ADNANI, 20 April 2023
Ketika Ikan Besar ditarik ke atas, terlihat bias sinar matahari di permukaan laut, senar bening tebal mengangkatnya, dan bayangan seorang lelaki tua sendu seperti akan mati. Pandangannya beralih pada langit biru yang sedikit silau hingga pandangan itu menjadi kelabu, perlahan menggelap menjadi hitam. Hitam terkelam yang pernah dilihatnya, lebih gelap daripada malam-malam yang dilaluinya.
Terkadang dia bertanya-tanya mengapa tak ada ikan yang ingin berteman dengannya. Mungkin karena wajahku, mungkin karena tubuhku, mungkin karena aku makan mareka, pikirnya. ”Ya, aku selalu makan mereka, mulutku selalu haus dan terus menganga. Begitu juga ikan yang lebih besar dariku. Pun jika aku berteman dengan mereka, mereka pasti akan memakanku,” ucapnya sambil berenang, menjauh dari terumbu karang.
Dari kejauhan terumbu karang kelabu sedikit kekuningan, ikan-ikan kecil sudah tak lagi berada di sana sejak tempat itu perlahan rusak karena sampah dan limbah. Tempat itu rapuh, menyedihkan, hanya hewan-hewan menyedihkan yang tinggal di sana.
Ikan Besar membayangkan sekelompok ikan berenang, berwarna biru keperakan. Alangkah enaknya jika menu makanan hari ini adalah ikan berkelompok. Selain mudah ditangkap, sekali cengkaman dapat banyak daging, cukup untuk sehari atau dua hari ke depan, pikirnya. ”Sudah lama sekali aku belum makan, dua atau tiga hari? Bahkan aku tidak ingat kapan dan apa yang terakhir kumakan. Tempat ini seperti pengasingan, biru paling biru, tidak ada siapapun selain gelembung-gelembung kecil. Aku harap mendapat seorang teman, teman yang bisa kumakan,” ucap Ikan Besar, siripnya melambai-lambai, terus berenang membuat gelembung-gelembung kecil mengapung.
Dari kejauhan ikan kecil terlihat berenang sendirian, dikuti darah yang keluar dari badannya. Mata Ikan Besar membesar, dipelankannya gerakan tubuh, menggerakkan sirip tanpa bunyi, mulutnya menganga, sekali lahap gigi-giginya menerkam ikan kecil itu. ”Tidak terlalu buruk ikan kecil, sayangnya kita belum berkenalan. Maafkan aku,” ucapnya bergegas pergi. Namun, ada sesuatu yang tergantung dalam tubuhnya, senar yang tak terlihat menyangkut di mulutnya. Senar itu bening mengikuti warna sekitar. Mata Ikan Besar mengecil, dia merasa bagian dalam tubuhnya ditarik oleh senar itu. Ikan Besar bergerak ke arah sebaliknya, rasa sakit bagian dalam semakin menusuk. Bagian dalam perutnya mulai terkoyak. Ini perangkap, ini perangkap. Bagaimana bisa ini terjadi padaku? Pasti karena rasa lapar sialan ini. Seharusnya tadi aku lebih bersabar, seharusnya aku tahu ini hanya tipuan. Dasar ikan kecil sialan, batin Ikan Besar. Dia tetap berusaha menarik senar itu, namun senar berganti menariknya. Darah keluar dari mulut Ikan Besar, kemudian menyatu dengan air laut.
Ikan Besar teringat pengalamannya seperti situasi saat ini, itu terjadi ketika dia beranjak besar. Kail menggantung di mulutnya, dia berhasil mengelabui dengan gerakan yang tangkas dan cekatan, sehingga kail dan senar lepas dari mulutnya. Sisa luka itu masih di mulutnya, lubang kecil di bawah bibir. Tapi itu sudah lama sekali, sekarang dia sudah sangat besar dan tua, tubuhnya seolah membengkak.
Apa yang dilakukan manusia di tengah laut seperti ini? Perahu kecil itu, dia pasti sedang sendirian. Aku yakin dia tak mampu menarikku. Tidak, aku harus punya rencana sebelum dia memikirkan rencana untuk menangkapku, sebelum dia dapat menyentuhku, pikirnya ketika melihat bayangan hitam di atas permukaan laut. Samar-samar Ikan Besar dapat melihat alat pancing yang digunakan manusia itu, alat yang panjang dan lancip.
Ikan Besar bergerak ke arah sebaliknya, rasa sakit bagian dalam semakin menusuk. Bagian dalam perutnya mulai terkoyak. Ini perangkap, ini perangkap. Bagaimana bisa ini terjadi padaku? Pasti karena rasa lapar sialan ini. Seharusnya tadi aku lebih bersabar, seharusnya aku tahu ini hanya tipuan. Dasar ikan kecil sialan, batin Ikan Besar.
Ikan Besar menarik senar, berenang menjauh sekuat tenaga. Dia bisa membayangkan seandainya bagian dalamnya keluar, yang tersisa dari dirinya hanyalah badan tak berisi seperti cangkang keong tak bertuan. Ikan Besar tak mau hal itu terjadi. Walau dirinya sudah tua dan mungkin kali ini maut benar-benar menghampirinya, dia masih ingin hidup.
Ketika dia mulai sedikit kewalahan, justru senar itu yang menariknya. Badannya mengikuti arah senar, dia seperti melayang sekaligus jatuh. Ikan Besar segera menutup mulutnya rapat-rapat agar bagian dalam tubuhnya masih bertahan, dia berenang mundur memperhatikan jarak perahu dan dirinya yang semakin jauh.
”Kasihan manusia itu, dia berjuang sendiri sepertiku. Apa lebih baik kubiarkan dia menangkapku. Lagi pula aku sudah tua, mungkin dia sudah berhari-hari belum makan, mungkin sudah berhari-hari juga dia berada di tengah laut, belum mendapatkan ikan sama sekali,” ucap Ikan Besar melihat bayangan perahu yang menggelombang seperti bayangan ikan raksasa. Tapi aku tak boleh ingin mati begitu saja, mungkin aku hanya kasihan padanya. Seharusnya dia juga merasa kasihan padaku. Mungkin kita sama-sama belum makan berhari-hari. Tapi tetap saja, aku tidak boleh mati seperti ini. Kecepatan berenangnya semakin cepat dan gesit, terkadang siripnya menggunakan tempo pelan dan cepat. Dia cepat ketika senar mulai kendur, istirahat sebentar ketika senar menariknya. Ikan Besar loncat, memperlihatkan badannya yang besar. Dilihatnya manusia yang berada di atas perahu itu adalah manusia tua, lelaki tua seperti dia.
Apa yang kamu lakukan manusia tua? Berusaha menangkapku di tengah lautan sendiri. Mungkin nasib kita tak jauh sama. Antara kamu bisa menangkap dan membunuhku, atau kamu mati kelelahan karena berusaha menangkapku. Aku tidak mungkin lelah, walau aku hidup sendirian, walau aku sebenarnya mengasihani kamu. Mungkin saat ini kita sudah berteman, walau belum sempat berkenalan, dan sekarang saatnya kita bertarung. Siapa yang akan mendapatkan siapa, batinnya.
Ikan Besar tak lagi bisa mengingat hari atau waktu, bahkan dia tak menyadari matahari sudah terbit dan terbenam kembali. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun aku terperangkap, ditarik dan diulur oleh senar ini oleh pak tua itu, batinnya. Gelembung-gelembung kecil keluar dari mulutnya, gelembung itu naik ke atas seolah berhasil dipancing oleh manusia. Laut yang dilihatnya seolah buta, tidak melihat dirinya sedang sekarat. ”Tapi memang sejak dulu laut buta, dia tidak pernah menganggap keadaanku di lautan ini. Mungkin aku hidup untuk mati. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya aku menghindari pemangsa. Aku tidak pernah membayangkan diriku kembali pada situasi saat ini,” ucap Ikan Besar menarik senar lebih kuat. Sisi mulutnya mulai bergesek dengan senar, membuat bibirnya mendapatkan luka baru. Seandainya aku punya teman, apa kira yang dia lakukan ketika aku sedang kondisi seperti ini? Ah, teman ya. Mungkin dia akan memakanku, mungkin aku yang akan memakannya. Seandainya ada hal lain yang bisa kumakan selain ikan, pasti aku memakan itu. Pasir, terumbu karang, rumput laut. Tapi aku tak bisa memakan itu kecuali ikan-ikan, teman-temanku sendiri, batin Ikan Besar merasakan kail pancing berhasil merobek lambungnya, darah makin banyak keluar dari mulutnya.
”Sampai kapan manusia tua itu berusaha? Dia sudah tua, mungkin lebih tua daripada aku. Apa yang dia harapkan dariku? Aku hanya penyendiri yang memakan ikan berukuran lebih kecil dariku. Tubuhku tidak sesegar ikan lain, dagingku tidak terlalu enak walau aku tidak pernah mencobanya, tapi aku yakin akan hal itu,” ucap Ikan Besar berenang ke sana kemari.
Laut biru yang sunyi mengingatkan Ikan Besar pada darah yang keluar dari mulutnya. Air laut perlahan-lahan menjadi keunguan. Mungkin bau darahnya dapat mengundang beberapa ikan buas kepadanya, tapi Ikan Besar berhenti memikirkan itu. Dia tidak ingin dimakan oleh ikan buas ataupun manusia yang berusaha menangkapnya.
Arah berenang Ikan Besar semakin tak karuan. Rasa sakit dalam tubuhnya menyayat dari ujung bawah sampai ujung atas. Darah keluar dari mulut dan perutnya. Ikan Besar semakin dekat dengan bayangan perahu, seolah bayangan itulah yang akan melahapnya.
Kepala Ikan Besar keluar dari permukaan laut, dilihatnya manusia tua sendu seperti akan mati. Pandangannya beralih pada langit biru yang sedikit silau hingga pandangan itu menjadi kelabu, perlahan menggelap menjadi hitam. Hitam terkelam yang pernah dilihatnya, lebih gelap daripada malam-malam yang dilaluinya.
Mataram, Agustus 2022
***
Nuraisah Maulida Adnanilahir di Tulungagung, Jawa Timur, 27 Januari 2001. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Mataram. Cerpen-cerpennya dimuat di berbagai media, baik online maupun cetak. Saat ini bergiat di komunitas Akarpohon, juga mengelola perpustakaan Teman Baca, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
***
(7)
Ikan-ikan Buta Rumphius

Oleh: RAUDAL TANJUNG BANUA, 16 April 2023
TAK sekali pun ia menoleh ke belakang. Ia ingin segera berdayung, seakan melarung beban hidup yang tersandang.
Tapi saat mendorong perahu, ia dengar napas memburu. Memaksanya menoleh. Ternyata si sulung, dalam seragam putih-biru, mengejar.
”Kenapa balik, he? Ayah ’kan su bilang tak punya uang?”
Anak kelas dua SMP itu tenang sekali bilang, ”Beta bosan janji terus, Yah. Lebih baik beta ikut melaut, cari uang. Besok biar lega ketemu Ibu Maria.”
”Beraninya kau! Su berapa lama tak ada ikan, he?”
”Hari ini akan dapat, Yah….”
Si Ayah mau lanjut marah, tetapi karena dibuat punya harapan, seketika ia merasa punya teman, ”Naik sudah!” Cepat anak itu melompat naik, sesaat sebelum perahu berayun di punggung ombak. Meluncurlah ayah dan anak itu ke laut lepas.
Sambil berdayung, si Ayah bersiul. Si Anak ingat pantangan: bersiul di laut bisa panggil badai. Tapi ayahnya acuh tak acuh saja.
Ah, tak ada lagi takut mendera! Lebih dua tahun badai pandemi melanda, semua habis terjual atau tergadai. Hingga kini tak ada kepastian pendapatan. Gubuknya berdinding gaba-gaba mulai miring. Dihuni lima anak-beranak, dan istri yang lumpuh.
Si Ayah bersiul lebih keras mengusir bayangan celaka itu. Ajaib, si Anak melihat awan menyisih. Pertanda baik, bisiknya di ujung lunas perahu. Bagaimana pun, Patrik, namanya, terlanjur janji (berkali-kali) mau beli buku paket Pancasila dari Ibu Maria. Ia juga yakinkan ayahnya, Ahmad Muchsin, bahwa hari ini mereka akan dapat ikan.
***
”Kau yakin kita dapat ikan?” nada Muchsin menagih.
”Ya, Ayah!”
”Bagaimana kau bisa yakin?”
Patrik mengubah posisi duduknya. Persis ia duduk di perpustakaan sekolah—dan mulai bercerita. Sudah lebih seminggu ini, katanya, tiap jam istirahat tiba, ia ambil buku yang sama. Bercover biru laut, berisi gambar aneka ikan. Bila jam istirahat berakhir, ia simpan lagi di rak terbawah. Ia cicil membacanya.
Buku itu mengisahkan tentang lelaki seberang lautan mencintai ikan-ikan laut Maluku. Begitu tabah dan setia.
”Sebentar,” si Ayah teringat sesuatu. ”Do bukan pelaut seperti kita toh?”
”Bukan, Yah,” si Anak senang dapat tanggapan, ”Semula ia tentara. Tapi beralih jadi pengumpul ikan. Mungkin do tak suka perang. Setiap ikan ia catat dalam buku besar. Nama, ukuran, ciri, semua. Ia dibantu istri dan anak lelakinya yang rajin.”
Muchsin teringat istrinya yang lumpuh dan duduk sepanjang hari merangkai kerang dan lokan. Hasilnya berupa tasbih dan rosario dititipkan di art-shop Jalan Ampera. Ah, Patrik juga anak rajin, ia bergumam. Hari ini, tanpa diajak pun si Anak turut melaut.
”Sayang matanya diserang katarak, Yah. Seperti karang ditumbuhi terumbu. Ia buta akhirnya. Tak bisa lagi lihat laut biru dan ikan-ikan yang dicintainya,” nadanya sedih. ”Lebih kasihang lagi, Ibu Suzana, istrinya, meninggal karena gempa.”
”Ah, ayah ingat sekarang! Rumphius kau maksud?”
”Benar, Yah!” si Anak girang. ”Georg Eberhard Rumphius! Ayah tahu?”
”Sudah lama sekali…” suara Ayah bergetar. ”Dulu waktu ayah kecil, tetua masih sesekali menceritakannya. Laki-laki buta itu pernah tinggal di soa kita. Buyut dari buyut kita ikut membantunya kumpulkan ikan.”
Muchsin tatap cakrawala, dan kini balik bercerita. Katanya, lama setelah laki-laki itu meninggal, kampung dilanda paceklik. Nelayan pulang melaut dengan tangan hampa. Mereka panjatkan doa. Sebut nama-nama. Roh Kudus. Maria. Sulaiman. Khidir. Yunus. Tapi tak kunjung terkabul. Sampai Bapak Kepala Soa ingat nama yang terlupa: Rumphius. Itu layak disebut karena ketabahannya. Maka disebutlah namanya dalam doa. Tiga hari kemudian, ikan-ikan terdampar di pantai. Seluruh kampung berpesta.
”Konon, ikan-ikan itu buta. Orang percaya itu hadiah Semesta untuk Rumphius. Ia pun mempersembahkannya kepada leluhur kita sebagai terima kasih yang tulus.”
Hening. Hanya kecipak air laut disibak lembut dinding perahu. ”Maaf, ayah belum ceritakan ini padamu. Tapi Bapak Kepala Soa yang sekarang agaknya masih ingat cerita itu. Carilah dia nanti, lengkapi bacaanmu.”
Si Anak tergugu. “Beta percaya, Ayah juga tak akan menyerah toh?”
Si Ayah menggeleng. Matanya lamur oleh sesudut air asin menggenang.
***
Saat begitu tenang, tiba-tiba perahu bergoyang diayun sesuatu dari kedalaman. Ayah-anak itu bersiaga. ”Hiu!” si Ayah berseru.
Benar saja, sepasang hiu muncul melenggok di sisi perahu. Ukurannya lumayan, sekitar dua meteran. ”Lemparkan semua pancing!”
Si Anak melemparkan semua pancing. Ditambah pancing-pancing semula yang masih tertanam di air. Lama menunggu, tak satu jua disentuh moncong hiu. Dilirik pun tidak. Itu tampak menggemaskan di air jernih.
”Sayang tak ada jala,” sesal si Ayah. Ia mulai gusar dan memikirkan cara untuk tidak menyerah. Ah, kepalang basah, ia pinta, ”Pisau!”
Si Anak ambilkan pisau di balik bilah lantai perahu. Dan, cresss, ternyata si Ayah melukai telapak tangannya sendiri! Darah menetes ke laut.
”Ayah!”
”Seperti kau minta, ayah tak menyerah.”
”Tapi, Yah…”
”Nah, kaulihat, hiu mabuk bau darah,” Si Ayah tersenyum puas. Sambil menahan perih tangan, ia bongkar pengait besi, semacam tempuling, yang terikat di bagian dalam dinding perahu. Kini ia siap menundukkan.
Sial! Mereka melongos pergi, bagai kawanan anjing jinak di pantai mengibas-ngibaskan ekornya menjauh. Si Ayah ingin melolong.
”Sayang sekali,” dan ia mulai membebat lukanya.
”Pasti mahal, ya, Yah?” Patrik menyela polos.
”Cukup buat ongkos ibumu tiga kali ke dokter,” Muchsin hilang minat, dan dengan tangan terbebat, ia lanjut berdayung. Si anak menimba dengan perasaan kosong. Bukan rezeki kita, bisik Muchsin, seperti hari-hari kemarin. Bagaimana pun ia ingin bersikap selayaknya ayah menghibur anak yang kecewa.
Dan sikap mulia itu cepat berbalas: sepasang hiu itu muncul lagi sekarang. Muchsin jadi berang. ”Jika kalian pamer, enyahlah!” ia sodokkan dayungnya ke hiu penggoda itu.
Di luar dugaan, seekor di antara hiu kelabu itu membuat manuver cantik: tiba-tiba ia melompat ke atas perahu! Benda terapung itu nyaris terbalik. Ayah dan anak terkejut, tapi segera sadar rezeki tak ke mana. Keduanya bergulat bagaimana pun, menundukkan makhluk laut yang menggelapar membahayakan.
”Pisau!” lagi-lagi si Ayah minta benda berkilau itu.
Patrik menunjuk pisau dengan ragu. Garang laki-laki itu menyambarnya.
”Dia buta, Yah!” Patrik cegah pisau menghunjam lambung hiu.
Kaget oleh teriakan ganjil itu, Muchsin terhenti. Ketika hiu dapat dikuasai, ia ikut periksa matanya. Putih. Putih seluruhnya.
”Ah, kita pulang, seekor cukup!” mendadak ia putuskan putar haluan. Bayangan Rumphius menggelisahkannya.
”Ayah, mungkinkah roh Rumphius menggiring ikan buta ini kepada kita? Beta curiga kedua hiu tadi buta, buktinya tak seekor pun menyentuh kail kita….”
”Mestinya ada hidung, Buyung! Tapi entahlah. Semua serba mungkin. Lagi pula, kau benar, seekor telah melompat kepada kita.”
Dada Patrik melimpah. Ya, seekor telah menolong si Ayah yang hampir dibutakan oleh penderitaan. Roh Rumphius mungkin berperan.
Apa pun, kali ini ia senang mendengar ayahnya kembali bersiul.
***
Mereka berlabuh di muara tempat menara suar tua tegak dengan karatnya. Di situ ada los-los memanjang bagi segala jenis ikan. Dengan telapak tangan terbebat sobekan kaos parpol, ayah dan anak menurunkan seekor besar tangkapan mereka.
Para toke berdesak menyambut. ”Ale kena giginya?” seorang bertanya simpati.
”Kamong diserangkah?” yang lain ingin tahu.
”Tidak. Tangan beta kena pisau sendiri,” jawab Muchsin, berberes.
”Ai, ale tangkap pakai pisaukah?”
”Tidak. Beta umpan dengan darah.”
Orang-orang berdecak. ”Mesti ditempuh itu segala cara. Lama kita tak ada ikan.”
”Tapi kenapa bisa?” seorang lain memikirkan cara aneh tersebut.
“Hiu punya lobang hidung toh?” kata Muchsin sambil menancap dayung ke pasir.
“Lagi pula,” si Anak ikut menyela,”Ikannya buta…”
Dua orang petugas pelabuhan tertarik mendengarnya. Mereka kira mata hiu itu pecah sehingga disebut buta. Setelah dicermati, si petugas tahu mata itu putih bukan karena pecah atau meler. Seorang petugas berkata, ”Betul, kedua matanya buta. Tak mungkin kebetulan. Jadi, batalkan jual-beli.”
”Kenapa bisa begitu, Bapak?” Muchsin rasa itu candaan garing musim paceklik.
”Si petugas berbadan tambun mendongakkan kepala. ”Ini berbahaya. Kita baru saja reda dari bahaya Covid-19, sekarang mau coba bahaya daging beracun?”
“Maksud, Bapak?” nada Mucshin mulai naik.
”Kamorang dapat dari Teluk K, toh? Semua su tahu, ikannya seng boleh ditangkap! Tailing tambang emas di hulu sungai su cemari teluk!”
”Lagi pula,” petugas satu lagi menyela, ”Apakah ini bukan hiu terlarang?”
Orang-orang berbisik, ”O, pantas ia pulang paling akhir…ia diam-diam ke sana….”
”Untung kita tahu mata ikannya buta, jika tidak…, mati kita!”
”Jangan-jangan hiu langka, kita bisa dituduh penadah….”
Muchsin murka atas desas-desus keparat itu. Ia hunus pisau. Ia iris setangkup daging hiu dan siap ia telan mentah-mentah. ”Beta buktikan ini bukan ikan beracun, he?!”
”Stop, Bapak!” si Tambun panik. ”Kami bahkan lihat racunnya menetes!”
”Omong kosong!” Sekejap, daging sekepal tangan angslup ke kerongkongan Muchsin. Dan benar, terhuyunglah ia. Lalu bagai dipukul limbubu, ia rubuh. Orang-orang mengangkatnya ke bawah ketapang. Si anak menolak ayahnya dibawa ke klinik.
Patrik cabut dayung dan ia ayun-ayunkan. Ia yakin ayahnya hanya lelah dan sangat marah. ”Tinggalkan kami sudah. Ayah hanya mabuk!”
Orang-orang pergi, menggerutu, ”Ya, mungkin benar ia mabuk, seperti biasa….”
Kedua petugas pun pergi menyeret hiu buta itu. Mereka akan simpan di peti pengawet khusus bagi ikan-ikan berkasus.
Si Anak pangling. Sedari tadi ia berpikir hiu itu hadiah Rumphius untuk seorang ayah yang tak mau menyerah. Apakah akan ia biarkan dirampas, sekalipun oleh negara?
”Ikan buta Rumphius, ikan-ikan buta Rumphius,” Patrik berbisik lirih persis tetua soa mengucap mantra. Ia kejar kedua penyeret hiu keramat-suci itu. Seorang masuk ke kantor, mungkin melapor. Dan seorang lagi ia ikuti ke gudang.
Setenang mungkin ia bertanya, ”Apakah Bapak tahu ikan-ikan Rumphius?”
Orang itu terbahak. ”Itu di dunia ilmiah, Nak! Di sini, semua orang nelayan dan pedagang. Kecuali kau rajin belajar, dan kelak kuliah. Kau akan pelajari di sana. Bukan sekarang.” Ia meludah. ”Tapi lihat, baju sekolah ade pun telah jadi layar.”
Patrik raba seragam kumalnya. Di baliknya, pisau serba guna Ayah terbaring seperti dayung.
/Ambon-Yogya, 2023
__________________
Raudal Tanjung Banua, peraih Cerpen Terbaik Kompas 2018. Tinggal di Yogyakarta. Buku terbarunya, Cerita-cerita Kecil yang Sedih dan Menakjubkan.
Joko ”Gundul” Sulistiono, lahir 10 April 1970 dan menempuh pendidikan Strata 1 di ISI Yogyakarta. Meraih penghargaan kompetisi seni rupa Philip Morris Indonesia Art Award tahun 2000. Telah berpameran tunggal di Koong Gallery Jakarta (2003) dan Couple Art Exhibition di G-Print Art Studio Yogyakarta (2023). Kini menetap di Kota Yogyakarta.
***
(8) Rumah Trembesi
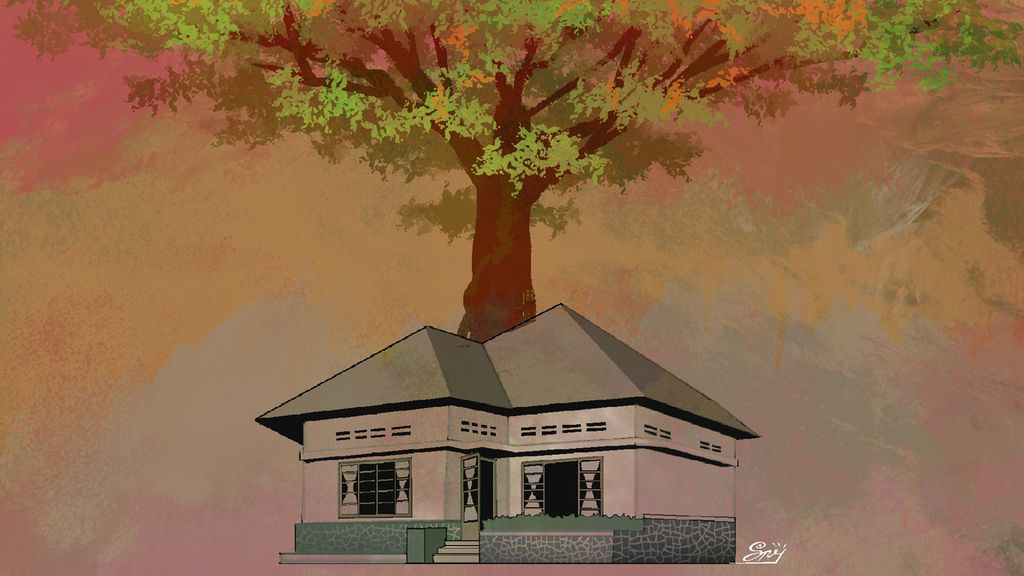
Oleh: AGUS DERMAWAN T, 15 April 2023
Sepasang orangtua itu, Brata dan Lenna, keluar dari mulut hutan. Mereka lantas berjalan pelan menuju rumahnya yang nun jauh di sebelah utara. Dua kantong plastik berisi buah berbentuk polong dengan hati-hati dijinjing. Satu di tangan Brata, satu di tangan Lenna.
Setelah berjalan sekitar satu jam mereka sampai di rumahnya, sebuah bangunan kuno berukuran besar dan lusuh. Mereka lalu merayap menuju tepian halaman luas, yang terposisi di bagian tengah rumah yang beratap langit.
Di tepian halaman itu Brata menumpahkan isi kantong-kantong plastik buah polong itu ke atas meja. Lenna bersigap. Ia segera mengambil baskom, dan menaruh puluhan buah polong itu ke dalamnya. ”Lelaki dari dulu begitu. Selalu maunya berantakan,” katanya. Brata tertawa, sambil mengalihkan percakapan.
”Kapten Arie Smit pintar merancang rumah ini. Bagian tengahnya dibikin lapang tanpa bangunan, sehingga matahari tropis bisa langsung menghambur ke sini. Lihatlah dari ketinggian, rumah ini manis membentuk huruf O.”
”Rumah ini bukan Smit yang merancang, tapi Wolff Schoemaker, tahu! Vergeetachtige oude man! (Dasar pak tua pelupa!),” tukas Lenna.
Mereka bersama tertawa.
Buah polong pohon trembesi dari hutan itu lalu dikupas kulitnya dan dikumpulkan dalam satu wadah. Untuk kemudian pada suatu hari digoreng. Hasil gorengannya dikemas dalam bungkus-bungkus kecil, dan dijual ke beberapa kedai. Dua orang tua itu mengerjakan semuanya dengan rasa gembira saja. Mereka tak ingin mengingat riwayat keterpurukan yang pernah dialaminya.
Dulu Brata dan Lenna adalah suami-istri yang tak berkekurangan. Mereka bekerja baik-baik di perusahaan milik pemerintah Belanda. Namun ketika diketahui Brata dan Lenna berdekat-dekat dengan para nasionalis pejuang kemerdekaan, mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Bahkan rumah kecil mereka di kota juga disita. Untung ada seorang aannemer Belanda yang berbaik hati. Pemborong itu menawarkan rumah tua tak terurus, dan konon berhantu, di sehampar desa. Lalu, selama bertahun-tahun Brata dan Lenna bermukim di sana, dengan meniti hidup sebisanya.
Siang itu mereka asyik mengupas polong, dan mengeluarkan biji-bijinya. Dalam keheningan yang bahagia mereka tiba-tiba mendengar ada suara mendengung keras dari kejauhan. Suara itu lantas terdengar semakin mendekat dengan deru menyeramkan.
”Hantukah itu?” tanya Lenna.
Belum sampai Brata menjawab, tiba-tiba terdengar suara ledakan-ledakan hebat. Suara itu sebentar menjauh, sebentar kemudian datang lagi. Dan debam-debum ledakan terdengar lagi. Mereka berdua terkejut bukan main. Biji-biji yang mereka keluarkan dari kulit berhamburan ke lantai dan tanah halaman tengah rumahnya.
”Siap! Berlindung! Pesawat Jepang menyerang dengan gila! Bom-bom dijatuhkan di wilayah kita!” teriak warga desa yang berhamburan.
Peristiwa yang sungguh bikin keder. Kalender yang tergantung di rumah tua itu menunjuk bulan April 1942.
*
Karena dikabarkan bahwa rumahnya akan direbut oleh tentara Jepang, Brata dan Lenna lantas pergi meninggalkan kediamannya. Dan mereka mengungsi ke suatu tempat yang tak tentu rimbanya.
Tiga setengah tahun kemudian, setelah Jepang hengkang, mereka kembali ke rumah itu. Mereka melihat betapa rumah semakin lusuh dan bahkan menyeramkan, tanda bahwa tidak pernah dihuni. Dari situ mereka memperoleh berita bahwa ternyata rumah tersebut memang tak pernah ada yang menempati. Takut hantu? Mungkin begitu. Namun yang paling mencengangkan adalah ketika mereka melihat: ada pohon yang tumbuh di halaman luas di tengah rumahnya. Pohon tersebut terlihat artistik dahan dan rantingnya, subur dedaunannya dan gagah benar berdirinya.
”Aku pastikan, pohon ini tumbuh dari biji trembesi yang tercecer dulu. Waktu kita kaget saat pesawat Jepang menyerbu!” kata Brata.
Mereka lalu kembali bermukim di rumah itu. Pohon trembesi tersebut dibiarkan terus tumbuh dengan rindang. Semakin hari semakin meninggi. Bertambah bulan bertambah pula rimbunnya. Akar-akar pohon yang merambat di beberapa sisi lantai dibiarkan saja.
Waktu terus beringsut. Ketika Brata dan Lenna menua, pohon itu menjulang dengan ketinggian melebihi atap rumah. Semakin bertambah tahun, semakin meninggi dan melebar dahan dan rantingnya. Sehingga rumah tersebut bagai bangunan yang berpayung daun.
”Surealis…rumah beranak pohon,” sebut seorang penduduk desa yang menatap pemandangan itu. Bukan, ”Pohon pelindung rumah,” kata warga satunya. Brata tersenyum mendengar julukan yang aneh-aneh itu. ”Kalau kami berdua menyebut ini adalah Rumah Trembesi,” kata Brata. Semua yang mendengar setuju saja.
Dalam kesempatan itu Brata dan Lenna berpesan: apabila mereka berdua meninggal dunia, rumah dan pohon itu diharap dipelihara oleh penduduk desa. Ini rumah bahagia. Ini rumah yang dianugerahi keajaiban semesta, katanya. Lalu, jika ada surat tanah dan bangunan yang perlu diurus, mereka telah menyiapkan biayanya dari uang tabungan. ”Kami tidak memiliki anak. Anak kami adalah rumah dan pohon ini.”
*
Syahdan setelah Lenna meninggal dunia, dan empat bulan kemudian disusul Brata, pohon itu sudah tumbuh begitu besar. Bentuknya seperti payung raksasa, sehingga rumah di bawahnya nampak bagai rumah liliput belaka. Dalam terik siang sang trembesi hadir seperti sesosok dewa yang sedang turun ke bumi. Dalam hujan sang trembesi serta merta menjelma jadi malaikat langit, pengendali rintik dan penangkap petir yang kesasar. Pada malam hari, di bawah cahaya rembulan, trembesi raksasa itu bagai siluet Sang Empunya Dunia. Lalu rumah dan pohon itu dengan bersungguh-sungguh diurus oleh warga desa.
Atas rumah trembesi tersebut Lurah setempat memiliki ide cemerlang. Ia mengumumkan ke warga wilayah lain bahwa di desanya ada pemandangan ajaib. Semuanya boleh menonton dan memasuki rumah itu, tapi harus membayar tiket terlebih dahulu. Seperti yang diduga, warga berbagai wilayah berdatangan. Mereka mengantre untuk melihat dari jauh, dan lantas berkhidmat masuk ke rumah, menatap takjub pohon raksasa itu.
Kepopuleran rumah trembesi semakin bergema. Bahkan ada yang menyebarkan kabar hoax bahwa pohon itu memiliki kehebatan: bisa memberi apa yang kita minta. Dari uang, jodoh, istri baru, sampai cara taktis melanggengkan kekuasaan. Alhasil, semakin banyak saja orang yang mengunjungi. Bahkan, orang-orang yang tadinya hanya percaya kepada Mbah Tedjo, si dukun kebal dari Situbondo, ramai-ramai beralih dan bersujud meminta-minta di bawah pohon itu. Koran-koran mengeksposnya dalam headline. Sebuah harian bertanggal 21 Agustus 2005 menulis dalam judul: Pohon Lebih Layak Dipercaya Dibanding Manusia.
Untuk menjaga kelestariannya, Lurah memerintahkan warga untuk membuat pagar kuat di sekitar situ. Sementara pintu masuk posisinya diperhitungkan cermat, agar tak sembarang orang bisa lewat. Dan di sekitar lokasi lantas terpasang papan logam bertuliskan: Cagar Desa Rumah Trembesi – Lokasi Wisata Keajaiban.
Lebih dari 100 tahun pohon itu berdiri. Tinggi pohon itu sudah setara dengan bangunan bertingkat 17. Sedangkan kelebaran gerumbul daunnya yang ijo royo-royo membentang lebih dari 80 meter. Sehingga rumah kuno di bawahnya terlihat bagai kotak korek api mini. Memasuki milenium ketiga kepopuleran rumah trembesi sudah tidak terperi. Suatu kenyataan yang memikat wisatawan nasional dan internasional untuk berkunjung. Apalagi pemandangan di sekitar rumah itu indah, dengan lereng-lereng bukit yang dihampari permadani tanaman teh. Diimbuh sungai bening, berbatu-batu dan dangkal, yang gemericiknya terdengar musikal. Ya, jika tidak indah, mana mau Kapten Arie Smit memilih lokasi itu?
Keramaian kunjungan wisatawan ini merangsang warga desa membuat rumah kecil di sekitar situ untuk disewakan kepada pengunjung yang berminat menginap. Usaha ini menstimulasi sejumlah orang kota untuk membuat aneka motel. Lalu kedai-kedai kopi dan aneka warung dibuka. selanjutnya restoran, cafe dan semacamnya muncul mentereng di sana-sini. Tempat parkir luas dibikin dengan menggusur lahan perkebunan. Untuk menguatkan persaingan antar pengusaha fasilitas wisata, para preman banyak direkrut.
Waktu terus beringsut. Ketika Brata dan Lenna menua, pohon itu menjulang dengan ketinggian melebihi atap rumah. Semakin bertambah tahun, semakin meninggi dan melebar dahan dan rantingnya. Sehingga rumah tersebut bagai bangunan yang berpayung daun.
Wisata rumah trembesi, yang kemudian berubah sebutan dengan Wisata Pohon Kemustahilan, memang mengundang ribuan tamu. Dengan begitu, melahirkan para pemandu. Tak sedikit pemandu yang mengarang cerita semau-mau, asal wisatawan takjub. Tapi ada juga yang berusaha referensial dalam berkata-kata.
”Trembesi ajaib ini bisa jadi saingan Dragon Tree di Pulau Canary! Tandingan pohon aneh Silk Cotton Tree di Seam Ream, Kamboja! Tak kalah cantik dibanding pohon baobab di Madagaskar sana! Kalau trembesi biasa saja bisa berusia limaratus tahun, kita boleh yakin, trembesi ini bisa seribu tahun. O ya, pohon dahsyat ini bisa menyerap karbondioksida, lho. Itu racun di udara! Juga memiliki buah yang gurih dan berkhasiat untuk kesehatan,” tutur seorang pemandu dengan menggebu.
Di sudut beda pemandu lain berkata: ”Layak diketahui, pohon trembesi ini bernama Latin Samanea Saman. Sementara di Indonesia dipanggil Pohon Ki Hujan. Kenapa panggilan ini muncul? Karena bagian-bagian pohon itu sering meneteskan air, dan jatuh seperti gerimis, bahkan seperti hujan. Indah kan? Ini lantaran kemampuan hebat akar-akar pohon dalam menyerap air tanah. Bapak dan Ibu sekalian, ini sungguh pohon kehidupan. Oleh sebab itu, setelah melihat Pohon Kemustahilan ini, baik apabila kita mulai menanam trembesi di rumah kita masing-masing. Atau di kampung kita masing-masing!”
Namun, keramaian wisata itu membawa akibat. Persaingan antar pengelola fasilitas wisata semakin hari semakin meruncing. Tukang parkir berseteru berebut pengunjung. Para restowan dan kedaiwan bersengketa berebut rejeki. Para preman maju perang membela masing-masing tuan. Bahkan ada kedai yang dibakar. Ada resto yang dirusak, dan mobil pemilik motel yang dicongkel. Urusan pohon ayal menjadi masalah sosial. Ketika Lurah puyeng dan Camat mengaku bingung. Bupati yang terkenal pendek pikiran segera turun tangan. Maka pada suatu siang si Bupati—yang terkenal sebagai mantan pegawai pajak nan mahakaya—meluruk ke lapangan.
”Saudara-saudara, saya Bupati Harun Rapal Tubodo! Dengarkan ya, kejadian ini sudah memusingkan dan berkepanjangan. Oleh karena itu harus diambil keputusan: apabila semua sengketa tidak bisa diredam, saya akan memusnahkan sumber dari keresahan ini. Rumah itu akan saya robohkan! Pohon itu akan saya tumbangkan! Sehingga kalian bisa kembali ke tempat masing-masing, tanpa sakit hati, tanpa umpatan!” seru Bupati sambil memoncongkan toa. Di belakangnya tampak delapan traktor peruntuh rumah. Juga belasan mesin penggergaji pohon, dengan dikawal selusin motor gede yang berdentam-dentam bunyi knalpotnya.
Belum selesai Bupati Harun bicara, mereka yang bersengketa kembali berhantam-hantaman. Preman yang disiapkan segera berkelebat dengan senjata tajam dan pentungan. Para pemilik kedai, resto dan penginapan saling menuding dan memaki. Bupati sungguh gusar. Ia segera memberi aba-aba. Lalu rombongan traktor dan mesin penggergaji itu terlihat bergerak menuju pusat lokasi Wisata Pohon Kemustahilan. Suaranya sangat mirip dengan dengung pesawat pembom Jepang!
Rumah itu dihancurkan, dan trembesi raksasa itu ditubruk-tubruk traktor dan berusaha dipangkas habis-habisan. Rumah rata tanah sudah! Tapi trembesi tetap berdiri perkasa tanpa sedikit pun terluka. Batangnya yang besar bergeming. Dahan dan rantingnya meregang keras bagai baja. Sepuluh mesin penumpas tampak lumpuh dan terbakar. Sedangkan berpuluh-puluh gergajinya berkeping-keping berpatahan. Ketika sisa-sisa mesin pemusnah berusaha mengorak pohon, puluhan juta helai daun trembesi mengibas langit. Dan hujan segera turun dengan derasnya. ”Apa salah saya, hai manusia!” Terdengar gemuruh suara ganjil di udara.
Siang yang terik dan terang benderang itu mendadak menghitam. Di salah satu sisi lokasi, wartawan National Geographic serius merekam semua kejadian.
***
Kelapa Gading, 2023.
***
Agus Dermawan T. Kritikus seni rupa. Penulis puluhan buku kebudayaan dan seni. Menulis puisi dan cerpen. Kumpulan cerpennya, Odong-odong Negeri Sulap terbit pada November 2022.
***
(9)
Pagebluk

Oleh: MASHDAR ZAINAL, 13 April 2023
Ibu menerakan hujan pada Jumat petang itu sebagai sebuah firasat. Setelah hampir sebulan hujan tidak turun, sore itu alam seperti menumpahkan dendam. Jumat yang hening. Seakan tidak ada pergerakan apapun di muka bumi ini. Sejak pagi matahari seperti sedang bermain petak umpet. Sedikit cahaya muncul, lalu redup lagi. Terang lagi, redup lagi. Sekitar pukul lima petang, langit rata menjadi gelap. Seolah langit kematian listrik. Tanpa diawali gemuruh, air dari langit luruh begitu gegas. Seperti bongkahan kerikil yang dilemparkan pakai ketapel. Suara di atap bergemeletap.
Ibu berdiri dari balik jendela, dan berkata pada dirinya sendiri, ”Hujan hari ini tidak seperti biasanya.”
”Iya, deras sekali,” aku menyahut.
”Bukan, bukan itu maksudku. Coba kau tengok air yang turun dari langit itu, warnanya gelap kemerahan.”
Aku mengekor, berdiri di belakang ibu, dan di bawah langit terbuka, di depan sana, hujan berjatuhan dengan air berwarna gelap kemerahan.
”Mungkin hujannya bercampur debu,” ujarku lagi.
”Bukan, bukan itu.”
Petang itu hujan terus turun sampai malam. Sedikit reda, menderas lagi. Begitu beberapa kali. Hingga esok paginya, tanah-tanah menjadi gembur, pohon-pohon beraroma basah, dan setiap benda di bawah atap jadi berembun. Selepas kami sarapan, ibu tergopoh-gopoh membawa ember berisi air yang hari lalu ia letakkan di bawah jemuran dan lupa tidak dibawa masuk.
”Kau lihat airnya, kotor dan kemerahan,” ucap ibu cepat-cepat sambil menciduk air dalam ember dengan telapak tangannya, lalu mendekatkan ke hidungnya, ”dan baunya anyir,” lanjut ibu.
”Mungkin kecipratan air dari talang, jelas saja kotor. Mungkin di atap ada bangkai tikus atau apa,” aku mencoba merangkai kemungkinan.
Tapi ibu tetap menyangkal dengan wajahnya yang cemas, ”Bukan, bukan itu.”
”Lalu, maksud ibu apa?”
”Pagebluk, tak lama lagi bakal muncul pagebluk,” serunya sambil mengeloyor ke arah dapur. Meningalkan ember berisi air hujan di sisi meja makan.
Bapak yang masih asyik menyantap sarapannya mendadak berhenti mengunyah, ”Jangan ngomong yang tidak-tidak. Minta saja sama Gusti Allah biar kita semua sehat,” ungkapnya.
Usai sarapan, dengan langkah terpincang-pincang akibat penyakit kencing manis, bapak mengamati air dalam ember yang dibawa ibu, lantas mengendusnya, bapak tidak berkomentar apa-apa, tapi wajahnya menyiratkan kecemasan. Layar yang sama dengan wajah ibu.
Kejadian itu berlangsung genap dua bulan silam.
Beberapa hari selepas ibu menyinggung soal pagebluk, mendadak kampung kami ribut, sebab dalam sehari tiga orang tetangga kami meninggal bersamaan, dan mereka satu keluarga. Mereka baru tiba dari liburan selama sepekan di luar kota. Menurut omongan demi omongan, sebelum meninggal, sore harinya mereka mengeluh mual, malamnya panas tinggi, dan pagi harinya mereka sudah tidak bernyawa. Pagi hari berikutnya, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan mereka, mendadak dikabarkan sakit, lalu malamnya meninggal. Beruntun, dimulai dari tetangga paling dekat, beberapa orang yang tandang ziarah, sampai mereka yang tak tahu apa-apa. Hampir tiap hari, orang di kampung kami ada yang meninggal. Hingga orang-orang tak berani keluar rumah.
Di tivi-tivi disiarkan, kejadian serupa juga melanda berbagai tempat di belahan bumi, dan konon bakal menyebar ke seluruh muka bumi. Pemerintah mengumumkan, ada makhluk tak terlihat yang mengawasi para manusia. Makhluk-makhluk itu akan membunuh siapa saja yang masih nekat keluyuran di luar rumah. Barang siapa berjalan lebih dari sepuluh langkah keluar rumah, artinya ia telah siap mati. Pagebluk sudah datang. Mereka yang sakit di pagi hari, akan meninggal pada malam hari. Mereka yang sakit pada malam hari, akan meninggal di pagi hari. Dan seterusnya.
Dalam waktu kurang satu bulan, kampung kami telah menjadi kampung mati. Seperti di kampung-kampung lain. Seperti di kota-kota lain. Jalan-jalan menjadi lengang. Sekolah-sekolah diliburkan. Rumah-rumah ibadah kosong melompong. Warung-warung tutup. Di kampung kami, satu-dua orang dengan hati was-was nekat melangkah menuju ladang-ladang untuk meramban bahan makanan. Sebab pasar-pasar tak lagi buka. Orang-orang yang keluarganya ditimpa pagebluk menjadi sangat sedih dan semakin sedih, sebab mereka akan dijauhi. Bila ada keluarga sakit lalu meninggal, mereka akan mengurusnya sendiri, lalu memakamkannya di pekarangan depan atau belakang rumah. Tanpa pelayat. Tanpa iringan pengantar.
Dalam waktu sekejap, seolah-olah setiap rumah telah menjadi makam bagi penghuninya sendiri. Beberapa orang yang tak punya sanak keluarga dan tak kuat iman, lebih memilih mengakhiri semua dengan menggantung leher sendiri. Hingga aroma busuk menguar dan mengganggu tetangga sekitar. Bila ada tetangga yang bermulia hati, mereka akan membantu mengurus dan menguburkan. Dan seringkali, pada hari-hari ke depan, silih mereka yang dikuburkan.
Orang-orang menangis, suara mereka mendengung dari satu dinding ke dinding lain. Dari satu rumah ke rumah lain. Seperti bersahutan.
***
Genap dua bulan, selepas hujan yang menurut ibu berwarna kemerahan itu, bapak ambruk. Kami—aku dan ibu, sudah tahu bagaimana keluarga kami akan berakhir. Bapak ambruk di malam hari, dan esok paginya, ia sudah tiada. Kami mengurus jenazah bapak dalam diam. Dan jenazah itu kami kuburkan di pekarangan belakang, di bawah naungan pohon kepayang. Hampir seharian ibu tergugu di samping gundukan tanah di belakang rumah. Seperti merenung. Seperti menginsyafi diri.
”Zaman apa ini, zaman apa ini, zaman apa ini,” ucap ibu berulang-ulang, semakin lirih, hingga ia tampak seperti berbisik, berkomat-kamit.
Semenjak kepergian bapak, ibu tidak doyan makan. Ia lebih banyak diam. Wajahnya putih pudar, dan tingkah lakunya gamang. Aku seperti melihat sebuah ilham turun ke batok kepalanya, hingga tingkahnya menjadi sedikit aneh. Aku mengira, ibu mulai ditimpa stres.
Hari terus berjalan dan orang-orang terus mati bergantian seperti ayam keracunan. Aku dan ibu seperti tengah bersiap, menunggu giliran sang maut datang, mengetuk pintu rumah kami. Semenjak kematian masal merenggut orang-orang di kampung kami dan di banyak tempat lain, hujan tak lagi turun. Hingga suatu pagi, mendung mendatangi kami seperti mengirim pertanda lain. Matahari tak tampak muncul. Seharian langit gelap. Namun hujan tidak juga turun. Seperti ada sesuatu yang menahannya.
Dari balik korden, ibu bersisik, ”Yang lain akan segera tiba… yang lain akan segera tiba… ”
Aku tidak menanggapi. Mendung gelap itu terus berlangsung selama beberapa hari, menyentuh pekan. Dan hujan tak juga turun. Aliran listrik serentak mati. Dan udara menjadi begitu dingin. Sangat dingin. Ketika langit menjadi gelap dari hari ke hari, ibu jadi suka berdiri berlama-lama di balik jendela, tak peduli pagi, siang, sore, bahkan malam. Ibu bisa tahan berdiam dalam hitungan jam, seperti tengah membaca sesuatu. Hingga suatu hari, kabut menipis dan hilang perlahan. Langit menjadi begitu terang. Terang yang sedikit berbeda. Aku melihat ibu berlari-lari kecil menyongsong pintu, lalu membukanya. Seperti membuka jalan napas untuk rumah kami yang pengap.
Di pekarangan depan, wajah ibu mendongak ke ketinggian. Cahaya kekuningan menimpa seluruh wajahnya. Mendadak ia terdiam lama, lalu menangis tersedu-sedu, seraya berseru, ”Matahari terbit lagi… Matahari terbit lagi… Dari barat… Dari barat….”
Akhir-akhir ini ibu memang tampak aneh. Aku tak ingin memercayai kata-katanya. Tapi aku merasakan seluruh tengkukku berdiri. Dadaku berdebaman. Ada sesuatu yang mengentak di kedalaman. Aku berjalan gegas menyeberangi pintu. Menyongsong ibu. Dan dari lengkung langit bagian barat. Aku melihat matahari memancarkan cahaya agung.
Jam berapakah ini? Apakah ini fajar, atau senja? Ibu masih saja tersedu sambil berteriak-teriak. Matahari terbit lagi. Dari arah barat.
Malang, 2022
***
Mashdar Zainal, lahir di Madiun 5 Juni 1984, suka membaca dan menulis puisi serta prosa. Tulisannya terpercik di berbagai media. Buku terbarunya Kartamani, Riwayat Gelap dari Bonggol Pohon, Penerbit Basabsi, 2020. Kini bermukim di Malang.
***
(10)
Toko Kelontong Koh San

Oleh: GABRIELLA KUSUMA, 9 April 2023
Toko itu adalah satu-satunya toko kelontong yang dimiliki oleh keluarga Tionghoa di antara deretan toko keluarga etnis lain. Orang-orang memanggil paman pemilik toko sebagai Koh San, tak peduli apakah mereka seumur anak si Kokoh atau seumur cucunya. Dia adalah laki-laki separuh baya yang suka tersenyum, dengan rambut hitam dari semir saset yang juga dia jual.
Koh San, Cik San, dan ketiga anak mereka juga menjadi satu-satunya keluarga keturunan Tionghoa di daerah ini. Padahal, lima puluh tahun yang lalu, daerah itu masih bisa dibilang Pecinan Mini. Setelah pendatang lain datang, lama-kelamaan keluarga Tionghoa yang sudah beberapa generasi tinggal di sana memutuskan untuk pindah.
Ayah Koh San berasal dari Tiongkok, tepatnya Shanghai. Dia datang naik kapal menuju kota ini, bersama dengan tiga ratus lebih perantau lain. Tidak semuanya berhasil mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagian kembali ke Shanghai, sebagian menyebar ke daerah lain, sebagian sudah meninggal, dan hanya segelintir saja yang bisa menikah, menetap, dan meninggalkan legasi untuk keturunannya.
Kalau ditanya tentang tombak yang tergantung di dinding toko, Koh San dengan semangat ’45 akan bercerita tentang kemampuan bela diri ayahnya. Katanya, ayahnya lebih keren dari Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat, juga Andy Lau dijadikan satu. ”Tapi masih belum bisa menandingi Bruce Lee, ya!” kelakar Koh San tiap kali anak-anak kompleks datang untuk jajan.
Selama bertahun-tahun, toko kelontong Koh San sudah membantu ratusan hingga ribuan orang. Mulai dari yang membutuhkan barang, menumpang berjualan, sampai pinjam uang. Koh San sangat baik, kata ibu-ibu yang bergosip di depan tukang sayur. Laki-laki itu tidak pelit, tidak cadel, tidak rewel kalau diajak tawar-menawar, dan ingat semua wajah orang yang datang ke tokonya.
Saking ingatnya, banyak orang muda yang kuliah atau kerja di luar kota yang kaget ketika mampir ke toko Koh San. Si Kokoh, dengan senyum lebar dan kerut ramah di sekitar mata sipitnya, akan menyapa orang-orang ini. ”Wah, sudah sukses kamu, ya!” atau ”Wah, sudah lama enggak ke sini, ya!” adalah kalimat-kalimat yang sering sekali terdengar di toko itu.
Aku yang kembali selama liburan kuliah dari Australia pun disapa dengan sangat ramah. Aku ikut tersenyum ketika Koh San bertanya berapa banyak kanguru yang sudah kulihat, apakah koala memang selalu memeluk pohon, dan memintaku bercerita apa saja kegiatanku di sana.
”Ini permen kesukaan kamu masih Koh San jual, ya,” katanya pula, menunjuk pada sestoples permen merah jadul yang dulu sangat kusukai. ”Sekarang harganya naik, ya. Naik 500 perak. Kalau beli lima, gratis satu, ya.”
Hari itu aku pulang membawa dua lusin permen yang kubagikan kepada anak-anak kecil yang sedang bermain di dekat situ.
Sayangnya, sekarang ini toko Koh San kian sepi. Tokonya memang terlihat sangat berbeda, dengan gantungan lampion kertas merah, tulisan Mandarin yang artinya keberuntungan, tombak di dinding, dan pernak-pernik khas Tiongkok lainnya.
Mungkin karena persaingan, ya, begitu kata Koh San kalau menanggapi orang yang prihatin. Dengan pertumbuhan lima toko kelontong lain di situ, banyak orang yang memutuskan untuk membeli di sana. Barang-barang titipan yang sebelumnya hanya dijual di toko Koh San pun berpindah ke toko pesaingnya.
Anak-anak kecil masih suka datang ke situ karena Koh San menjual es dan peralatan tulis paling murah. Barang-barang yang berasal dari China memang biasanya lebih murah, dan si Kokoh paham betul akan hal itu. Dia mendatangkan banyak barang dagangan tersebut dengan kontainer. Anak-anak senang sekali kalau kiriman kotak pensil warna-warni, tas kain, penghapus wangi, atau buku bergambar tokoh keren datang.
Tiap pagi Koh San juga menyiapkan es bon-bon yang akan membeku sempurna saat jam pulang sekolah tiba. Bukan es bon-bon buatan pabrik, tapi resep keluarga yang sudah dijual sejak ayahnya yang dari Shanghai itu membuka toko. Resep asli Tiongkok katanya. Kadang, dia suka makan es bersama anak-anak yang datang. Berhubung hawa memang panas juga lembap, Koh San pun lebih suka mengenakan kaus kutang.
Semuanya itu tak pernah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Namun, dalam waktu semalam, banyak pria yang datang dan meminta Koh San untuk berpakaian lebih rapi. Mereka menyebut-nyebut pengunjung toko itu banyak anak kecil dan perempuannya. Kaus kutang dan celana pendek bukan penampilan yang pantas untuk diperlihatkan. Menolak untuk terlibat dalam masalah, si Kokoh meminta maaf dan berjanji akan mengenakan baju yang tidak terlalu ”mengganggu”.
Meski demikian, pengunjung tetap menurun. Tidak ada yang tahu kesalahan apa yang diperbuat pemilik generasi kedua toko kelontong itu. Orang-orang hanya berubah tidak menyukainya. Titik. Tidak ada koma, titik koma, atau tanda baca lain yang menjelaskan akar permasalahannya.
Mereka jadi menjauhi toko Koh San, menolak untuk berbelanja di situ. Jajanan yang dijual, termasuk es bon-bon aneka rasa yang tak laku lagi, dituduh mengandung unsur tak jelas. Para orangtua menyuruh anak-anak mereka untuk berhenti datang. Rasa percaya dan kekeluargaan yang sudah terbina belasan tahun runtuh begitu saja hanya karena praduga tanpa alasan.
Para ibu di kompleks mulai membicarakan Cik San dengan kata-kata yang menyudutkan. Kata mereka si Cicik tidak seramah dulu. Tatapannya tajam memandang pengunjung yang datang. Senyumnya juga terasa dipaksakan. Mau pinjam uang juga lebih susah.
Untuk beberapa waktu, hanya itu terus digosipkan. Koh San harusnya tahu apa yang dikatakan para tetangga tentang keluarganya mengingat kompleks ini tidak besar dan hubungan antartetangga bisa dibilang guyub. Tapi tak pernah sekali pun mereka membalas. Meski Cik San terkesan menjaga jarak, dia tetap melayani pembeli dengan baik.
Kadang kupikir Koh San dan keluarganya terlalu baik kepada orang lain. Dia tak segan mendahulukan orang asing dibandingkan kepentingan pribadi. Sampai akhirnya puncak masalahnya terjadi beberapa bulan kemudian, saat Imlek tiba.
Keluarga Koh San tidak pernah neko-neko dalam merayakan hari tahun baru China. Mereka tidak memanggil barongsai atau liang liong untuk memeriahkan perayaan. Tidak ada juga petasan atau kembang api. Mereka hanya mengundang keluarga untuk makan-makan di rumah, mengunjungi sanak saudara, atau sembahyang di klenteng. Tak ada yang berlebihan. Bahkan, bisa dibilang, Koh San cenderung merayakan Imlek dengan diam-diam.
Sebenarnya tidak pernah ada larangan baginya untuk merayakan Imlek sesuai kebiasaan orang Tiongkok. Tapi tentu dia sadar bahwa dia adalah minoritas. Dan memasang kembang api atau memanggil barongsai akan sangat mengganggu para tetangga, sekalipun itu adalah bagian dari tradisi ribuan tahun yang menjadi bagian dari jati dirinya.
Saat Imlek kemarin, tahu-tahu datang lagi sekelompok pria. Saat pintu dibukakan, mereka langsung masuk dan meminta Koh San menghentikan semua kegaduhan yang dia buat. Rupanya, beberapa keponakan yang datang sedang menyalakan kembang api tangan di halaman belakang. Anak-anak itu tertawa sambil mengayunkan kembang api ke satu sama lain, yang dianggap berbahaya oleh para tetangga.
”Bahaya apa, ya?” tanya Koh San. ”Kan ini mainnya di halaman belakang saya, ya? Di situ juga sudah ada ember air untuk mematikan kembang apinya, ya.”
Para tamu tak diundang itu tidak mau tahu. Mereka tidak ingin ada sesuatu yang mengusik keharmonisan kompleks perumahan mereka. Mereka juga tidak suka dengan bau-bau dupa yang ditancapkan di depan altar keluarga Koh San. Berhubung sejak malam Imlek dan hari Imleknya, bau dupa itu terus saja menguar keluar rumah, mencapai rumah-rumah di sekitarnya.
Salah seorang dari bapak-bapak itu merokok dan menyebarkan abunya ke mana-mana, karena dia memperhatikan seisi ruang tamu Koh San seakan dia adalah tamu betulan. Tidak ada yang merokok di keluarga Koh San, baik dia, kedua anak laki-lakinya, maupun saudara-saudara yang tengah berkunjung. Anak perempuan Koh San satu-satunya sampai terbatuk-batuk menghirup asap.
Si bapak ini kemudian memandang menu-menu yang tersaji di meja makan bundar besar dan terkesiap ngeri saat melihat kepala babi panggang. Sambil menyumpah-nyumpah, dia menunjuk-nunjuk Koh San tepat di muka. Di pengujung sumpah serapahnya, dia ingin Koh San pergi dari daerah itu.
Cerita tentang apa yang terjadi menyebar seperti kobaran api. Tak perlu waktu lama hingga seluruh kompleks tahu apa yang terjadi pada keluarga Koh San saat Imlek malam. Hampir seminggu setelah Imlek, aku diberi tahu oleh ibuku yang juga merupakan salah satu ibu-ibu penggosip di depan tukang sayur. Belum selesai ibuku bercerita, aku langsung pergi ke toko Koh San.
Tak ada lagi Kokoh yang selalu tersenyum kepada pengunjung. Tak ada lagi Cicik dan ketiga anak mereka yang suka membantu di toko. Pintu harmonika tertutup rapat menyambut pengunjung yang datang, dengan kertas A4 tertempel di sana. Kertas itu bertuliskan, ”Tutup Sementara”. Tak lebih, tak kurang. Hanya satu kalimat, dua kata, tanpa informasi lainnya.
Satu minggu berubah menjadi satu bulan. Aku harus kembali ke Australia untuk menyelesaikan studi dan dalam hati berharap saat pulang nanti aku akan disapa ramah oleh Koh San lagi. Akan tetapi, rupanya satu bulan berubah menjadi tiga bulan, enam bulan, dan sembilan bulan dengan cepat. Tak ada tanda-tanda toko kelontong itu akan terbuka lagi.
Banyak yang mencibir keluarga itu kemudian. Mereka menyalahkan Koh San yang terlalu sensitif, yang salah mengartikan nasihat baik para tetangga, dan malah kabur. Sebagai minoritas, sudah tentu dia harus mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas, kan? Kalau apa yang dia lakukan mengganggu tetangganya, tentu itu karena yang dia lakukan melenceng dari kebiasaan masyarakat di kompleksnya.
Sejak saat itu, aku selalu bertanya-tanya. Seandainya kami para warga yang tidak terganggu dengan keberadaan keluarga Koh San melakukan sesuatu, apakah sekarang toko kelontong itu masih menjadi bagian dari kami?
***
Gabriella Kusuma yang lahir di Surabaya 28 tahun yang lalu adalah seorang penikmat cerita yang suka menulis di waktu luang. Berprofesi sebagai content writer, dia hidup dikelilingi kata-kata dan cerita—yang merupakan lebih dari sekadar hobi baginya.
Polenk Rediasa, lahir di Tambakan, Buleleng, 18 Maret 1979. Perupa dengan nama asli I Nyoman Rediasa ini menjadi dosen seni rupa di Universitas Ganesha, Singaraja. Ia menempuh pendidikan seni mulai dari SMSR Denpasar, ISI Denpasar, hingga pascasarjana Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar. Selain melukis di atas kanvas dan kertas, Polenk juga menggambar di atas tubuh (body painting).
***
(11)
Turun Tanah

Oleh: MOH. TSABIT HUSAIN, 8 April 2023
Kau diarak ke rumah Pak Kalebun dengan wajah lebam. Warga mencacimu dengan sumpah searapah. Beberapa saat kemudian, ibu dan paman datang. Melihatmu dengan kondisi tak berdaya di hadapan massa, kau seperti mengurap tahi ke wajah mereka. Bedebah!
“Apa yang telah kau lakukan?”
Plak!!
Gamparan tangan paman mendarat di pipi. Kau menunduk menahan perih di wajah dan hati, setelah paman bilang bahwa kau bukan keponakanya lagi. Air mata ibu mengucur. Deras. Melihat anaknya sendiri penuh lebam dan luka. Baju yang kau kenakan pun koyak-koyak. Darah segar menetes dari sudut bibirmu. Tiba-tiba, kau merasa bumi berputar. Kepalamu berdenyut-denyut sedang kau duduk dengan tangan terikat di halaman rumah Pak Kalebun, di bawah terik yang menyengat.
Paman beranjak meninggalkanmu. Punggungnya menjauh dan hilang dari pandangan. Ibu meronta ketika ditariknya, paksa. Dia mendengar pengakuan warga kalau kau telah membunuh seorang pemuda seusiamu.
Kau bukan keponakanku lagi!!
Kalimat itu terngiang-ngiang. Melebihi umpatan dan amarah warga. Paman tidak mengakuimu lagi sebagai bagian keluarga sedangkan ibu merasa malu walau dia tak tega melihat anaknya sendiri babak belur. Kau bertanya pada diri sendiri. Apakah membunuh seorang pemuda pengganggu tunangan orang lain itu salah? Dia bahkan berani menyentuh dan menyeretnya ke tempat sepi. Dia mau merenggut harga diri Mariani, tunanganmu. Mau diletakkan di mana harga dirimu sebagai seorang lelaki jika kau biarkan orang lain menodai gadis yang akan kau nikahi beberapa bulan lagi.
Ango’ pote mata etembang pote tolang.
Sebab itu, kau menantangnya beradu. Dia tidak membawa apa-apa sedang kau membawa celurit pusaka milik ayahmu. Celurit yang dia dapatkan dari salah seorang gurunya sebab pengabdiannya yang tulus. Pertarungan yang tidak sebanding terjadi. Tak butuh waktu lama, kau berhasil membacok dada dan kepalanya. Belum puas, area selangkang juga menjadi sasaran celurit yang berlumur darah itu.
“Mengapa kau membunuhnya?”
Kau tak menyahut. Dadamu bergolak. Warga tak tahu kalau lelaki itu kerap mengganggu tunanganmu. Baru pagi tadi, kau menguntitnya saat Mariani mau pergi ke pasar. Kau memergokinya saat dia menyekap mulut Mariani dan menggiringnya ke tempat yang sepi. Jauh dari jalan yang biasa dilalui orang-orang.
Kemudian, warga membawamu ke kantor polisi. Wajah mereka bagai api menjilat jerami. Aroma benci menguar dari mulut mereka sebab lelaki sebaya yang kau bunuh adalah anak seorang sesepuh kampung yang amat mereka segani. Kau tertawa ketir. Anak pemain sapi karapan atau anak sesepuh kampung, apa bedanya? Harga diri tak memandang siapa pun untuk dibela. Begitu pula celurit pusaka ayahmu. Sampai kau mengingat kembali masa kecil yang pernah ibumu ceritakan, saat turun tanah atau toron tana digelar di depan rumah, kau memilih mengambil tali tambang sapi karapan dan celurit daripada kitab suci, tasbih dan songkok yang tertata rapi di atas gaddang.
***
Kau menyiapkan bubur untuk anak-anak kecil yang kau undang pada turun tanah anakmu. Mereka akan datang sore nanti, ketika matahari mulai menurunkan suhu panasnya. Kau bersiap-siap sejak pagi. Bubur telah dituang dari wajan besar ke atas nampan. Tinggal mencampurnya dengan koin lima ratusan.* Dengan itu berharap rejeki sang anak akan lancar. Dan anak-anak yang memakan bubur itu pelan-pelan akan gembira setelah menemukan mulutnya tersumpal bubur berisi koin.
Kau mengambil gaddang. Di atasnya, kau tata rapi tasbih, kitab suci mini, songkok putih, jagung, cermin, sisir, pakaian, celana, sarung, uang seribu sampai sepuluh ribu, alat tulis dan dadamu bergetar saat suamimu meletakkan tambang sapi karapan beserta celurit mini bersisian dengan benda-benda lainnya.
“Untuk apa kau meletakkan tali tambang dan celurit di dalamnya?” tanyamu.
Suamimu tak menggubris. Dia mengambil rokok yang diletakkan di atas meja. Asapnya mengepul. Dia menyepuhnya dan berlalu. Meninggalkan aroma hampa sama seperti asap yang membumbung di udara. Kau mengikuti suamimu. Dia masuk ke kamar dan mencium anak lelaki usia dua tahun. Anak yang akan diberkati dengan tradisi warisan leluhur. Berharap dia menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi siapa saja utamanya bagi kedua orang tuanya.
“Mas, kau belum menjawab pertanyaanku!”
Anak pemain sapi karapan atau anak sesepuh kampung, apa bedanya? Harga diri tak memandang siapa pun untuk dibela. Begitu pula celurit pusaka ayahmu. Sampai kau mengingat kembali masa kecil yang pernah ibumu ceritakan, saat turun tanah atau toron tana digelar di depan rumah, kau memilih mengambil tali tambang sapi karapan dan celurit daripada kitab suci, tasbih dan songkok yang tertata rapi di atas gaddang.
Mata suamimu melotot. Kau bergidik melihatnya. Sejak kau menikah, belum pernah wajahnya semerah itu dengan mata membola sekalipun percekcokan kerap kali terjadi dalam rumah tangga kalian.
“Apa yang perlu kujelaskan padamu?”
Kau mendekat lalu menariknya keluar, khawatir anakmu terbangun dari tidur.
“Apa maksudmu meletakkan tali tambang dan celurit di atas gaddang, bersisian dengan benda-benda yang telah disarankan K. Samaon?”
“Itu tali biasa. Bukankah petani butuh tali dan celurit untuk hasil panen dan rumput bagi ternak mereka?”
“Tapi itu tali tambang sapi karapan. Dan celurit itu bukan celurit…”
“Diam!!” bentak suamimu. Kali ini kau berani menatap matanya. “Kau jangan ikut campur. Tetua kampung itu hanya menyarankan. Selebihnya kita yang menjalankan. Awas jika kau buang benda yang kuletakkan di atas gaddang itu!!” ancamnya dan beranjak masuk ke kamar.
Kau mengelus dada. Sebulir air mata menetes di pelupuk mata namun segera kau usap dengan punggung tangan. Sejak pertama kali menikah, kau sudah tidak suka dengan lelaki pilihan ayahmu itu. Tapi apa boleh buat, perempuan yang menolak pilihan orang tua akan terancam tidak laku. Tidak akan ada yang mau meminang apalagi mempersunting.
Saat ini, kau mengkhawatirkan turun tanah anakmu. Kau khawatir dia akan mengambil tali tambang karapan dan celurit. Kau tak mau dia memasuki dunia perpacuan sapi dan carok, kelak, ketika dia besar nanti. ** Bagimu, leluhur mewariskan tradisi bukan hanya sebagai corak suatu daerah yang dibanggakan, melainkan doa. Benda apa pun yang akan di ambil anakmu nantinya adalah pertanda akan jadi apa dia kelak.
Waktu yang ditunggu tiba. Setelah azan asar berkumandang, banyak anak-anak kecil berdatangan. Kau persilahkan mereka duduk bersila di atas tanah tanpa tikar. Di tengah-tengah mereka enam nampan besar berisi bubur koin sudah terhidang. Mereka duduk melingkar. Mereka diperbolehkan menyantapnya setelah anakmu mengambil benda-benda yang sudah disediakan di atas gaddang.
Kau keluar membawa gaddang itu dan suamimu mengikuti dari belakang sembari menggendong putera kesayangannya yang baru bisa duduk. Anak yang baru bisa duduk harus ditajinin melalui turun tanah.
Suamimu mendudukkannya di tanah, di depan gaddang. Dari kejauhan, tiga kerabatmu memegang sapu lidi yang akan dipecutkan pada anak-anak yang hadir setelah makan bubur sebagai harapan anak kalian kokoh ketika berdiri dan tidak tersandung ketika berjalan. Sebuah nilai agar ia kelak berada pada jalan yang lurus meski terjal. Dan semua itu membuatmu gelisah karena tali tambang dan celurit ada di dalamnya.
Suamimu memberi sambutan. Kemudian, sebagai tanda dimulainya acara, anakmu akan dikurung menggunakan kurungan ayam. Orang-orang berebut untuk melihat. Mereka menebak-nebak, kira-kira apa yang akan anak kalian ambil. Pertama, dia tertarik pada sisir. Orang-orang bertepuk tangan. Kalau anak perempuan yang mengambil sisir, itu pertanda dia suka kebersihan. Tapi, kalau anak laki-laki pertanda dia akan tumbuh sebagai orang yang cemerlang.
Kedua kalinya, anakmu ragu-ragu. Tangannya melayang-layang antara mengambil songkok, celurit dan tali tambang di sisinya. Tapi suamimu, dengan senyum kebanggaan, mengarahkan anak itu pada celurit dan tali tambang sapi karapan.
“Mas, apa yang kamu lakukan!” bentakmu sembari membuka kurungan itu. Kau membuang celurit dan tali tambang sapi karapan itu ke tanah.
“Kenapa kau mengahalanginya. Dia mengambil sendiri!”
“Aku tidak buta. Kau menuntunnya mengambil celurit dan tali tambang itu. Apa kau ingin menggariskan nasibnya di tanganmu? Apa kau ingin dia hidup dalam dunia perpacuan sapi dan carok sepertimu?”
Plak…
Tangan suamimu mendarat di pipi. Kau menangis. Kerabat serta beberapa orang coba melerai kalian. Di kampung ini, suamimu terkenal sebagai bajing atau preman kampung yang menjaga keamanan kampung ini. Tak ada yang berani melawannya dengan celurit pusaka yang dimilikinya.
“Jaga bicaramu. Itu tradisi. Carok tidak seperti yang kau bayangkan. Itu pembelaan kehormatan!!”
“Kehormatan? Apa membunuh merupakan sebuah kehormatan? Sejak kapan? Itu penistaan diri manusia atas kuasa Tuhan!!”
Kau beranjak ke dalam setelah mengambil anakmu yang sekarang menangis dalam pelukan. Kau mengunci diri di dalam kamar. Di luar, suamimu menggedor pintu namun tak kau hiraukan. Kau menciumi pipi anakmu. Penuh kasih sayang sembari berharap garis tangannya tidak seperti yang didinginkan ayahnya.
***
Kau pikir perceraianmu dengan suamimu tak akan meninggalkan apa-apa. Meski sekarang kau berhasil mendidik anakmu jauh dari dunia perpacuan sapi, entah darimana dia memperoleh celurit itu. Celurit yang membinasakan tuannya sendiri.
***
Moh Tsabit Husain merupakan santri di Pondok Pesantren Annuqayah asal Bukabu, Ambunten, Kabupaten Sumenep, Jawa TImur. Kuliah di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) . Aktif di KCN Lubselia dan Pendamping bilik F/12 Lubangsa.
***
Catatan:
– Ango’ pote mata etembang pote tolang = peribahasa Madura; lebih baik putih mata daripada putih tulang.
– Pak Kalebun = kepala desa
– Gaddang = sejenis nampan yang terbuat dari rotan
– Tinggal mencampurnya dengan koin lima ratusan (*) = sekarang, koin itu tidak diletakkan dalam bubur lagi. Khawatir akan tertelan jika anak-anak memakannya.
– Kau tak mau dia memasuki dunia perpacuan sapi dan carok, kelak, ketika dia besar nanti (**)= dalam novel Damar Kambang karya Muna Masyari diceritakan bahwa perpacuan sapi disertai taruhan seisi rumah termasuk orang-orangnya. Namun sekarang, hal seperti itu sudah tidak ada lagi.
***
(12)
Biografi Luka

Oleh: YUDITEHA, 2 April 2023
Saki pulang nyekar. Seharian dia habiskan waktu di makam Jejawu. Dia banyak merenung perihal sahabatnya itu, yang semasa hidup memang sering bersamanya. Bahkan setiap kali Saki melukis, Jejawu hampir selalu menemani. Namun setelah Jejawu meninggal, keadaannya menjadi lain.
Dulu setiap Jejawu di dekatnya, Saki merasa terbebani harus menjaganya. Keadaan mental Jejawu yang tidak normal penyebab Saki punya pemikiran seperti itu. Namun, kepergian putra pertama Luwika—Demang Sukodono—itu, membuat Saki menyadari sesuatu, dia tidak adil terhadap Jejawu. Saki pikir, dulu dia dan Jejawu akrab karena nasibnya hampir sama. Meski beda tingkatan, Saki juga punya kekurangan. Setengah dari wajahnya terdapat kerutan kasar melintang hingga membuat wajahnya tampak aneh.
Selain itu, Saki sadar dirinya miskin. Menjadi pelukis, sebenarnya hanya pelukis biasa yang dia sendiri tidak yakin ada orang yang peduli. Saki merasa justru Jejawu-lah yang peduli. Buktinya, setelah Jejawu tiada, belum ada orang yang mau dekat lagi dengannya.
Karena itu Saki merasakan, kepergian Jejawu membuatnya kesepian, bahkan karenanya dia ingin pergi, meninggalkan Kademangan Sukodono. Saki memutuskan akan hijrah ke Sala. Selain untuk melupakan kesepiannya, di tempat itu dia berharap ada orang yang mau berteman dengannya, atau setidaknya ada yang berkenan menghargai lukisannya, selayaknya Jejawu yang tulus menghargainya. Terlebih kebetulan saat itu di Sala sedang ada perayaan keraton. Keramaian itu membuat Saki punya harapan.
Setelah seharian berjalan, sampailah Saki di gapura masuk Kademangan Plupuh. Saki memperkirakan dirinya baru menempuh setengah perjalanan. Untuk sampai di Sala, dia masih melintasi beberapa sungai. Namun karena saat itu menjelang malam, Saki memutuskan mencari tempat istirahat. Permukiman Plupuh sudah terlihat dari banyaknya obor menyala.
Sebelum Saki memasuki permukiman, penglihatannya dikejutkan sosok berwarna putih di pinggir jurang. Awalnya Saki takut, tapi rasa penasarannya begitu besar, lantas dia memberanikan diri mendekat.
”Perempuan?” gumamnya.
Ketika jarak semakin dekat, Saki yakin sosok itu memang seorang perempuan. Samar Saki mendengar perempuan itu menangis. Karenanya Saki curiga, perempuan itu akan melakukan bunuh diri. Saki tidak ingin terlambat mencegahnya. Perempuan itu mundur dua langkah, ancang-ancang melompat. Begitu perempuan itu maju, Saki menyambarnya. Perempuan itu meronta sembari berteriak meminta dilepaskan. Saki tidak menghiraukan, dan menjauhkannya dari bibir jurang.
Saki melepasnya. Perempuan itu berlari menuju jurang lagi. Saki tidak membiarkannya.
”Tak ada gunanya hidup! Lepaskan aku!” teriak perempuan itu.
Saki tidak menanggapi.
”Jangan sok pahlawan, kamu!”
Saki tetap diam, kemudian kembali melepas pegangannya.
”Hai jelek, katakan satu hal mengapa aku tidak boleh mati!”
Saki bergeming.
”Ayo katakan. Tak ada, kan!?”
Saki hanya melihat perempuan itu.
”Yang ada hidup ini asu! Maka biarkan aku!” ucap perempuan itu lalu menjauh.
”Tidak ada kalimat yang sempurna. Sama seperti tidak ada keputusasaan yang sempurna,” sahut Saki.
Perempuan itu berhenti, lantas melihat Saki. Beberapa detik terdiam sebelum bertanya, ”Apa katamu?”
”Tidak ada yang sempurna,” jawab Saki.
Perempuan itu lantas duduk di sebuah batu di bawah pohon trembesi, setelah itu diam. Matanya memerah lalu menangis. Melihat itu Saki mendekat.
”Mengapa kamu ingin melakukannya?” tanya Saki.
Perempuan itu tidak menjawab, tapi tangisnya semakin tersedu-sedu.
”Tidak apa, aku akan menunggu,” ucap Saki sembari duduk pada batu yang lain. Keadaan diam itu membuat Saki menyadari badannya lelah dan butuh istirahat.
”Namaku Sima, anak Demang Pluluh.” Setelah mengenalkan diri, Sima menjawab pertanyaan Saki sebelumnya. Sima juga mengatakan bahwa kecantikan adalah awal bencana. Orang-orang menilai dirinya cantik, karena itu banyak lelaki ingin menjadikannya istri. Dari pendekar hingga orang biasa. Namun, lamaran itu tidak ada yang dia terima. Sima merasa belum ada yang cocok. Setelah itu Sima diam sejenak sebelum akhirnya mengambil napas panjang.
”Lantas?” tanya Saki penasaran.
”Dua orang dari mereka merencanakan sesuatu.” Saki mendengarkan saksama. ”Mereka tak lebih dari binatang!” lanjut Sima geram.
Saki tak berani menanggapi.
”Dua orang itu memerkosaku bergiliran,” ucap Sima lirih, matanya basah. Hening seperti tiba-tiba menyergap.
”Setelah aku dengar ceritamu,” ucap Saki tidak berlanjut.
”Jadi wajar kan kalau aku ingin mati?” sahut Sima.
Saki melihat Sima, lantas mengangguk pelan.
”Sekarang katakan, aku harus gimana?” tanya Sima.
”Sebelum kujawab, aku ingin bilang sesuatu.” Saki mengatakan, ketika ada orang mendapat hal buruk atas apa yang dipunya, lalu orang itu ingin mati berarti wajar. Namun, justru karena itu hal wajar, ada sebuah nasihat: langkah yang masuk akal adalah tidak menyerah.
”Aku tidak mengerti,” sahut Sima.
”Baiklah, lupakan. Ada dua saran untukmu,” sambung Saki.
”Ya?”
”Pertama, kamu bunuh diri dan aku tak akan menghalangimu lagi. Kedua, lukai dirimu, bisa di wajahmu. Pokoknya jadikan dirimu jelek.”
”Jika kamu jadi aku, apa yang kamu pilih?” tanya Sima.
Saki memandang Sima lekat. Wajahnya sedikit menghitam semu. ”Yang kurasa selama ini adalah luka yang tidak mendapat perhatian orang lain. Kamu bisa lihat sendiri gimana rupaku. Bahkan andai aku yang seperti ini menginginkanmu, tentu kamu tidak mau. Jadi aku akan memilih mengakhiri hidup. Terlebih jika dalam diri sudah ada keinginan menyerah, tak ada jalan lain, satu-satunya cara memang bunuh diri.”
”Baik, aku pikirkan malam ini,” sahut Sima.
”Baguslah. Kebetulan aku lelah, dan ingin istirahat,” ucap Saki.
Mereka berjalan bersisian menuju permukiman sambil melanjutkan obrolan.
”Oya, namamu siapa?” tanya Sima.
Saki memperkenalkan diri, termasuk mengatakan hendak pergi ke mana. Bahkan juga menceritakan bahwa dia seorang pelukis. Jawaban Saki sejenak seperti bisa melupakan apa yang Sima derita. ”Yang kamu bawa itu peralatannya?” tanya Sima.
Saki mengiyakan. ”Juga beberapa lukisan. Siapa tahu bisa kujual di Sala,” jawab Saki.
”Hebat kamu,” sahut Sima.
”Tidak juga. Lukisanku hanya berbahan yang ada di alam. Seperti arang dan berbagai macam getah. Getah daun jati, getah pisang, getah pohon karet dan sebagainya,” terang Saki.
”Yang penting itu lukisan,” sahut Sima. ”Oya, jika mau, kamu bisa bermalam di kademangan. Ada ruang yang biasa untuk tamu. Biar nanti aku bilang rama,” lanjutnya.
Saki menghentikan langkahnya lalu memandang Sima. Sima ikut-ikut berhenti dan memandang Saki. ”Bukan bermaksud tidak menghargai tawaranmu, tapi aku istirahat di tempat lain saja,” sahut Saki.
Sima memandang Saki sebelum akhirnya bicara, ”Baiklah jika keinginanmu begitu.”
Saki tersenyum, lalu meminta maaf kepada Sima.
Sima mengatakan hal itu tidak masalah. Mereka melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di sebuah pertigaan, Saki mengatakan kepada Sima bahwa mereka harus berpisah karena arah jalan mereka berbeda. Sebelum berpisah, Sima sempat mengucapkan terima kasih kepada Saki.
Ketika Sima sampai di kademangan, rupanya telah banyak orang. Sebelumnya mereka bingung, terlebih rama Sima sempat marah-marah karena mereka tidak menemukan keberadaan Sima. Kepulangan Sima membuat semua senang.
Sementara, usai berpisah dengan Sima, Saki sampai di sebuah surau, dan ingin beristirahat di tempat itu. Meski sebelumnya Saki mengatakan sangat lelah, tapi ketika berada di surau itu tidak segera tidur. Saki memikirkan Sima, terutama tentang apa yang dia sarankan. Saki menyesalkan hal itu. Perasaannya tidak tenang.
Untuk mengalihkan gundah, Saki mengeluarkan perlengkapan lukis, lalu mulai melukis. Menjelang fajar Saki baru tidur dan sebentar sudah terbangun karena mimpi buruk. Hampir bersamaan penjaga surau menghampirinya dan mengajak berbincang. Selama perbincangan, perasaan Saki pun masih tidak menentu. Kira-kira tengah hari, Saki melanjutkan perjalanannya.
Sampai di Sala, keriuhan menyambutnya. Gegas dia mencari tempat untuk membuka layanan jasa lukisnya. Selama sepekan, sesekali ingatan Saki masih kepada Sima, tapi dia tidak mendapat kabar apa pun. Pernah dia mendengar berita beberapa kematian di waktu yang hampir sama, tapi dia tidak mendapat keterangan yang jelas. Meski selama itu hanya sedikit orang memakai jasanya, tapi beberapa lukisannya berhasil terjual dan itu cukup membuatnya senang. Sebenarnya lukisan yang dia buat waktu singgah di surau menarik minat banyak orang untuk membelinya, tapi dia tidak ingin menjual.
Waktu telah berjalan sekitar dua pekan. Siang itu, Saki makan di warung pecel. Dari warung itu Saki melihat ada orang mendatangi tempat layanan jasanya. Gegas Saki menyelesaikan makanannya yang tinggal beberapa puluk.
Usai membayar, Saki berlari kecil menghampiri orang itu. Rupanya seorang perempuan yang sedang memperhatikan lukisan. Begitu dekat, Saki baru menyadari ternyata perempuan itu Sima. Saki terpaku, layaknya sedang melihat hantu, hingga dalam beberapa waktu dia bengong. Sementara, perempuan yang rupanya memang Sima masih asyik memperhatikan lukisan. Sima sempat menoleh dan mendapati Saki yang tidak jauh darinya.
”Kukira aku tidak akan bertemu kamu lagi,” ucap Saki.
”Aku justru memilih pernyataanmu yang dulu aku bilang tidak mengerti. Karenanya kita masih bisa bertemu,” sahut Sima.
Setelah itu penglihatan Sima kembali mengarah pada lukisan yang sebelumnya terus diperhatikan, sebuah gambar perempuan dengan luka di wajahnya. Sima kembali menoleh ke arah Saki. ”Tapi aku suka lukisan ini,” katanya sembari tersenyum. Pandang mata dan perkataan Sima membuat Saki salah tingkah. Sejenak kemudian pikirannya mengembara. Satu dari sekian yang ada di benaknya adalah kenangannya ketika bersama Jejawu, karib yang dulu selalu bersama.
***
Yuditeha, penulis tinggal di Karanganyar. Pendiri Komunitas Kamar Kata.
Yuswantoro Adi, lahir di Semarang, 11 November 1966. Pelukis yang sesekali menulis artikel Seni Rupa. Juga seorang pengajar seni rupa untuk berbagai kalangan, utamanya anak-anak. Sudah berkeliling Indonesia untuk memberikan workshop dan atau pelatihan. Dua pameran terakhir pameran di tahun ini adalah pameran ”Seni Agawe Santoso” di Galeri Semarang dan pameran ”Wiwitan Pasa” di Mapolda DIY.
***
(13)
Surat untuk Emak

Oleh: E ROKAJAT ASURA, 1 April 2023
Yth Emak
Mak, apa kabar? Semoga emak sehat. Alhamdulillah sekarang saya sama istri juga sehat. Ya, disehat-sehatkan saja, Mak. Banyak mengeluh juga percuma. Setiap hari dipaksa banting tulang, pulang kerja badan serasa rontok. Maklum, Mak, saya kan hanya lapisan paling bawah dari kehidupan kota besar ini. Mungkin tidak termasuk hitungan siapa pun dan apa pun kecuali pada saat pemilihan umum. Berangkat dari kontrakan berlomba dengan suara kokok ayam, pulang ketika semua orang sudah lelap.
Setiap berangkat kerja diantar istri yang menahan kantuk sehabis mengitari pusat kota setiap malam. Sering kali saat saya pulang, dia sudah tidak ada di rumah. Sama, Mak, mencari tambahan penyambung hidup di kota besar. Mimpinya sih setiap rupiah yang didapat akan ditabung. Siapa tahu suatu hari kelak bisa punya rumah sendiri. Tak apa jauh dari pusat kota pun asal punya rumah sendiri, bisa pulang ke rumah milik sendiri. Tapi namanya hidup ada saja keperluan mendesak, yang menguras tabungan istri saya itu. Sekalipun tak pernah mengeluh, tapi sering membuat saya tak enak hati. Kalau kebetulan ada tambahan penghasilan, saya bayarkan untuk tabungan istri yang terpakai itu. Begitulah kehidupan kami jalani dengan saling memahami atau barangkali dipaksa untuk saling memahami.
Hidup di kota besar ternyata tak semudah ketika saya memimpikannya dulu, yang bisa dilakukan sambil nongkrong di toilet masjid. Pantas saja dulu Emak pernah bilang, daripada mengembara tidak jadi apa-apa mending di kampung sendiri sekalipun kerja serabutan. Tapi dari dulu Emak tahu sendiri, saya tidak biasa kalau diam di rumah tanpa pekerjaan yang jelas. Makanya, Mak, lebih baik alon-alon asal kelakon hidup di kota besar untuk satu mimpi yang bagi kami luar biasa—punya rumah sendiri. Mengembara di kota besar sekalipun tidak jadi apa-apa, saya punya pengalaman yang berharga yang kelak bisa diceritakan pada anak cucu: untuk bertahan hidup harus siap berjuang sampai mati.
Saya hanya buruh kecil di kota besar ini. Hanya remah rengginang dalam pusaran kota besar, yang tak memiliki apa-apa, selain satu suara pada saat pemilihan umum. Hasil dari banting tulang setiap hari, hanya menyisakan lelah di akhir bulan dan rumah tetap saja ngontrak. Rumah itu hanya namanya, Mak, sebab sebenarnya lebih pantas kalau disebut kandang kambing yang sumpek dan sempit. Sebab itulah saya hanya bisa memaklumi ketika untuk menambah penghasilan—syukur-syukur bisa menabung seperti impian kami—istri jualan susu dan daging mentah di Kalijodo. Kata orang, istri saya itu PSK tapi bagi saya tetap saja pahlawan, Mak. Sebab sampai hari ini dia masih tetap sayang dan hormat sama saya, seperti juga hormat dan sayangnya saya pada dia yang tak pernah bisa diukur. Tidak bisa dimungkiri setiap malam istri saya menjual tubuhnya, tapi bukan dirinya. Bukan menjual hatinya. Sebab diri dan hatinya tetap milik saya seutuhnya.
Kalau emak pernah bertemu dengan istri saya dan menanyakan bagaimana bangganya saya, bangga sekali, Mak. Istri saya itu patriot sejati, di dadanya bersemayam jiwa nasionalis. Sebab itulah, istri saya hanya mau melayani lelaki pribumi, pantang mau melayani orang asing. Istri saya juga memahami benar arti Bhinneka Tunggal Ika sekalipun sekolahnya hanya tamat sekolah dasar. Jiwa kebinekaan itu dibuktikan dengan mau melayani lelaki pribumi dari Sabang sampai Merauke, tapi tetap hanya punya satu suami.
Sembah sungkem untukmu, Mak. Saya sekarang bingung sebab istri saya sedang mengandung. Secara de facto tak jelas siapa bapaknya, tapi secara de jure jelas saya suaminya, sebab jelas di mana, dan kapan kami menikah. Kebingungan pertama soal nama, Mak. Saya khawatir kalau dikasih nama terlalu berat, anaknya kelak jadi sakit-sakitan. Kalau dikasih nama sembarang, asal ngasih nama, jangan-jangan anak kami itu calon pemimpin di masa depan. Kemarin ketika menuntaskan hasrat di toilet umum, muncul ide bagaimana kalau diberi nama diawal dengan suku kata ”Har”, sebab sepengetahuan saya nama yang diawali suku kata itu sakti mandraguna. Terpikir bagaimana kalau diberi nama Harmoko. Tapi setelah dipikir-pikir, kok, berbau Orde Baru ya. Di hari lain terpikir mau dikasih nama Harta, dengan harapan semoga saja anak kami kelak punya banyak kekayaan.
Tadi sambil menahan kantuk yang sangat, istri mengusulkan bagaimana kalau jabang bayi ini kelak lahir, beri saja nama Habibie. Tapi terpikir baru saja, Mak, bagaimana kalau anak kami itu kelak otaknya tidak moncer. Masak Habibie, tapi tidak paham matematika. Saya sadar, Mak, otak saya ini kan benar-benar pas-pasan. Pas hanya bisa baca, pas hanya bisa berhitung, selama sekolah benar-benar pas-pasan, setiap ulangan pas untuk nyontek. Saya ralat lagi memberi nama Habibie. Terlalu berat saya pikir. Takut jadi beban untuk anak kami kelak.
Belum selesai memikirkan nama, pikiran saya sudah terpecah lagi. Bagaimana kalau kelak ternyata lahir perempuan? Muncul kemudian ide. Sudahlah kasih saja nama Marsinah. Tokoh perempuan yang punya semangat baja untuk melawan, tak takut mati demi mempertahankan kebenaran. Saya sebagai orangtuanya tentu bangga kalau punya anak perempuan serupa itu.
Lain waktu terpikir kalau anak kami kelak perempuan, akan diberi nama Susi. Emak tentu ingat nama itu tak lain anak kepala desa, satu-satunya perempuan di desa yang terang-terang menyukai saya dan saya juga secara sembunyi-sembunyi menyukainya. Bagi saya, Susi itu sejarah, Mak. Sebab baru sepanjang sejarah di kampung kita ada anak seorang buruh tani yang mencintai anak kepala desa sekalipun secara sembunyi-sembunyi. Sejarah desa kita tentu mencatat siapa sebenarnya yang mengejar-ngejar. Yang jelas bukan saya, Mak, berani sumpah. Tapi Susi yang mengejar-ngejar saya. Suatu hari Susi pernah terus terang, wajah saya ini mirip bintang film kesohor. Lalu dia menyebut satu nama. Sayang waktu itu saya tidak bisa membayangkan seperti apa wajah bintang film kesohor itu, dan mirip sebelah mananya dibanding wajah saya. Susi juga bagi saya penyemangat, sebab dialah satu-satunya perempuan yang membantu saya pergi dari kampung sebab keselamatan saya terganggu dengan ancaman-ancaman hansip. Menamakan putri kami kelak Susi, bagi saya serupa cara yang paling sembunyi untuk memberi jalan pada kenangan.
Itu saja dulu surat dari saya, Mak. Semoga emak tak pernah lupa cara berdoa kepada Tuhan, semoga istri saya nanti melahirkan dengan lancar dan selamat, seperti lancar dan selamatnya istri saya selama melayani laki-laki selama ini. Jangan terlalu dipikirkan tentang apa yang dilakukan istri saya, Mak, sebab di kota besar ini halal dan haram baru sebatas sertifikat.
Salam hormat,
Anakmu.
***
Emak yang selalu saya hormati.
Semoga emak tambah sehat, jangan kayak tetangga saya, Mak, masih muda tapi sudah sakit-sakitan. Katanya sih sewaktu remaja suka jajan, ada juga berita angin kalau sesungguhnya dia itu stres, Mak, ditinggal istrinya minggat gara-gara tak bisa memberi kepuasan. Entah kepuasan apa yang tak bisa dipenuhinya itu. Beruntung saya, Mak, setiap malam istri selalu pulang membawa uang dari hasil jual susu dan daging mentah. Seingat saya belum pernah sekali pun istri saya itu berniat pulang kampung, apalagi minggat gara-gara tidak terpuaskan.
Mak, kemarin istri saya melahirkan, laki-laki, sehat, demikian juga istri saya sehat dan selamat. Kalau diperhatikan bentuk hidungnya, sepertinya enggak jauh beda dengan saya, Mak. Tapi anak kami itu matanya sipit dan dahinya lebar. Ah, siapa tahu kelak bisa jadi Habibie. Senang sekali ketika saya mendengar gurauan suster, katanya anak kami itu calon orang pinter. Sekalipun hanya gurauan, tapi cukup membuat senang saya sebagai orangtuanya. Tapi kebahagiaan itu harus terhenti karena ternyata anak dan istri saya tidak bisa dibawa pulang sebab saya tak bisa melunasi biaya perawatan.
Sungguh bukan sok-sokan membawa istri ke bidan, Mak, tapi saya bingung di kota besar ini ke mana harus mencari dukun beranak. Kata tetangga daripada susah nyari dukun beranak, lebih baik ke bidan saja. Tadinya saya pikir antara bidan dan dukun beranak tidak jauh beda, sama-sama menolong yang akan melahirkan, biayanya bisa dicicil atau dicampur dengan beras dan palawija seperti yang sering saya lihat sewaktu di kampung. Emak masih ingat Ni Rumsiah, dukun beranak di kampung kita, setiap selesai menolong yang melahirkan, pulangnya selalu diberi beras, ayam, kelapa, dan hasil pertanian lainnya sebagai tanda terima kasih, dan jarang sekali dibayar dengan uang.
Setelah anak kami lahir, saya menemui bidan. Aduh, Mak, serasa mendengar petir di siang bolong. Biayanya besar sekali. Sampai hari ini saya belum pernah melihat bagaimana uang sebanyak itu. Saya berusaha memohon kebijakan, dibayar setengahnya dengan harapan bisa mengambil dari uang tabungan istri. Tapi bidan tetap menggeleng, apalagi ketika saya menawarkan jalan keluar, bagaimana kalau dicicil tiap bulan. Bu Bidan malah marah, memangnya tukang kredit katanya. Agar istri bisa cepat dibawa pulang, akhirnya saya memberanikan diri menemui atasan istri saya. Saya malah kena marah, Mak. Memangnya saya ini pengelola panti sosial katanya. Saya masih bingung, Mak, sebab sampai hari ini belum bisa membawa pulang anak dan istri.
Tolong doakan ya, Mak, saya cepat dapat rezeki, supaya bisa membawa pulang anak dan istri, berkumpul di rumah kontrakan untuk saling berbagi cerita. Semoga saja kalaupun terlambat membayar, istri dan anak saya masih bisa dibawa pulang, tidak seperti ngegadai sawah, terlambat bayar sawah kita hilang.
Salam hormat dari saya, Mak.
***
Emak yang selalu saya hormati,
Berkah, Mak, doa kita dikabul Tuhan. Sekalipun shalat sering bolong, tapi doa masih juga dikabulkan. Ceritanya begini, Mak. Waktu saya termenung sepulang dari rumah bidan, datang seorang wanita paruh baya meminta bantuan, menyuruh mengantarkan barang. Barangnya dibungkus kertas koran, seukuran tempat kerupuk. Entah berapa kilo beratnya. Tapi saya pikir anak kecil juga bisa mengangkatnya.
Barang itu diminta dikirimkan ke daerah C, tak terlalu jauh dari tempat praktik bidan. Tentu saja saya mau sebab selain diberi ongkos, juga dapat uang saku dalam amplop. Selesai mengirimkan barang, saya pulang. Baru di rumah ketahuan uang saku dalam amplop itu jumlahnya banyak sekali. Uang seratus ribuan baru, entah berapa jumlahnya, saya tak sempat menghitungnya saat itu keburu shock. Sore itu juga saya kembali ke tempat praktik bidan, menebus anak dan istri. Memang belum lunas seluruhnya, tapi Bu Bidan berbaik hati, sisanya bisa dicicil katanya, tapi jangan dikasih tahu orang lain sebab bisa jadi kebiasaan. Benar juga saya pikir, masak bayar biaya bidan kayak bayar cicilan panci.
Selang seminggu saya ketemu ibu itu lagi. Minta tolong lagi. Kali ini mengantarkan barangnya ke daerah Bogor. Barang yang dikirim juga lebih banyak, dua dus bekas indomi. Seperti biasa, Mak, ongkos dikasih, uang jajan ada, bahkan ketika pulang mengantarkan barang, saya juga dapat amplop. Isinya tentu saja lebih banyak. Baru kali itulah saya sadar, Mak, ternyata kalau sudah rezeki, akhirnya saya bisa menemukan cara mencari uang dengan gampang.
Setelah mengantarkan barang ke Bogor, kami tak pernah bertemu lagi, saya pun kembali kerja di pabrik dan istri menghentikan kegiatan jualan susu dan daging mentah malam hari, sebab harus mengurus anak kami.
Selang sebulan setelah saya menerima gaji, kami bertemu lagi dengan ibu itu tak jauh dari tempat praktik bidan. Saya diminta mengantarkan barang lagi, dan tempatnya lebih jauh lagi. Sebenarnya waktu itu saya mau menolak, sebab kata istri, uang upah mengantar barang ke Bogor saja masih ada sisa. Tapi karena ibu itu terus memohon bantuan dengan sangat, akhirnya saya menerima tawaran itu. Tak tanggung-tanggung, Mak, saya harus mengantarkan barang itu ke Surabaya. Entah barang apa sebenarnya yang harus saya kirimkan tersebut. Keesokan harinya saya mengajukan cuti dari tempat kerja karena mengirim barang ke Surabaya perlu beberapa hari perjalanan.
Tiba waktunya mengirim barang, saya bawa mobil sendiri lengkap dengan sopir. Barang yang akan dikirim juga lebih banyak lagi, berdus-dus bekas indomi. Bahagianya saya waktu itu, Mak, sebab bisa ke Surabaya tempat yang tak pernah ada dalam bayangan untuk dikunjungi, bawa mobil sendiri lengkap dengan sopir, dan tugas saya ringan sekali hanya mengantarkan barang. Tak terbayang pulang dari Surabaya nanti, betapa tebalnya amplop yang akan saya terima. Mengantar barang ke Bogor saja, tidak habis sebulan dipakai belanja keperluan sehari-hari.
Sedang membayangkan akan menerima upah lebih banyak sambil menikmati nyamannya duduk di dalam mobil sendiri, di daerah Tanjungsari kami dicegat polisi, isi mobil diperiksa, dan yang mengherankan kenapa saya harus dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, saya diperiksa, ditanya segala macam yang semua saya jawab tidak tahu karena memang tidak tahu. Pertanyaan itu diulang-ulang, disaling silang, membuat saya mau muntah saja.
Sejak saat itulah saya tidak bisa ke mana-mana, Mak, sebab ditahan di kantor polisi. Bahkan pada anak dan istri pun saya tidak diberi kesempatan untuk ngasih kabar. Saya juga tidak yakin apakah surat ini akan diterima Emak atau tidak, sebab surat ini hanya dititipkan ke polisi. Tapi saya yakin sekalipun terhalang gunung dan samudra, seorang ibu akan mendengar rintihan anaknya. Kali ini saya menulis surat sambil menahan air mata agar tidak terus menyungai di pipi.
Salam dari putramu dari dalam tahanan.
***
Dari dalam tahanan polisi tanpa tahu apa kesalahannya, anak yang merindukan emaknya itu terus menulis surat, lalu menitipkannya kepada petugas. Dia memang tidak tahu kalau selama ini emaknya tak pernah sekali pun menerima surat itu. Sebab setahun sebelum anak itu mengirim surat, emaknya sudah berada di dalam kubur. Anak itu tak pernah tahu yang terjadi di kampung sebab masih ketakutan kalau pulang kampung akan diancam hansip gara-gara tak tahu diri mencintai Susi sekalipun sembunyi-sembunyi.
Sungguh bukan sok-sokan membawa istri ke bidan, Mak, tapi saya bingung di kota besar ini ke mana harus mencari dukun beranak. Kata tetangga daripada susah nyari dukun beranak, lebih baik ke bidan saja. Tadinya saya pikir antara bidan dan dukun beranak tidak jauh beda, sama-sama menolong yang akan melahirkan, biayanya bisa dicicil atau dicampur dengan beras dan palawija seperti yang sering saya lihat sewaktu di kampung.
Suatu hari ketika menangis di dalam tahanan, seorang petugas menghampiri dan menyodorkan sepucuk surat. Dia segera membacanya. Surat dari emaknya. Dia sangat yakin tulisan dan rangkaian kata-kata dalam surat itu dari emaknya. Selesai membaca surat itu, seketika dia merasa tenteram, sekalipun isi surat itu hanya beberapa kalimat:
Ujang anak emak yang baik.
Tak perlu dibuat sedih, sebab hidup sudah ada yang mengatur. Boleh kamu sedih kalau sudah lupa pada kekuatan yang Maha Menghidupkan. Boleh kamu menangis kalau hidup sudah lupa dari siapa sumber kehidupan. Bangkitlah, Nak. Lihat matahari. Matahari tak pernah sekalipun terlambat untuk terbit.
Doa emak menyertai hidupmu.
Emak.
***
E Rokajat Asura lahir di Bandung. Telah banyak memperoleh penghargaan dalam menulis. Belakangan lebih mengkhususkan diri dalam menulis novel sejarah atau berlatar belakang sejarah. Novel ”Dwilogi Prabu Siliwangi” merupakan novel sejarah pertama yang laris di pasaran. Novel ”Kupilih Jalan Gerilya” (novel biografi Panglima Besar Sudirman), yang terbit tahun 2015, mengantarkan ke Ubud Writers and Readers International Festival 2016 di Ubud, Bali, dan dipresentasikan dalam diskusi panel bertajuk Past & Present bersama penulis lain dari Meksiko, Amerika, Inggris, dan Australia. Novel ”Raden Pamanah Rasa” telah diproduksi sinetron serial dengan judul sama dan tayang di RCTI. Buku tunggal paling mutakhir adalah Haji Hasan Mustapa: Sufi Besar dari Tanah Pasundan (Biografi, Imania, 2020) dan Budak Angon: Kiprah M. Ridwan Kamil (Biografi, Biro Adpim Sekda Jabar, 2021)






