(1)
Tarian Kelelawar Biru

Oleh RISDA NUR WIDIA, 31 Desember 2022
/1/ Tangisan Sebutir Peluru
Semua orang di Rafah, wilayah sekitar Gaza, mengenal baik Abu Hasaant. Ia orang baik, tapi sering berpikiran tak masuk akal setelah putrinya, Ammal, terkena peluru nyasar seorang Tzahal di suatu siang. Dari kejadian itu, setiap kali selesai serangan mendadak dari Tzahal ke permukiman penduduk, Abu Hasaant akan datang memeriksa tempat serangan. Di sana Abu Hasaant tidak berusaha menyelamatkan penduduk yang terluka. Ia malah mengumpulkan selongsong peluru yang ditembakkan tentara Tzahal.
Orang-orang di Distrik Rafah tidak mengerti mengapa peluru-peluru itu dikumpulkannya. Padahal selongsong itu tidak laku dijual di pasar loak mingguan yang tidak jauh dari kamp-kamp pengungsian Nusseirat.
”Apa gunanya mengumpulkan selongsong peluru kosong?” Ismail pernah bertanya kepada Abu Hasaant. ”Kau hanya memenuhi dirimu dengan sampah.”
”Ini bukan sampah,” jawab Abu Hasaant. ”Ini harapan.”
”Harapan?” Ismail kebingungan. ”Harapan bagaimana?”
”Harapan yang disalah gunakan manusia,” lanjut Abu Hasaant.
”Kau gila!” Ismail sedih melihat kawannya itu.
”Sulit menjelaskannya kepadamu,” Abu Hasaant menjawab dengan senyum. ”Aku ingin mengurus ceceran harapan ini, lalu menguburnya.”
”Jadi kau mengubur peluru-peluru itu layaknya manusia?” tanya Ismail lagi.
”Oh, terserah apa yang akan kau katakan nanti,” pekik Abu Hasaant. ”Tapi aku sering mendengar mereka menangis.”
Ismail tidak peduli dengan penjelasan Abu Hasaant. Ismail menganggap kalau Abu Hasaant sudah senewan seperti yang sering dikatakan oleh penduduk Distrik Rafah.
Ismail berlalu dengan mengumpat-umpat melihat tindakan Abu Hasaant yang konyol. Sedangkan Abu Hasaant tenang mengumpulkan ceceran selongsong peluru, sambil menahan pedih di hatinya mendengarkan tangisan pilu para selonsong dan mata peluru.
/2/ Permintaan Maaf Sebutir Peluru
Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa ia sering mendengar peluru-peluru itu menangis. Pertama kali Abu Hasaant menyadari kalau peluru itu juga memiliki perasaan seperti manusia terjadi setelah putrinya tertembak secara tidak sengaja tak jauh dari Masjid Abu Alif Rafah. Putrinya waktu itu baru saja pulang dari toko kue yang berada di Jalan Al-Imam Ali, setelah sebelumnya membeli kue baklava. Putrinya tertembak di bagian dada.
Dokter yang mengurus tubuh Amal berhasil mengeluarkan peluru tersebut. Cuma dokter itu tidak mampu menyelamatkan nyawa anaknya dari kehabisan darah dan kerusakan organ.
”Tuhan lebih mencintai putrimu untuk menghuni surga,” jelas si dokter.
Abu Hasaant segera menangis mendengar putrinya meninggal. Bahkan tangisan itu tidak berhenti setelah pemakaman putrinya selesai di kompleks makam Al-Hikmah.
Abu Hasaant sangat terpukul dengan kematian anaknya. Ia merasa bersalah tidak mengantarkan anaknya untuk mencari kue kesukaannya tersebut—karena sebenarnya si anak sempat minta diantarkan, tapi Abu Hasaant malah sibuk mengecat dinding rumahnya.
Setelah sepanjang hari mengikuti upacara pemakaman anaknya, Abu Hasaant mengurung dirinya di kamar. Di tengah rasa sepi hatinya, Abu Hasaant mendengar tangisan lain dari dalam sakunya.
”Apakah benar peluru ini menangis?” Abu Hasaant kebingungan. ”Aku salah dengar?”
”Kau bisa mendengar tangisanku?” tanya si peluru.
Abu Hasaant tercenung cukup lama dengan kejanggalan itu. Apalagi kini peluru itu berbicara dengannya.
Abu Hasaant seketika berpikir: kesedihan membuatnya gila. Ia pun segera meletakkan peluru itu dengan hati-hati di depannya. Kemudian Abu Hasaant menampar wajahnya sebanyak tiga kali.
”Apakah aku benar-benar bisa mendengarkan peluru ini menangis?” Abu Hasaant bingung.
”Ya tangisan itu adalah tangisanku,” sahut si peluru. ”Jadi kau bisa mendengarkan suaraku?”
”Aku bisa mendengarkannya,” Abu Hasaant merasa berhalusinasi.
”Maafkan aku,” segera peluru itu memekik keras. ”Maafkan aku telah membunuh anakmu. Tapi aku tak pernah ingin membunuhnya.”
Peluru itu kemudian menceritakan kepada Abu Hasaant apa yang sebenarnya terjadi.
Peluru itu memang sengaja ditembakkan untuk menciptakan keributan di tengah keramaian pada Jalan Al-Imam Ali di tengah pasar tradisional Al-Burjh. Salah seorang Tzahal yang waktu itu ditugaskan untuk menyamar menjadi masyarakat sipil, menembakkan secara serampangan peluru tersebut, hingga akhirnya mengenai Amal. Si bandit kemudian pergi dengan mobil kapsul hitam bersama kawannya.
”Aku memang diciptakan untuk membunuh,” ungkap si peluru. ”Tapi aku tidak pernah ingin membunuh.”
”Kau tidak bersalah.” Abu Hasaant tiba-tiba mengatakan itu. Padahal hatinya sangat sedih. ”Manusialah yang bersalah. Mereka berperang demi kepentingan pribadinya.”
Peluru itu sekali lagi meminta agar Abu Hasaant memaafkannya. Abu Hasaant segera mengabulkan permintaan itu.
”Tangan manusialah menciptakan kehancuran,” desis Abu Hasaant begitu murung.
”Dan tidak ada yang salah dari seluru benda ciptaannya.”
Peluru itu menangis cukup lama dengan Abu Hasaant. Tangisan mereka terdengar begitu menyedihkan bagi siapa saja yang mendengarnya dari luar pintu apartemen Abu Hasaant.
Setelah cukup lama mereka menangis, si peluru meminta kepada Abu Hasaant untuk menguburnya di suatu tempat agar dapat istirahat dengan tenang. Selain itu, si peluru juga meminta kepada Abu Hasaant untuk mengubur peluru-peluru lainnya bila kelak ia bertemu di suatu tempat.
”Dengan menguburnya, semua rasa bersalah dari kekejaman yang telah kami ciptakan dapat sedikit teredam,” jelas si peluru. ”Jadi mohon kabulkanlah permintaanku ini.”
Abu Hasaant mengangguk dan melakukannya.
/3/ Peluru dan Kepak Kelelawar
Hari berikutnya, setelah Abu Hasaant mengubur peluru yang membunuh anaknya, secara ajaib dari gundukan kuburan peluru itu keluar seekor kelelawar bercahaya biru. Kelelawar itu terbang ke langit Gaza.
”Apa aku tidak salah lihat?” desis Abu Hasaant. ”Peluru itu berubah menjadi kelelawar.”
Dari kejadian tidak masuk akal tersebut, Abu Hasaant mulai mengumpulkan selongsong atau mata peluru sisa peneyerangan yang ditemukannya secara tak sengaja. Demikianlah malam itu adu tembak antara Tzahal dan kelompok perjuangan lokal di dekat kompleks apartemennya kembali terjadi.
Memasuki pukul 12 malam, rentetan tembakan mulai sayup terdengar. Tidak segaduh sebelumnya. Tapi suara-suara menyedihkan lain dari para peluru mulai terdengar.
”Aku mulai mendengarkan tangisan peluru,” desis Abu Hasaant. ”Pasti ada ratusan peluru yang secara terpaksa membunuh seseorang malam ini.”
Sebuah peluru tiba-tiba nyasar mengenai kaca apartemen Abu Hasaant. Ia kemudian mendengar sayup-sayup pekik tangisan dari peluru itu. ”Kau baik-baik saja bersamaku,” tenang Abu Hasaant.
”Aku sumber petaka!” peluru itu merengek. ”Dunia ini hancur karena aku.”
”Tidak,” Abu Hasaant menenangkan. ”Kau adalah harapan manusia yang disalahgunakan.”
Setelah menunggu sekitar satu jam, hingga Abu Hasaant sendiri tertidur di kolong kamarnya, pertempuran dua kubu itu berakhir. Abu Hasaant pun pelan-pelan mulai keluar dari apartemennya. Ia mencoba mengais-ngais peluru yang dapat dijangkaunya dengan mudah di sekitar apartemen.
”Seharusnya para pasukan itu sudah pergi meninggalkan tempat ini,” Abu Hasaant tetap memasang sikap hati-hati. ”Malam ini aku akan menolong kalian.”
Abu Hasaant saksama mencari mata peluru atau selonsong peluru di bawah kakinya. Setiap kali Abu Hasaant menemukannya, ia selalu mendengar tangisan dan kutukan sesal.
”Aku telah membunuh orang,” tangisan sebuah peluru. ”Aku membunuhnya.”
Abu Hasaant menghampiri sisa mata peluru itu. Ia kemudian berusaha menghiburnya.
”Kau adalah sosok baik,” lerai Abu Hasaant. ”Kau tidak pernah salah.”
Ia dengan lembut memasukkan mata peluru itu ke kantong merah yang selalu dibawanya ke mana-mana.
Setelah kantong itu penuh dengan selongsong atau mata peluru, Abu Hasaant membawanya pulang. Namun malam itu, tanpa disadari oleh Abu Hasaant, ada sesuatu yang menunggu nasibnya. Seorang mata-mata zionis yang sudah membaca kisah hidupnya di koran lokal Knesset, berusaha mencari tahu perbuatan Abu Hasaant.
”Ada yang mengikutimu,” kata salah satu peluru dari kantung merahnya. ”Mereka mungkin ingin berbuat jahat kepadamu.”
Abu Hasaant yang mengetahui segera berlari menuju apartemennya. Mata-mata yang mengikutinya kaget. Si mata-mata akhirnya menembak mati Abu Hasaant.
/4/ Para Peluru Mengantar Abu Hasaant ke Surga
Sepanjang malam, mayat Abu Hasaant hanya dibiarkan teronggok—setelah tertembak—tanpa ada yang mengetahuinya. Anjing-anjing liar bahkan sempat ingin memakannya. Seluruh peluru yang dikumpulkan Abu Hasaant segera melindunginya dan menangis histeris mengetahui Abu Hasaant mati.
”Dunia ini bukanlah tempat bagi orang-orang sepertinya,” kata setiap peluru di sana.
”Ia lebih pantas di surga.”
”Kita harus mengantarkannya ke surga,” tambah para peluru lain. ”Kita harus menempatkannya di dekat Tuhan.”
Selonsong dan mata peluru yang jumlahnya puluhan seketika menjadi kelelawar bercahaya biru. Kelelawar itu syahdan merubung mayat Abu Hasaant, hingga tubuh itu menjadi serpihan abu berwarna biru yang perlahan-lahan hanyut diembus angin ke langit dengan para kelelawar. (*)
***
Risda Nur Widia. Kini sedang kuliah S-3 di Pendidikan Bahasa Indonesia UNY. Buku kumpulan cerpen tunggal Berburu Buaya di Hindia Timur (2020).
***
(2)
Lelah Digantung

Oleh LIA LAELI MUNIROH, 29 Desember 2022
Sedikit pun kau tak memedulikan peluh yang membintik di wajahmu. Sepeda kumbang yang kau kayuh terpaksa kau hentikan saat mendekati jembatan. Kau khawatir terjerumus pada kayu-kayu yang mulai tak utuh. Kedua tanganmu memegang setang sepeda. Dengan sekuat tenaga kau menaikkan sepeda itu menaiki jembatan gantung penghubung dua kampung.
Sesekali kedua matamu tertuju ke dasar sungai yang berjarak sepuluh meter ke bawah. Suara air sungai seolah menjadi penghibur jiwamu. Isi tempurungmu masih memikirkan kepala sekolah baru. Ucapannya begitu menusuk ruang hatimu. Kau mengakui kelemahanmu. Lebih dari dua dekade kau bolak balik melewati jalan setapak. Pengabdianmu seolah tak ada harganya. Tiba-tiba kau disuruh berhenti mengajar.
Air jernih di dasar sungai sudah tak terlihat. Kau baru sampai di ujung jembatan yang membentang lebih dari sepuluh meter. Kerudungmu berkibar terbawa desau semilir angin yang menerpa wajahmu. Kau mengusap keringat. Hampir satu jam kau berjalan. Warung Bi Mun selalu menjadi tempatmu melepas dahaga sebelum kau melanjutkan perjalananmu menuju rumah.
”Wajahmu kok murung, Mar?”
Kau baru saja meletakkan sepedamu di bawah pohon kersen. Kau selalu menyandarkannya di sana. Baru saja pantatmu menyentuh bangku kusam.
”Aku disuruh berhenti ngajar oleh kepala sekolah baru. Katanya aku gaptek dan ….”
Kau tidak melanjutkan ucapanmu. Sudut matamu mulai mengembun. Kau memang tampak akrab dengan Bi Mun. Hampir tiap hari kau selalu singgah ke warungnya sebelum pulang ke rumah.
”Apa benar? Kepala sekolah itu tak punya hati, apa?”
Ucap Bi Mun sambil menyimpan segelas teh dingin di atas meja. Mereka duduk saling berdampingan.
Kau menundukkan kepala seakan tidak ada daya. Tangan kananmu langsung meraih teh manis dingin. Tiga tegukan cukup menyegarkan kerongkonganmu yang kering sejak tadi. Isi tempurungmu masih terus memikirkan ucapan kepala sekolah muda yang baru diangkat. Gaya dan sikapnya yang meninggi membuat Marni tidak betah lagi di sekolah. Padahal, ia adalah guru paling lama mengajar di sana.
Kau kembali meraih gelas yang tinggal berisi air teh setengahnya. Sementara Bi Mun, menatapmu dengan penuh tanya. Dari sudut matamu menggelinding bulir bening menuruni sisi pipimu. Kau mengusapnya dengan ujung hijabmu yang tak lagi cerah.
”Kau menangis, Mar?”
Bi Mun meraih kedua tangan Marni. Seakan merasakan kesedihan yang melanda, Bi Mun mencoba mencari tahu masalah Marni. Baginya ia adalah guru paling sabar mendidik anak-anak kampungnya. Bi Mun tahu betul bagaimana Marni mengajar dengan sabar, terlebih anak kelas satu yang belum bisa membaca dan berhitung. Anak Bi Mun hingga cucunya yang kelas dua turut diajari oleh Marni.
”Aku akan dikeluarkan kayaknya, Bi.”
Bi Mun penasaran dengan kepala sekolah yang baru.
”Bukannya negara yang berhak menghentikan Guru mengajar, bukan kepala sekolah?”
”Negara juga tidak peduli nasibku, Bi.”
”Sabar aja. Nanti juga ada di pengangkatan pegawai.”
”Udah capek aku ikut testing, Bi. Hampir dua puluh tahun tetap saja gaji kecil.”
Bi Mun memalingkan muka. Ia semakin paham apa yang dirasakan Marni. Hatinya ikut teriris. Puluhan Tahun mengajar tanpa ada harganya. Terlebih datang kepala sekolah baru yang menekan akan mengeluarkannya dari sekolah. Tentu Marni tidak terima. Hanya karena Marni gaptek. Memang karena kemajuan teknologi semua guru dituntut harus peka dengan kemajuan. Sementara Marni masih mengajar dengan metode lama.
”Yowis, Bi. Jangan cerita siapa pun. Aku pulang dulu.”
Bi Mun mengangguk. Dadanya ikut sesak menyaksikan Marni memegangi sepeda kumbangnya. Bi Mun tahu persis siapa Marni. Anak yatim yang di sekolahan oleh pak haji Kosim hingga ia dapat mengajar sekolah dasar di kampungnya. Ia menikah dengan seorang kepercayaan pak haji Kosim. Namun, berpuluh tahun mengabdi belum ada tanda-tanda ia akan diangkat jadi pegawai negeri. Langkahnya pelan meninggalkan warungnya hingga punggungnya tak terlihat lagi di belokan.
***
Mentari belum menetas, Bi Mun sudah bergegas membuka warungnya. Setiap pagi selalu ramai didatangi para pelanggannya. Orang-orang yang hendak ke sawah singgah terlebih dahulu di warungnya meski sekadar minum kopi dan pisang goreng. Pun para guru di sekolah dasar dan pegawai kelurahan sering nongkrong di warungnya barang sejenak. Bi Mun terkenal dengan pisang goreng lampenengnya yang pulen. Hampir tiga hari Bi Mun terganggu pikirannya. Batang hidung Marni belum pernah tampak. Atau sekadar lewat ke depan warungnya. Tak pernah terlihat.
Dari balik jajanan yang tergantung pada tali rapia. Bi Mun menelisik di antara para pelanggannya. Tebakannya benar. Orang yang sedang menyantap pisang gorengnya adalah Kurdi suami Marni. Bi Mun gegas keluar warungnya lalu menarik baju Kurdi pelan. Kurdi yang sedang menikmati pisang goreng seketika terkejut. Kurdi memahami kode Bi Mun untuk mengikutinya ke belakang warung.
Di atas sebuah bangku yang terbuat dari tiga batang bambu mereka duduk berdampingan.
”Marni ke mana, Bibi jarang melihatnya lewat mengajar.” Tanpa basa basi Bi Mun langsung menyemprot Kurdi dengan pertanyaan.
”Ada di rumah. Ia ingin berhenti mengajar.”
”Kenapa?” Bi Mun pura-pura tidak tahu masalahnya.
”Katanya disuruh kepala sekolah baru tidak perlu mengajar lagi. Aku sih senang aja Bi. Ada bojo di rumah. Biar aku pulang gawe ada yang siapin makan. Ngajar juga gajinya tidak seberapa. Lebih gede gaji babu di rumah Pak Haji Kosim.”
”Sayanglah … sudah ngajar puluhan tahun, kok malah berhenti. Siapa tahu ada pengangkatan pegawai. Kasih semangat bojomu, Di.”
”Jangan mimpi, Bi. Jaman sekarang engak ada yang gratis jadi pegawai. Kalo harus nyogok juga kami engak bakalan mampu.”
”Lah, jangan nyogok, Di.”
”Ya, habis bagaimana? Udah ya Bi. Aku mau kerja ke tempat Pak Haji Kosim. Takut kena semprot kalo terlambat datang. Aku ngutang dulu hari ini. Kopi sama dua pisang goreng.”
Bi Mun mengangkat kedua alisnya sambil geleng-geleng kepala menatap Kurdi berlalu meninggalkannya. Kasian Marni, batinnya.
***
Lia Laeli Muniroh, Pegiat literasi dan penikmat sastra. Tulisannya tersebar di beberapa buku antologi cerpen dan media massa seperti Kompas.id, Radar Bromo, Radar Kediri, dan Cendana.com. Domisili di pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat.
***
(3)
Musibat Hemat

Oleh GANDI SUGANDI, 24 Desember 2022
Herman berdiri hanya berhanduk di depan bak mandi. Tubuhnya sudah bersih diguyur air dan gosokan dari sabun yang sudah kecil. Rambutnya masih basah, sudah bersampo. Saat hendak menggosok gigi, pasta gigi dalam kemasan plastiknya ternyata tinggal sedikit. Akhirnya, urung menggosok gigi, keluar dari kamar mandi.
Di dapur, Herman berkata pada Iros istrinya, “Pasta gigi mau habis. Paling untuk dua kali lagi pakai. Sisa pasta gigi, buat kau saja. Mau beli lagi, uang tidak ada. Mesti nunggu aku dapat uang lagi dari hasil mengojek.”
“Ya Kang, semoga hari ini dapat rezeki lebih,” jawab Iros.
Usai Herman berganti pakaian, bersiap berangkat.
“Eh, sarapan dulu.”
“Tanggung.”
**
Di pertigaan jalan raya kabupaten, ojek-ojek kampung berbanjar. Herman duduk di atas motor bebek yang terbilang tua bila dibandingkan dengan motor kawan-kawan pengojek. Beberapa saat kemudian, sekitar sepuluh meter menjelang pertigaan itu, satu angkutan pedesaan berhenti. Lalu, turunlah tiga orang penumpang, termasuk seorang pria paruh baya yang hendak menemui anaknya.
Kali ini, Herman yang sedang berada di banjar pertama, otomatis yang mendapat penumpang.
“Ojek Pak?” Herman ramah menawari jasa ojek pada pria paruh baya.
“Iya, saya mau ke Kampung Mekar. Berapa ongkosnya?”
Herman tidak langsung menjawab, berpikir dulu untuk menentukan ongkos karena tahu bahwa calon penumpangnya ini bukan penduduk setempat yang biasa naik ojek, tetapi tamu—lagi pula Herman sendiri sedang butuh uang.
“Berapa?” Pria paruh baya mengulangi bertanya.
Herman sedikit gugup menjawab, “Dua puluh ribu Pak.”
“Bisa kurang?”
“Ya sudah segitu biasanya juga.”
Pengojek ini dan penumpang ini pun sepakat dengan satu harga, tetap di harga dua puluh ribu rupiah. Herman gegas menslag motor bebeknya. Suara mesin pun menderu, motor mulai meluncur ke arah utara ke Kampung Mekar, di atas bukit.
Setelah dua ratus meter, di satu pertigaan jalan, jalanan tersendat. Kendaraan-kendaraan dari arah selatan seperti ojek yang Herman tunggangi, harus menunggu keluar-masuk kendaraan dari belokan jalan sebelah kiri—sebagai jalan masuk ke satu-satunya Puskesmas.
Tak berapa lama, atas jasa pengatur liar lalu-lalang kendaraan, jalanan pun lancar kembali. Herman dan pria paruh baya bisa terus melenggang.
Selama dalam perjalanan, Herman dan pria paruh baya lebih banyak diam.
Rumah-rumah penduduk terus terlewati, kemudian, usai sekira lima belas menit pun berlalu, jalanan mulai menanjak. Di kiri kanan, tanah-tanah yang tertanami aneka sayuran—kol, selada bokor, wortel, lobak—terhampar. Di bidang-bidang tanah lain, palawija seperti kentang, kacang panjang, kedelai, juga terlihat sedang tumbuh subur.
Setelah tiba di depan satu rumah berhalaman luas, berpagar besi hitam, pria paruh baya tiba-tiba teringat petunjuk untuk sampai di rumah anaknya, agar berbelok kiri. Herman pun membelokkan motornya. Setelah lima puluh meter, tibalah pula di tempat tujuan.
Sesuai janji kesepakatan, pria paruh baya membayar dua puluh ribu rupiah. Herman menerimanya dengan senang, lalu berlalu begitu saja.
Nining, anak pria paruh baya, menyambut dengan suka cita.
Nining langsung menanyakan ongkos ojek. “Tadi berapa bayar ojek?”
Pria paruh baya menyebutkan satu angka, membuat Nining menggelengkan kepala. “Kemahalan Pak. Biasanya juga hanya sepuluh ribu. Ya mungkin karena Bapak dianggap tamu.”
“Tadi juga sudah ditawar, ya Bapak kira karena tukang ojek kan orang kecil, akan jujur. Ternyata tidak begitu. Tukang ojek bisa berbohong rupanya.”
“Ya sudahlah Pak. Sudah telanjur.”
Pria paruh baya lalu masuk ke dalam rumah.
Di tengah jalan, di depan satu warung, Herman teringat, pasta gigi sudah mau habis. Motor dihentikannya. Namun, saat mengeluarkan uang di saku, yang hanya ada dua puluh ribu. Herman ragu, hingga akhirnya tidak jadi membeli pasta gigi yang berharga sepuluh ribu rupiah. Motor kembali dilajukan.
Tiba di rumah langsung menuju meja makan. Tertampak tempe dan sayur sop saja. Herman mendadak tertegun, kurang bernafsu untuk menyantap hidangan. Istrinya menegur, “Kenapa Kang, menunya kurang?”
“Bukan.”
“Lalu apa?”
Herman bergeming.
“Kenapa Kang?”
“Ya, tiba-tiba saja barusan aku merasa bersalah karena tadi telah menarik ongkos yang lebih mahal pada satu penumpang yang baru.” “Kan biasanya juga suka begitu?”
“Tidak juga. Ya karena aku sedang butuh uang kan? Iya, kan belum punya pasta gigi. Memang sekarang sedang akhir bulan, sepi penumpang.”
“Tetapi…”
“Tetapi kenapa?’
“Kenapa untuk hari ini, di hati kecilku timbul perasaan bersalah? Mendadak juga aku teringat masa laluku. Ya semoga Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Umur orang kan siapa yang tahu.”
“Jangan bicara begitu Kang.”
Dua hari kemudian, hari sudah cukup siang, Herman masih saja diam di kamar. Herman sesekali meraung saat nyut-nyut di satu giginya terasa.
“Kau sih, dua hari tidak menggosok gigi, jadinya gigi sakit.” Iros ngomel.
Herman membalas dengan menahan sakit. “Kan aku ingin hemat. Nunggu sampai awal bulan, saat banyak penumpang, baru beli pasta gigi.”
“Iya, tapi kan ini akibatnya. Ya sudah, aku akan ke warung membeli obat. Kau pun bangun, paksakan saja untuk mencari penumpang, supaya tidak begitu terasa sakit giginya.”
Iros pergi ke warung terdekat, berjarak sekitar seratus meter. Herman pun bangun dengan memegangi pipi kanannya menuju dapur. Motor dikeluarkan ke teras depan yang sempit. Mesinnya dihangatkan.
Seraya mendengarkan suara mesin, Herman memegangi kedua pipinya. Sudah banyak bulu yang tumbuh. Dagu dan leher juga dipeganginya, ternyata sama, bulu-bulu sudah cukup lebat.
“Sudah waktunya aku bercukur,” Herman berkata pada dirinya sendiri.
Tanpa memadamkan mesin motor, Herman mengambil alat cukur yang tergolek di bawah kusen jendela muka rumah.
Seperti biasa, spion motor dijadikan cermin. Tertampaklah wajahnya yang kusut, terlihat lebih tua dari umurnya yang sekarang 45 tahun.
Serutan pertama, dimulainya di pipi kanan. Herman mengeluh. “Ya, silet ini sudah tumpul. Mau beli yang baru, mana uangnya? Kan aku harus berhemat.” Meskipun begitu, diteruskannya memaksakan menyerut, hingga di pipi kanan dan di pipi kirinya tak tersisa lagi bulu-bulu.
Serutan terus berlanjut di dagu bawah dan di dagu atas, lalu menyerut kumis—yang sebagiannya sudah berwarna putih.
Saat hendak menyerut bulu-bulu di leher, Herman mendadak ragu: silet sudah tumpul, apakah ini akan baik-baik saja? Ah, tapi barusan juga hasil serutan, lancar saja, meskipun hasilnya tidak secepat dengan silet tajam.
Alat cukur mulai ditempelkan di leher kiri, serutan mulai dilakukan. Berlembar-lembar bulu pun berjatuhan. Usai berkali-kali menyerut, di leher kiri pun bersih, tak ada lagi bulu.
Menyerut kini akan beralih ke leher sebelah kanan. Serutan pertama agak tertahan, ya karena silet sudah tumpul. Herman memaksakan menyerut dengan lebih menekan silet ke dalam kulit.
“Ah!” Herman tiba-tiba memekik, serutan silet mengenai lehernya. Darah pun menetes, mengucur, mengenai bajunya.
Iros, pun tiba pula di teras depan—pulang dari warung—langsung menjerit mendapati suaminya sedang mengaduh-aduh seraya memegangi lehernya yang penuh darah.
Jeritan Iros terdengar tetangga-tetangga, juga Pak RT yang rumahnya berhadapan dengan Herman. Pak RT gegas menolong, dengan mobil pick upnya membawa Herman ke Puskesmas. Iros dan beberapa orang tetangga ikut serta.
Tiba di Puskesmas, Herman dibawa ke ruang UGD.
Beberapa saat kemudian, dokter jaga Puskesmas menemui Iros. Katanya, “Herman selamat, goresan silet tidak dalam, tidak mengenai arteri carotis. Tadi Pak RT gesit, langsung membawa ke sini, jadi tidak banyak darah yang keluar. Kalau banyak darah yang keluar, entahlah..”
Bandung, Juni 2022
***
Gandi Sugandi. Penulis adalah alumnus Sastra Indonesia Unpad tahun 2000. Saat ini bekerja di Perum Perhutani Kesatuan PHermangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan.
***
(4)
Permen
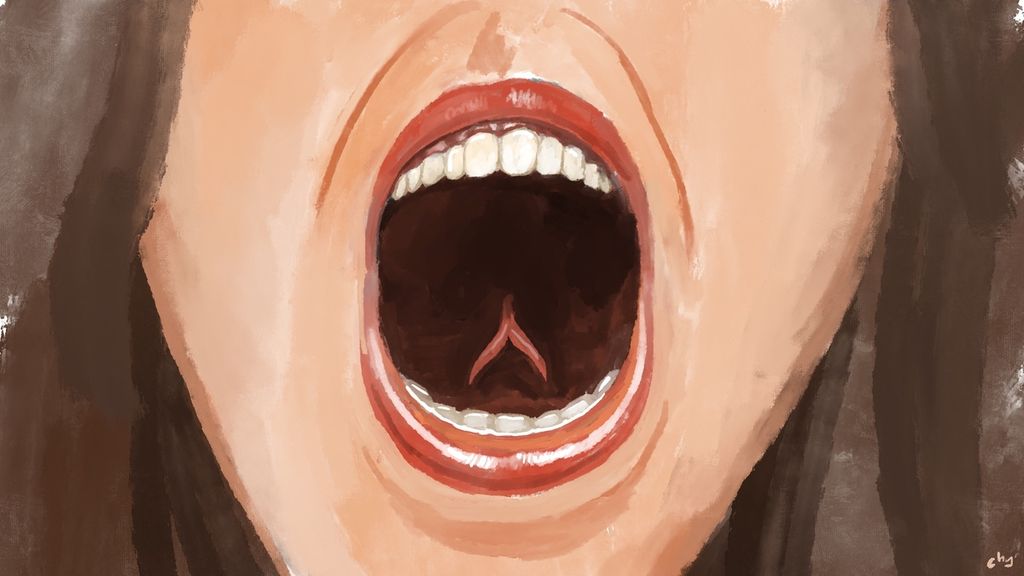
Oleh PUSPA SERUNI, 22 Desember 2022
Ada lima permen kujajarkan di atas meja, dua permen rasa cherry, satu permen rasa mint, satu rasa anggur, dan satu lagi rasa jahe. Di sebelahnya masih ada tiga permen pelega tenggorokan yang diberikan oleh Pak RT kemarin sore. Di kumpulan lainnya lagi, ada dua biji permen susu yang kudapatkan dari warung Bu Yayuk sebagai kembalian uang belanja. Pemberian permen-permen itu membuatku jengkel, bukan karena Bu Yayuk mengganti uang recehan dengan permen, tetapi karena ucapan Pak RT dan ibu-ibu kompleks yang menganggap aku perlu mengemut permen itu ke mana-mana. Apalagi saat mengingat wajah para pemberi permen yang menatapku dengan pandangan meringis sekaligus cemas.
Dalam satu bulan terakhir, pemberian permen memang kerap kali kuterima dari orang-orang yang kutemui. Awalnya, aku merasa itu adalah sebuah bentuk perhatian dan keramahan saat aku berkunjung ke rumah para tetangga. Pemberian permen itu semakin membuatku betah duduk mengobrol di teras mereka, tetapi saat Pak RT mulai ikut-ikut memberikannya juga—apalagi disertai pandangannya yang menatapku dengan takut-takut—aku mulai menaruh curiga. Jangan-jangan, mereka menyelipkan sesuatu, mungkin racun atau jampi-jampi untuk menjatuhkanku. Bisa jadi, kan? Meski di depanku mereka bersikap baik dan ramah, aku selalu tidak bisa mempercayai tetangga dan Pak RT sepenuhnya.
Isu bahwa aku akan mencalonkan diri sebagai ketua RT tahun depan mungkin membuat Pak RT memcoba mempengaruhi warga untuk tidak memilihku. Pak RT sudah dua kali terpilih dan mungkin terobsesi untuk terpilih pada periode selanjutnya dan karena itulah segala cara dia lakukan untuk menjegalku. Aku, sih, tidak masalah. Toh, aku tahu kapasitasku yang jauh di atas Pak RT. Warga tentu akan lebih memilihku untuk menjadi RT, apalagi itu akan menjadi terobosan baru seorang perempuan menjabat sebagai ketua RT.
Aku menghempaskan tubuh dengan kesal pada kursi kayu yang dibeli beberapa waktu lalu. Kuraba permukaan kayu yang halus dan berpelitur coklat itu. Sebuah mahakarya dari seorang perajin kayu di pesisir Jawa yang sengaja kuletakkan di teras supaya semua orang yang datang atau sekadar melintas tahu bahwa perabot di rumahku memang selalu berkualitas nomor satu. Sambil mengagumi kursi sultan milikku, aku mencoba menganalisis maksud dan tujuan pemberian permen-permen itu.
Mari kita cermati satu per satu pemberi permen itu. Kita mulai saja dari Pak RT. Pak RT, siapapun tahu, dia hanya pensiunan pegawai kecamatan yang karena ketelatenannya mengurus warga dipilih sebagai ketua RT. Sebagai pensiunan tentu gajinya tidak seberapa, apalagi kudengar dia juga hanya pegawai rendahan. Alasan kenapa dia terpilih sebagai ketua RT karena dia telaten membantu warga mengurus administrasi kependudukan di kantor kecamatan dan Dinas Kependudukan, menjadi penengah jika ada warga bermasalah, dan tentu sebagai pensiunan dia memiliki banyak waktu luang untuk memperhatikan warga. Meski gaji sebagai ketua RT tidak seberapa, tetapi kuduga pungutan liar yang dilakukannya mampu membuatnya mampu menambah aset pribadinya.
Berbeda lagi kisah Bu Manda, pemberi permen cherry yang pagi tadi kutemui di Mang Jajang sayur, Perempuan berusia awal tiga puluhan dan beranak satu itu merupakan pekerja kantoran yang hidup sendirian. Kuduga dia dicerai sama suaminya karena terlalu sibuk bekerja atau bisa juga karena penampilannya. Aku bertanya-tanya, apa alasan dia membeli rumah di kampung yang jarak ke kantornya di kota kabupaten hampir tiga puluh kilometer. Desas-desus yang kudengar dia memiliki hubungan gelap dengan seorang pengusaha kayu, karena itulah rumahnya—meski berukuran tidak terlalu besar—terlihat berseni dengan penggunaan kayu-kayu jati tua pada jendela, tiang-tiang penyangga hingga pengaturan taman yang dipenuhi bunga-bunga dan rerumputan.
Setiap acara pengajian, dia selalu menjadi pusat perhatian. Wajahnya yang seputih susu, matanya yang bulat bersinar, hingga tutur katanya yang lembut, meresahkan banyak perempuan. Kuminta ibu-ibu di kampung ini erat memegangi suami-suami mereka, bukan tidak mungkin, kan, Bu Manda diam-diam menjadi duri yang mengancam kelangsungan rumah tangga warga. Bagiku, kehadiran Bu Manda adalah sebuah bencana bagi kampung ini, dan aku sudah punya rencana untuk membuatnya pindah.
Lain lagi kisah Bu Yayuk, pemilik warung yang biasa dijadikan tempat ibu-ibu kompleks mengobrol sambil berbelanja. Meski hanya pemilik warung kelontong kecil dan suami yang stroke sejak lima tahun lalu, dia mampu membiayai anak-anaknya kuliah. Bahkan anak bungsunya melanjutkan ke S2. Aku curiga, di sela aktivitasnya berjualan, dia menyelipkan usaha membungakan uang. Pasalnya aku mendengar, beberapa warga bahkan Imah—pembantu di rumahku—pernah meminjam uang kepadanya saat kepepet. Katanya, Bu Yayuk selalu ringan tangan menolong yang sedang membutuhkan.
Aku menghela napas panjang, sebenarnya masih banyak kisah warga kampung yang bisa kuceritakan. Aku sudah banyak mencermati warga kompleks, mengorek informasi mereka hingga ke ruang paling tersembunyi, dan mengetahui aib-aib mereka semua. Aku menganalisis mereka sebagai bagian dari persiapan mencalonkan diri sebagai RT mendatang. Hasil analisa yang nantinya aku gunakan untuk membuat mereka memilihku di acara pencalonan itu.
Aku berdiri lalu melangkah ke depan pintu. Saat daun pintu mulai terbuka, seketika bau bangkai menyeruak, bertubi-tubi mendesak rongga dada, membuat sesak dan perutku terasa bergolak.
“Imah … Barjo …. sudah periksa plafon belum? Bangkainya sudah dibuang?” Aku mulai menutup hidung dan mulutku dengan tangan kanan, sambil tetap berdiri di ambang pintu. Bau itu semakin menusuk.
“Imah … Barjo ….”
Sampai otot leherku bertonjolan, sepasang suami istri yang sudah bekerja kepadaku selama tiga tahun itu tidak juga menyahut apalagi menghampiriku.
Aku melangkah masuk dan disambut empat pot sedap malam yang diletakkan di pojok ruang tamu. Sedangkan di meja, seikat mawar merah di letakkan dalam vas berukuran sedang. Aku terus masuk menuju ruang makan dan dapur. Jambang berisi kelopak melati serta mawar di letakkan di tengah meja makan dan pot-pot tanaman arumdalu di susun di rak bunga di dekat dapur. Aku telah menyuruh Imah dan Barjo membeli banyak bunga beraroma kuat untuk menghilangkan bau dari rumah ini, tetapi sepertinya tidak berhasil.
Aku membuka pintu kamar satu per satu, kosong. Aku menuju dapur, juga kosong. Aku berlari ke halaman belakang, tetap kosong. Aku menggerutu, di mana orang-orang ini. Apa Imah dan Barjo juga pergi seperti suamiku yang awal minggu lalu meninggalkanku: padahal sudah kubilang kepadanya bau bangkai ini akan kuatasi dengan segera. Aku hanya butuh beberapa botol lagi pewangi ruangan, mungkin lebih banyak bunga dan sedikit teriakan kepada Barjo agar segera memeriksa plafon—karena kuduga dari sanalah bau itu berasal, entah dari bangkai tikus atau yang lain.
“Imah … Barjo ….”
Urat leherku nyaris putus rasanya karena sejak tadi berteriak kepada dua orang pekerja yang belum juga muncul. Mungkin sudah saatnya aku memecat mereka. Selama ini aku tidak pernah bisa bertahan lama dengan pembantu rumah tangga, Imah termasuk yang paling lama, mungkin karena itu dia mulai banyak berbantah. Barjo apalagi. Kerjanya cekatan tetapi seperti sapi penarik pedati, harus dipecut dulu untuk bisa berjalan cepat dan perintahku dituruti.
Aku kembali masuk ke dalam rumah, menuju dapur. Kuteguk segelas air putih yang baru kutuang. Setelah meletakkan gelas, pandanganku beralih ke ruang makan. Ada sesuatu di atas meja dan aku bergegas mengambilnya. Sebungkus permen mint rasa buah serta satu lembar kertas lusuh dengan tulisan tangan yang kukenal adalah milik Shifa, anakku yang berusia enam tahun. Dia memang suka permen sejak masuk TK, tetapi untuk apa dia meninggalkan permen itu di sini?
Aku mengambil surat itu, perlahan membaca isinya kemudian merematnya dengan geram. Pikiran Shifa sudah diracuni oleh bapaknya. Dia meninggalkan permen ini untukku.
Ibu, Shifa ikut bapak dulu.
Shifa mau ibu mengulum permen-permen ini, ya.
Permen ini rasanya enak juga wangi.
Di makan, ya, Bu, supaya mulutnya wangi.
Aku menghembuskan napas ke telapak tangan sambil menghirup aromanya. Ah, tidak seburuk yang disampaikan Pak RT tadi. Orang tua itu benar-benar menyebalkan, gerutuku.
“Mohon maaf sekali, Bu, saya terpaksa menyampaikan ini. Beberapa warga sempat berkeluh kesah kepada saya, menyampaikan bahwa dari rumah ini tercium aroma bangkai, begitu juga saat ibu bicara; di warung sayur, di pengajian ataupun di jalan.”
“Pak RT jangan sembarangan bicara. Saya yakin di antara semua orang di kampung ini hanya saya yang punya jadwal khusus untuk ke dokter gigi.”
Aku berkata dengan dada yang bergemuruh.
“Kami tak meragukan itu, Bu. Warisan ibu sangat banyak, bisnis juga berjalan baik. Siapapun tahu, untuk perawatan tentu sudah ibu lakukan. Hanya saja ….”
“Apa?”
Mataku membulat menatap lelaki yang kepalanya sudah penuh dengan uban itu. Hanya pensiunan pegawai rendahan saja, kok, coba-coba menilaiku.
Aku melemparkan sebungkus permen beserta surat dari Shifa ke lantai, menepis bayangan obrolanku dengan Pak RT tadi pagi. Permen-permen berhamburan dari kantungnya yang robek. Orang-orang ini memang keterlaluan. Suamiku, dua orang pembantu, warga kampung bahkan juga Shifa, bisanya hanya mengeluh dan mengeluh saja. Aku tidak peduli mereka semua menjauhiku. Selama aku masih punya uang, aku bisa mencari pengganti Imah dan Barjo, aku juga sangat yakin suamiku akan kembali nanti. Dan untuk Pak RT juga warga kampung di sini, aku sudah punya rencana, akan kubuat mereka semua menyesal telah memberiku permen.
***
Puspa Seruni, penulis kelahiran Situbondo, Jawa Timur, yang saat ini menjadi pengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Bali. Penulis terpilih sebagai Emerging Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2022.
***
(5)
Cerita Tanpa Cerita: Beran, 1949

Oleh SENO GUMIRA AJIDARMA, 18 Desember 2022
Jakarta, 2022
Ia sering teringat ibunya belakangan ini.
Ibunya sudah meninggal 20 tahun lalu, dan kelebat bayangan ibunya ada kalanya muncul.
Namun yang sering teringat olehnya kini adalah suatu kenangan tertentu.
Kenangan timbul, kenangan tenggelam.
Seperti sesuatu yang sebetulnya tidak pernah hilang, tetapi bisa dilupakan.
Kenangan tertentu ini mungkin sesuatu yang sebaiknya dilupakan.
Sesuatu yang mungkin seharusnya dilupakan.
Ingatannya berasal dari masa lalu yang jauh, dalam suatu kamar yang bersih dan terang dan manusia tidak diburu waktu, ketika ibunya bercerita tentang sesuatu yang dikenangnya.
Seperti sambil lalu, tetapi sekarang ia berpikir keras, mengapa ibunya bercerita.
Ia tidak dapat mengingat dengan tepat kata-kata ibunya, tetapi sejauh dapat diingatnya terdapat gambar adegan-adegan yang hidup di kepalanya.
Beran, 1949
Dalam sergapan malam untuk memburu pasukan gerilya di sebuah desa, tentara Belanda menangkap ibunya.
“Ibu membantu palang merah, tetapi ditahan juga, karena langsung kentara bukan penduduk desa itu,” kisah ibunya.
Ibunya di antara perempuan-perempuan di desa. Itu memang dapat dibayangkannya.
Ibunya dibawa ke sebuah pos polisi di Beran, di luar kota Yogyakarta, dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sudah ada seorang perempuan lain di dalam sel itu.
Yogyakarta, 1967
Sel itu mungkin seperti sel dalam kenangannya sendiri. Dari masa kecil, ia teringat sel tahanan di pos polisi kecil dalam kompleks rumahnya. Sel itu terletak di bawah tanah, tetapi lubang anginnya yang berterali berada di atas tanah. Lubang angin itu menjadi satu-satunya jendela bagi seorang tahanan yang ada di situ untuk melihat dunia.
Ya, dunia sebatas mata kaki siapapun yang lewat di depan lubang angin itu. Padahal tempat itu bagaikan tempat tersepi di muka bumi.
Kami, sekawanan anak yang selalu mengembara ke sana dan kemari, dari ngebongan[1] sampai Selokan Mataram, pernah berada di depan lubang angin itu, dan harus berjongkok jika bercakap-cakap dengannya.
Hanya ada seorang lelaki di situ. Seperti sudah cukup lama ditahan, karena dari balik terali itu ia memamerkan apa saja yang dibuatnya. Tampak seperti sebuah peralatan berbahan rotan. Dirinya sendiri tak paham itu peralatan apa, batang rotan kecil yang kedua ujungnya dihubungkan tali.
Barangkali sel tempat ibunya ditahan juga seperti itu. Ia tak terlalu ingat wajah tahanan yang rambutnya sebagian beruban itu, yang sepertinya senang diajak bicara anak-anak kecil di luar lubang angin, karena pada tanah di depannya berderet tanaman tapak dara[2] yang bunga-bunganya merah dan putih.
Beran, 1949
Seingatnya, ibunya juga sulit mencari kata-kata untuk menceritakan apa yang dialaminya.
Setiap hari ibunya diinterogasi seorang perwira Belanda, dalam bahasa Belanda, didesak untuk memberitahukan di mana posisi gerilya. Ibunya tidak pernah memberitahukannya, mungkin pula memang tidak tahu, tapi ayahnya, memang bersama pasukan gerilya.
Jika tidak ke gunung tentu berbaur dengan penduduk.
“Ibu ditanya di mana tempat Bapak dan teman-temannya sembunyi,” kisah ibunya.
Tidak seperti terdapat alur suatu kisah, melainkan kilas-kilas gambaran, itu pun bukan sesuatu yang pernah dilihatnya sendiri.
Misalnya bahwa perempuan yang satu sel dengan ibunya itu setiap malam dikeluarkan dan baru kembali menjelang pagi hari.
Perempuan itu, menurut ibunya, telah sangat membelanya, ketika para serdadu menghendaki agar ibunya juga keluar sel setiap malam.
“Jangan coba-coba! Dia sudah menjadi milik komandanmu tahu!”
Ia berada di sekolah menengah ketika ibunya bercerita, tidak tahu mesti bagaimana menanggapinya, selain diam dan mendengarkan.
***
“Ia dipanggil Tekèk,” kisah ibunya, tentang bocah remaja 15 tahun yang muncul di kantor polisi itu.
Ia membayangkan seorang lelaki berkulit gelap dan bercelana pendek, karena disebut Tekèk ia bayangkan kepalanya seperti cicak.
Tekèk rupanya kurir, yang tersamarkan entah sebagai pesuruh atau sebagai apa tidaklah jelas. Membawa pesan bahwa ayahnya mengetahui keberadaannya.
“Ia membawa kabar dari Bapak, katanya Bapak selamat dan tahu Ibu ada di situ.”
Orangtuanya tentu masih muda, dalam keadaan rusuh, mereka tinggalkan pendidikan di Jakarta, dan terseret hiruk-pikuk revolusi di Yogyakarta.
Tidak terlalu jelas baginya, apakah ibunya ditahan dua minggu atau dua bulan.
“Di dalam sel, setiap saat kami hanya menangis, menangis, dan menangis …”
Terbayang olehnya suatu sel tahanan yang gelap dan dingin, sementara di luarnya para serdadu Belanda melakukan segalanya untuk melupakan sepi.
***
Seingatnya, ibunya tidak seperti bercerita dengan sedih. Tidak menahan tangis, tidak berlinang-linang.
Ia hanya ikut merasa lega ketika ibunya bercerita tentang pembebasan, karena tentara Belanda harus meninggalkan Yogyakarta, kali ini untuk seterusnya.
Terbayang olehnya, di jalanan orang-orang saling bersalam dengan teriakan, “Merdeka!”
Masih juga tidak terlalu jelas baginya, bagaimana cara ibunya dibebaskan. Namun ia teringat ibunya menyebut Klitrèn, nama suatu jalan di kota tempatnya dilepas, kembali bertangis-tangisan dengan teman perempuannya yang satu sel, sebelum akhirnya berpisah.
Di sini ia bisa menanggapi, meski hanya tertarik dengan satu nama.
“Apakah pernah bertemu lagi dengan Tekèk?”
“Pernah.”
“Apakah dia masih ingat?”
“Suasananya sudah berbeda, kami bicara yang lain-lain.”
Waktu itu ia merasa sedikit heran, tetapi tidak bertanya-tanya lagi.
Yogyakarta, 1998
Hampir 50 tahun kemudian, ayah dan ibunya masih hidup, dan suasana sudah jauh berbeda. Mereka yang dahulu bergerilya kini berkuasa, dan mesti menghadapi gerakan kaum muda yang mengacungkan tinjunya di jalanan.
Ibunya tidak pernah bercerita lagi tentang peristiwa yang dialaminya. Ia sendiri merasa tidak pernah teringat sama sekali.
Namun kerusuhan yang berlangsung setiap hari itu seperti mengembalikan semua ingatan ayahnya.
Di depan banyak orang, dengan semangat mengungkap kekejaman perang, ayahnya mengungkap apa yang dialami ibunya.
Cerita itu belum pernah didengarnya.
Ibunya belum menceritakan semuanya.
Apakah ibunya waktu itu memang tidak ingin menceritakan semuanya? Sekarang tangisan kedua perempuan yang tiada hentinya itu baginya bermakna, sementara Tekèk mungkin tak ingin mengingatkan apapun yang mengembalikan kenangan itu.
Kepalanya menunduk ke bawah ketika ayahnya bicara.
Barangkali semua orang juga tidak ingin mendengar cerita seperti itu.
Cerita yang terlalu pahit untuk perempuan, terlalu pahit untuk manusia, dan terlalu pahit untuk dimaklumi.
Jakarta, 2022
Kedua orangtuanya sudah meninggal 20 tahun lalu, tetapi ia hanya teringat ibunya. Ia sering teringat bagaimana ibunya bercerita tentang apa yang dialaminya, sebagai sesuatu yang seperti wajib diceritakannya.
Seperti wajib diwariskannya.
Seperti mewariskan sejarah.
Mengapa ibunya tidak menceritakan semua? Apakah yang tidak diceritakan ibunya?
Dibandingkan cerita ayahnya, cerita ibunya terlalu sedikit, seperti baru memulai, tetapi belum membentuk alur cerita. Namun cerita ayahnya itu pun sangat pendek. Apabila digabungkan hanyalah kilas adegan sebuah cerita.
Tampaknya kedua orangtuanya pun tidak pernah membicarakannya lagi. Disadarinya betapa cerita itu terpendam begitu lama, dan tidak akan pernah terungkap sepenuhnya.
Inilah kenangan atas kenangan atas kenangan.
Perang apapun tidak ada yang bagus, pikirnya.
Apakah yang terjadi di Beran pada 1949?
Belakangan ini ia sering teringat ibunya.
–
Pondok Ranji,
Selasa 29 November 2022. 16:05.
Catatan:
[1]Dari bong atau pekuburan Tionghoa.-[2]Tapak dara(Jw.) = tapak merpati.
***
Seno Gumira Ajidarma, dilahirkan tahun 1958. Bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1977, kini tergabung dengan panajournal.com. Menulis fiksi maupun nonfiksi, dalam media massa maupun jurnal ilmiah; mendapat sejumlah penghargaan sastra, mengajar di sejumlah perguruan tinggi. Buku yang belakangan terbit: Ngobrolin Komik (catatan tentang komik dalam 25 tahun terakhir), komik Macan (bersama Thomdean), komik Percakapan di Ruang Tunggu (bersama Sheila Rooswitha Putri), komik Layang-Layang (bersama Gerdi WK), dan roman Para Pelacur dalam Perahu. Masih menyambung cerita silat Nagabumi.
Ledek Sukadi, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 19 Oktober 1969. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Ledek antara lain menerima penghargaan dari Pemerintah Kyoto, Jepang (1992), dan memenangi gelar lukis akbar di Candi Borobudur (1994).
***
(6)






