(1)
Perempun Hujan

Oleh INDRA TRANGGONO. 29 Januari 2023
Kami tak tahu siapa nama perempuan itu. Kami lebih suka menyebutnya Perempuan Hujan. Sebab, ia selalu datang ke kota kami setiap bulan yang penuh hujan. Ia selalu membawa cerita. Atau kisah-kisah apa saja yang membuat hati kami tergetar.
Alat musik dari logam, kayu, dan bambu tak pernah lepas dari dirinya. Juga gendang dan rebana. Suaranya yang merdu berpadu dengan nada yang mengalir berirama menimbulkan getaran yang merayap ke dalam sukma kami.
Sambil menari dan menyanyi, perempuan berwajah tirus, berhidung mancung, dan tinggi semampai, dengan rambut sebahu, itu mendaras baris-baris kalimat yang mengiris: Kami tak pernah punya piring, sendok, dan garpu/Jari-jari kami membajak gundukan nasi aking yang disengat matahari, tumpah di bak sampah dari truk-truk yang hilir mudik di jalan-jalan perumahan. Kami pun sering berkelahi dengan kucing dan anjing, sekadar berebut kepala ikan asin…. Tak hanya sekali tangan kami digigit atau dicakar. Kami menangis karena terpaksa tega menendang perut anjing dan kucing yang sama laparnya dengan kami…. Air mata kami sederas hujan senja yang memutih, memucat. Kami menggigil. Namun, mendadak ada yang menyentuh pundak kami. Sangat ajaib. Ada kehangatan mengalir. Kami pun menoleh. Seorang lelaki berambut sebahu dan penuh luka tersenyum. Tatapan matanya teduh. Dia memeluk kami. Membawa kami terbang, menembus gumpalan mega-mega, menuju ruang penuh cahaya.
Suara rebana dan bilah-bilah besi bertalu. Mengentak-entak. Disertai lengkingan panjang. Perempuan itu terus menggerakkan tangannya, tubuhnya, rambutnya. Kakinya berderap-derap menghantam Bumi. Ia lalu mengejang dan menumbangkan diri di tanah.
Para penonton tepuk tangan. Dada kami mengembang. Tubuh kami yang terasa ringan seperti diayun. Di kepala kami tepercik api. Kami yang selama ini tidur mendadak terenyak dan terbangun. Bangkit. Melihat luka-luka yang terpahat dalam tubuh dan jiwa kami. Mendadak rasa perih rata merajam sukma kami.
Sosok Perempuan Hujan itu diam-diam menyusup ke rongga dada kami, mendetakkan jantung kami. Kami sangat sadar bahwa semua orang yang diceritakan Perempuan Hujan itu adalah kami.
Selesai mendongeng, bermain musik, dan menari, perempuan itu langsung pergi. Ia tak mau menerima uang atau makanan yang kami berikan. Ia hanya tersenyum dan seperti mengatakan, ”Bukankah kalian masih kekurangan gandum, roti, atau ikan asin?” Perempuan itu tersenyum. Teduh.
Siapa perempuan itu? Banyak cerita tentang dia, karena warga kami memang suka mengarang. Ada yang bilang, dia mantan guru Sejarah, tetapi dipecat karena sering menceritakan kisah-kisah yang berbeda dari versi resminya, seperti korban-korban pembantaian orang-orang yang dicap ”merah”. Atau mengisahkan orang-orang yang dianggap pahlawan, tetapi menyimpan noktah-noktah hitam dalam jiwanya.
Ada juga yang bilang, perempuan itu hanya orang biasa. Janda yang ditinggal mati suaminya yang kena serangan jantung. Frustrasi. Lalu penyakit jiwa menggerayanginya. Ia pun meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Mengembara. Mengikuti desiran angin. Meracau di sepanjang jalan.
Yang lain bilang, perempuan itu sebenarnya jelmaan dari malaikat yang ditugaskan ke Bumi untuk mewartakan kebaikan. ”Malaikat sering menyamar! Guru agama saya sering bilang begitu…,” ujarnya.
Mana yang benar? Kami pun membiarkan kisah-kisah liar itu beredar.
***
Bulan penuh hujan kembali datang. Memandikan kota kami yang kotor dan lusuh. Kami sangat mencintai hujan meskipun udara dingin selalu memompa perut kami memberontak. Juga membikin kerinduan kami pada segelas kopi meronta-ronta. Namun, hujan pula yang menghibur kami. Kami pun semakin berani berkelahi melawan haus dan lapar.
Hujan sederas apa pun tak menyurutkan semangat kami untuk menanti kedatangan perempuan berwajah tirus itu. Dialah orang satu-satunya yang bisa menghibur kami. Menerbitkan harapan kami. Kami selalu menunggunya.
Namun, dia tak kunjung datang. Kami terus menunggu, tapi yang datang hanya bayangan sosoknya. Semua warga kota kami gelisah, cemas. Kami pun mencari di mana dia berada. Kami sisir kota-kota demi kota, tapi hasilnya sia-sia.
Kami pun berkumpul di alun-alun kota. Para polisi menatap kami penuh curiga. Namun, kami tetap saja mengadakan upacara untuk mendoakan keselamatan perempuan yang kami puja itu.
Ketika upacara hampir selesai, mendadak datang mobil yang langsung memasuki arena upacara kami. Mereka turun sambil memapah jasad perempuan yang selalu kami tunggu itu. Kami melihat, tubuh perempuan itu penuh luka, penuh bercak darah.
”Ada gerombolan yang telah memerkosa dan membunuh dia,” ucap salah satu pembawa jasad perempuan itu.
”Kamu yakin?” ujar seseorang.
”Seorang saksi bercerita kepada kami.”
”Siapa?”
”Dia,” kata orang itu sambil menunjuk seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya.
Laki-laki tua itu mengangguk. ”Ya, aku melihatnya. Gerombolan orang itu bagai serigala mencabik-cabik dan melumat tubuh perempuan ini….”
Orang-orang diam. Wajahnya tampak tegang. Tangan-tangan mengepal. Ada kemarahan bergolak dalam dada.
”Pak Tua! Siapa mereka?” tanya salah seorang dari kami.
Pak Tua menggeleng.
”Mereka itu preman yang disewa?”
Pak Tua menggeleng.
Orang-orang melepaskan umpatan kepada para pembunuh. Ada yang ingin memburu dan membunuh mereka. Teriak-teriakan menggetarkan udara yang basah.
Mendadak terdengar sirine. Mobil polisi datang. Empat orang turun. Mereka mengacungkan senjata. Membubarkan kerumunan. Tapi, orang-orang tetap bertahan. Para polisi tetap memaksa kerumunan untuk bubar. Mereka menembakkan pistol ke udara. Berkali-kali. Kerumunan pun bubar.
Di rumah, kami hanya bisa menggigit duka. Samar-samar, kami mendengar siaran berita di televisi. ”Polisi telah mengamankan perempuan yang diduga jadi pengacau keamanan.”
Kami tersenyum. Getir. Suasana hening terasa mengeras dan menekan. Di luar, jarum-jarum hujan menikam Bumi.
Indra Tranggono, cerpenis dan esais, tinggal di Yogyakarta. Belasan cerpennya dimuat dalam buku Cerpen Pilihan Kompas. Buku cerpen yang sudah terbit: Sang Terdakwa,Menebang Pohon Silsilah, Perempuan yang Disunting Gelombang, dan Iblis Ngambek.
***
Nasirun, lahir di Cilacap, 1 Oktober 1965, menamatkan pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta pada 1994. Meraih sejumlah penghargaan, antara lain Sketsa dan Seni Lukis terbaik ISI Yogyakarta, McDonald Award pada Lustrum ISI Ke-10, dan Philip Morris Award 1997. Aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran karya seni sejak 2004.
***
(2)
Kemuning
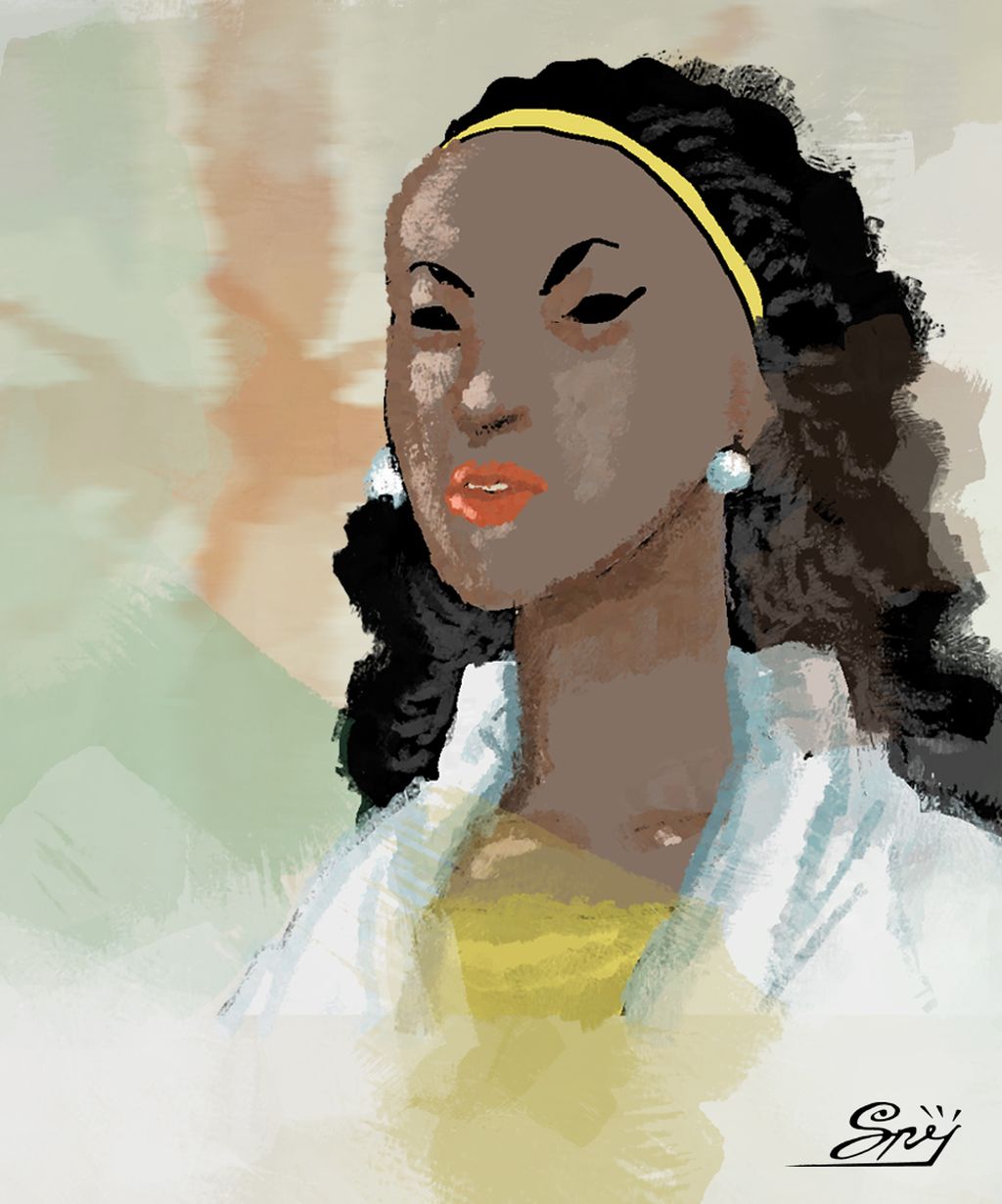
Oleh RINAL SAHPUTRA, 28 Januari 2023
“Kau tahu kenapa Ibu dan Bapak menamaimu Kemuning?“
“Mungkin karena Ibu menyukai warna kuning. Atau pada saat Muning lahir, Bapak sedang mengajarkan topik imbuhan sisipan kepada para siswa di sekolah.“ Meskipun Ibu terlihat sangat serius dengan pertanyaannya, Kemuning menjawab asal sambil cekikikan. Tapi, memang warna favorit Ibunya adalah kuning dan Bapak seorang guru Bahasa Indonesia di salah satu SMA di Jakarta.
Ibu dan Bapak ikut tersenyum. Itu hampir 20 tahun yang lalu, saat dirinya baru lulus SMA dan mendapatkan beasiswa kuliah ke Inggris.
Kemuning masih mengingat masa-masa bahagianya dulu. Ingatan yang membuat isakannya semakin kentara.
“Kemuning, kau yakin akan menikahi lelaki itu? Bukan hanya akidah kalian yang berbeda, tetapi budaya dan latar belakang keluarga juga harus kaupikirkan baik-baik. Kau sudah dewasa. Apalagi dengan gelar S-3 yang kaumiliki dan jabatan sebagai peneliti di universitas ternama. Tapi, Ibu mohon Kemuning, pertimbangkan dengan bijaksana keputusanmu ini!“
Memorinya bergerak cepat dan tak tertebak. Kemuning teringat air mata di wajah Ibu, 6 tahun yang lalu, saat dia mengungkapkan pada keluarganya di Indonesia bahwa dia akan menikahi John. Ibu gamblang menunjukkan ketidaksetujuannya, sementara Bapak memilih diam. Namun Kemuning bisa melihat gurat kekecewaan di wajah Bapak. Kemuning sama sekali tidak membantah, meskipun pada akhirnya dia tetap menikah dengan John. Dan semenjak saat itu, Ibu dan Bapak tidak lagi menjawab telepon atau pun membalas pesan Whatsapp darinya. Pun keluarga besarnya yang lain. Semua seolah beranggapan bahwa Kemuning sudah mati.
John tidak percaya keberadaan Tuhan. Sementara dirinya adalah seorang Katolik. Setidaknya itu yang tertulis di KTP. Kemuning sendiri sudah lupa kapan terakhir kalinya dia ke gereja. Dia bertemu dengan John melalui salah satu aplikasi dating. Padahal dia tidak terlalu serius saat mendaftar di aplikasi tersebut. Ketidakseriusan yang kemudian mempertemukan dia dengan John. Memilih John berarti memutuskan hubungannya dengan Ibu, Bapak, dan keluarganya yang lain. Kemuning seolah tidak diperbolehkan untuk memilih keduanya.
Pernah dia pulang ke Indonesia bersama Mirabelt, yang waktu itu baru berusia 2 tahun, untuk menemui Ibu dan Bapak dan sekaligus memperkenalkan Mirabelt dengan keluarga besarnya di Indonesia. Ibu terlihat semakin ringkih, sedangkan Bapak berbaring setengah sadar akibat stroke yang sudah hampir setahun dialaminya. Kemuning menangis sesenggukan, bersujud di kaki Ibunya. Semenjak mengandung dan melahirkan Mirabelt, Kemuning mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang Ibu. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Ibu. Bahkan dia menolak untuk memeluk atau menyapa Mirabelt.
Kemuning merasa dipojokkan. Saat kembali ke Inggris, dia mulai mengalami gangguan tidur dan sama sekali tidak bisa fokus dengan pekerjaannya. Setelah berdiskusi panjang dengan pihak lembaga research tempat dia bekerja, Kemuning memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih terbang ke pedalaman Afrika. Salah satu kawan dekatnya saat kuliah S3 dulu berasal dari Gambia. John tidak menentang keputusannya. Dia malah sama sekali tidak berkomentar. Kebisuan yang membuat Kemuning merasa diabaikan. Hanya tangisan Mirabelt saat John mengantarnya ke bandara yang sempat membuatnya ragu.
Air matanya mengalir kian deras.
Hampir enam bulan semenjak Kemuning memilih mengasingkan diri di Gambia, di antara orang-orang yang sama sekali tak dia mengerti, baik bahasa atau pun budaya mereka; namun Kemuning masih belum mampu menenangkan badai di hatinya. Semua upaya yang dia lakukan untuk berdamai dengan keluarganya di Indonesia seolah berakhir sia-sia. Kemuning masih tidak bisa mengerti, seberapa sulit bagi keluarganya untuk menerima John. Bahkan keluarganya di Indonesia menolak untuk mengakui Mirabelt sebagai bagian dari mereka. John sempat menyarankan dia untuk move on dari keluarga besarnya. Topik pembicaraan yang kemudian menjadi sumber keriuhan antara dia dan John. Kemuning bahkan mulai meragukan jika John masih tulus mencintainya. John sama sekali tidak menghubunginya.
Panas yang menyengat dan aroma tanah liat seolah menjadi identitas baru Kemuning selama berbulan-bulan di sini. Namun di tengah lamunan dan isakannya, Kemuning tersentak oleh tangisan anak perempuan yang terdengar nyaring di tengah kegelapan pedalaman Afrika. Wajah Mirabelt tiba-tiba memenuhi benaknya. Rindu yang menyeruak mengaburkan matanya oleh tetesan yang semakin tak terbendung.
Tanpa memberitahu John, Kemuning kembali ke Inggris. Bandara masih terlihat sepi, khususnya antrean untuk warga negara asing. Meskipun sudah menikahi John secara resmi, Kemuning tetap mempertahankan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Seolah masih ada ragu tentang masa depannya di sini. Pun kecintaannya pada tanah air tidak bisa dia abaikan begitu saja.
Hampir pukul 7 pagi, tetapi matahari masih belum terlihat. Gigil musim dingin di penghujung Desember menyambut Kemuning saat menapakkan kakinya di luar bandara, menuju antrean taksi.
Kemuning mematung. Ruang tamu berantakan dengan botol minuman keras di mana-mana. Juga terlihat beberapa pakaian dalam wanita yang terselip di antara celah sofa atau tergeletak di lantai begitu saja. Hati kecilnya menyuruhnya segera pergi, tetapi keingintahuannya malah menyeret kakinya menuju ke ruang tidur utama. Suara desahan semakin jelas terdengar.
Tangisan Kemuning bercampur amarah. Dia membanting pintu kamar sekuat tenaga dan bergegas menuruni tangga. Seketika Kemuning teringat Mirabelt. Dia kembali menuju ke lantai atas. Kamar Mirabelt tepat di samping ruang tidur utama. Tapi John sudah berdiri di sana, hanya memakai celana pendek dan masih terlihat mabuk.
Kemuning sigap menyeka air matanya.
“I want to see Mirabelt!“ Suara Kemuning terdengar asing, bahkan untuk dirinya sendiri.
John menatapnya tajam. Kemuning berusaha mencari rasa bersalah di sana, tetapi hanya ada amarah. John seperti terlahir kembali sebagai sosok yang baru.
“She is not here. But why suddenly do you care? You already got your black men out there!“
Kemuning tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. John menuduhnya berselingkuh? Tuduhan yang seolah menjadi pembenaran untuk perselingkuhannya sendiri.
“No, John! Do not blame me for all this shit! I was in Gambia to heal myself. You know that!“ Kemuning berteriak, melawan perih yang kian ganas menyayat ulu hatinya.
“Whatever! I have nothing to do with you anymore or with your arrogant family. Do whatever you want. Mirabelt stays with me, forever!“ John berbalik, berjalan menuju ke arah kamar. Suara bantingan pintu yang jauh lebih keras seakan mempertegas semuanya. Bahwa kisah mereka sudah berakhir.
Sepanjang perjalanan menuju ke hotel Kemuning hanya menangis. Rindunya pada Mirabelt, amarahnya pada pengkhianatan John, dan sakit hatinya terhadap tuduhan perselingkuhan yang John luapkan padanya. Semuanya saling berkecamuk. Tuhan! Apakah ini balasan yang kauberikan karena tak mendengar perkataan Ibu dan Bapak? Kemuning berusaha mengumpulkan setiap inci kewarasan yang masih dimilikinya. Foto Mirabelt dipeluknya lebih erat.
Kemuning menuntut hak asuh Mirabelt melalui pengadilan. Namun dia kalah telak. Status kewarganegaraannya, kondisinya yang saat ini tanpa pekerjaan, dan foto-foto dari John sebelum Kemuning memutuskan untuk berangkat ke Gambia yang menunjukkan kerapuhan mental dia. Semua itu cukup menjadi bukti bagi pengadilan untuk melimpahkan hak asuh Mirabelt kepada John. John sama sekali tidak mengizinkan Kemuning untuk menemui Mirabelt.
Bercerai dari John, Kemuning kehilangan hak tinggalnya di Inggris. Dia bisa saja mendapatkan status permanent resident karena sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun, tetapi Kemuning memutuskan kembali ke Indonesia.
Di saat yang bersamaan, kondisi Bapak semakin parah. Setibanya di Indonesia, Kemuning bergegas ke rumah sakit. Dia mencium tangan Bapak dengan takzim dan memijat kakinya. Ibu sama sekali bergeming dari kursinya, namun sama sekali tidak menolak saat Kemuning memeluknya. Dua hari kemudian, Bapak pun pergi, tak lagi kembali.
Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Ibu menangis dalam pelukannya dan itu membuat Kemuning menangis lebih kencang.
“Kautahu kenapa Ibu dan Bapak menamaimu Kemuning?“
Pertanyaan yang sama. Namun, kali ini Kemuning membisu. Hanya isakannya yang terdengar dengan jelas.
“Kau dulu perempuan tegar, Kemuning. Bahkan sejak kecil tak pernah kami dengar kau menangis, meskipun kawan-kawan di sekolahmu selalu mengolok-olok rambutmu yang keriting atau kulitmu yang hitam legam. Kau tak pernah menyerah untuk meraih mimpimu menjadi seorang peneliti di luar negeri. Padahal saat itu, nilai Bahasa Inggrismu adalah yang terendah di kelas. Bahkan ketika kami semua menentang pernikahanmu dengan John, Ibu tidak pernah melihat kebimbangan di matamu. Kau seolah bangunan kokoh yang bergeming di tengah amukan badai.“
Kemuning masih membisu.
Senja semakin mendekati malam. Para tamu yang datang mengunjungi rumah duka tak lagi seramai sebelumnya. Kemuning seolah masih membaui aroma kemboja yang bermekaran di pemakaman tempat Bapak berbaring untuk selamanya.
“Kami ingin kau tumbuh menjadi sosok yang selalu bahagia dan bermanfaat untuk semua. Seperti pohon Kemuning tua di halaman rumah Eyang, sebelum ditebang oleh Pamanmu karena alasan didatangi hantu.“ Ibu menatapnya dalam.
“Tapi apa yang Ibu dan Bapak lakukan terhadap Muning sangat tidak pantas. Ibu bahkan menolak memeluk Mirabelt, cucu Ibu sendiri. Selama ini Kemuning berusaha kuat karena dukungan semua keluarga. Sepahit apa pun masalah yang Muning hadapi, Muning tidak takut. Itu karena Muning yakin Ibu dan Bapak akan selalu ada mendukung Muning.“ Kemuning terdengar ragu-ragu, seolah takut menyakiti hati Ibunya.
“Cintamu terhadap pria itu yang menghancurkan dirimu sendiri, Muning!“
“Apakah salah jika Muning mencintai John?“
“Tidak ada yang salah dengan cinta. Kau hanya mencintai lelaki yang salah. Dan kau lebih memilih lelaki itu dibandingkan kami semua di sini. Kaupikir mudah bagi kami untuk mengabaikanmu begitu saja? Aku Ibumu, Muning! Berbulan-bulan aku mengandungmu dan berdarah-darah saat melahirkanmu. Kaupikir Ibu dan Bapak pernah merasakan bahagia sedetik pun saat kau memutuskan menikahi lelaki itu? Bahkan hingga Bapakmu meninggal, kaulah satu-satunya yang terus dia khawatirkan.” Air mata di wajah Ibu yang semakin deras menghadirkan perih di hati Kemuning.
Kemuning memeluk Ibunya.
“Maafkan Muning, Bu!“ Meskipun masih terisak, Kemuning tiba-tiba merasakan kelegaan yang perlahan memenuhi hatinya. Rasa damai yang sudah menjauhinya selama bertahun-tahun akhirnya kembali. Namun hanya sesaat.
Bayangan Mirabelt menyerbu benaknya secara membabi-buta dan membuat matanya kembali memanas. Dia mengepalkan tangannya sekuat tenaga hingga buku-buku jemarinya memerah. Ibu seolah paham dan memeluknya lebih erat. Isakan keduanya menandai malam yang semakin pekat.
***
– I want to see Mirabelt: Aku ingin bertemu dengan Mirabelt
– She is not here. But why suddenly do you care? You already got your black men out there: Dia tidak ada di sini. Tapi, kenapa tiba-tiba kaupeduli? Bukankah kau sudah punya para lelaki kulit hitam di luar sana.
– No, John! Do not blame me for all this shit! I was in Gambia to heal myself. You know that: Tidak John. Jangan menyalahkanku untuk semua ini. Aku ke Gambia untuk memulihkan diri. Kamu tahu itu!
– Whatever! I have nothing to do with you anymore or with your arrogant family. Do whatever you want. Mirabelt stays with me, forever: Terserahmu. Aku tidak punya urusan apapun lagi denganmu atau dengan keluargamu yang arogan itu. Lakukan apa saja yang kauinginkan. Mirabelt akan selalu bersamaku.
***
Rinal Sahputra, saat ini bekerja sebagai peneliti di Universitas Manchester, Inggris. Kumpulan cerpennya, Para Perempuan di Tanah Serambi, terpilih sebagai salah satu finalis penghargaan Sastra Rasa 2022.
***
(3)
Kronik Bukit Api

Oleh T AGUS KHAIDIR, 26 Januari 2023
Akhirnya ada jawaban untuk menampik cerita perihal bukit api. Cerita perihal Laung dan keluarganya yang disebut masih gentayangan dan senantiasa siap menuntut balas pada warga desa yang 21 tahun lalu menyerbu rumah mereka; membacok, menikam, menebas, menyeret-nyeret, dan melempar mereka ke dalam api yang berkobar.
Togu menghempas napas. Ada rasa kesal yang membuncah di dadanya. Ada marah, sedih, tapi sekaligus lega juga. Sembilan di antara penyerbu telah menemui ajal. Berturut-turut satu tiap malam pasca-kejadian. Waktu itu ia masih 16 tahun. Togu ingat, pertemuan para pemuka desa di rumahnya membulatkan kata walau tak berujung mufakat. Laung dan keluarganya harus dihabisi!
Kematian anak Marsilam memicu ledak amarah. Para tetangga bersaksi, anak itu, remaja perempuan yang sedang riang-riangnya berkawan, masih terdengar bernyanyi-nyanyi di rumahnya sepulang sekolah. Dia berlatih untuk keikutsertaan di festival menyanyi lagu perjuangan tingkat kabupaten. Namun, berselang setengah jam lonceng gereja berdentang mengabarkan kematian. Kata Marsilam di antara sedu sedan, anaknya mendadak terpekik. Matanya melotot dan napasnya tersengal, lalu ambruk tak bangun lagi.
Serangan jantung? Marsilam histeris mencecar sumpah, keluarganya tak punya riwayat penyakit ini. Lalu apa? Ini kematian mendadak ketujuh dalam kurun dua bulan. Kematian tanpa tanda-tanda, tanpa gelagat, dan bagi warga desa hanya ada satu jawaban: ulah begu ganjang, hantu jahat bertubuh tinggi yang bisa diperintah meneror mencelakai, sampai mati.
Namun, kenapa Laung? Dalam ingatan Togu, orang tua ini (73 tahun ditulis koran-koran saat itu), tak tampak meyakinkan sebagai parbegu. Satu-satunya hal yang membuatnya berbeda dari warga lain adalah dia tidak menanam padi atau jagung atau kentang atau jeruk di ladangnya. Laung menanam tumbuhan obat. Padahal dia bukan datu partaor, ahli ramuan penyembuh penyakit dan penangkal racun. Tatkala pemerintah di tahun-tahun awal Orde Baru membangun puskesmas dan menempatkan dokter di sana, dia termasuk yang paling getol mendukung. Konon inilah pergesekan pertama Laung dengan Guru Saut, orang pintar, tempat warga melabuhkan segenap adu dan tanya. Tak terkecuali saat ada yang sakit. Guru Saut sebenarnya datu, tapi dipandang telah mencapai tingkatan lebih tinggi. Hampir semua warga percaya, tak peduli penyakit apa, sekedar sentuhan tangan Guru Saut dapat menyembuhkannya.
Keberadaan dokter puskesmas mengguncang eksistensi Guru Saut, tapi tak lama. Kematian tiga bocah akibat diare menyusutkan ketakjuban warga. Campur tangan Guru Saut menggesernya jadi kebencian. Dokter itu tak tahan dan memilih angkat kaki.
Hampir berseiringan mencuat isu begu ganjang. Walau tak pernah ada bukti, sampai bertahun kemudian nama Laung tetap disebut. Akibatnya, ingatan tentang Laung sebagai pemelihara begu makin kuat dan lambat laun bergeser jadi kepercayaan.
Ingatan ini pula yang membuat Togu paham kenapa usulan Amang, ayahnya, untuk mengusir Laung dan keluarga ditolak mentah-mentah. Guru Saut dan Marsilam meradang. Pun Amangboru, dua tulang Togu, dan beberapa orang lain yang berada di ruang tamu rumahnya malam itu. Bilang mereka, parula-ula; pemelihara begu, dan semua yang berhubungan dengannya tak boleh dibiarkan hidup.
Walau kalah suara Amang berkeras mengambil jalan berbeda. Selain kepala desa, Amang juga sintua, pemuka agama. Kata Amang mengutip Alkitab, pembalasan, dalam bentuk apa pun, adalah hak Tuhan.
Guru Saut mengambil alih komando. Tidak ada basa-basi lagi. Laung yang tertatih keluar rumah langsung disergap. Bertubi pukulan dan hujaman bermacam senjata mendarat di tubuhnya yang renta. Istrinya menjerit, tapi segera senyap setelah kepalanya dihantam kayu balok. Anak Laung menghunus golok, menerjang kerumunan mengelebatkan tikaman dan sabetan membabi buta. Upaya sia-sia. Jumlah pengeroyok terlalu banyak. Tusukan kelewang dari arah belakang menghentikan perlawanan.
Para penyerbu makin dirasuk kegilaan. Tubuh Laung, istri, dan anaknya yang sudah tak berdaya diseret ke pinggang bukit. Di satu tempat terbuka mereka menumpuk kayu dan menyulut api dan melemparkan ketiga tubuh itu ke sana.
Menantu Laung bersama anak dan keponakannya lari ke hutan. Namun jejak mereka cepat terlacak. Cerita didengar Togu, sembari menangis menjerit-jerit menantu Laung memungut dahan kayu seukuran lengan dan mengayun-ayunkannya dengan liar. Perlawanan sia-sia. Tikaman susul-menyusul pada pinggang, dada, dan punggung menghentikannya. Cucu Laung, perempuan dan laki-laki yang usianya tak berselisih jauh dari mendiang anak Marsilam, bernasib serupa.
Keponakan menantu Laung sedikit merepotkan. Togu ingat-ingat lupa namanya. Mungkin Parulian. Mungkin Pandapotan. Pastinya, menurut cerita beredar, laki-laki muda ini (waktu itu baru setahun lepas SMA) punya kemampuan tarung yang tak sekadar. Pengeroyoknya kerepotan. Begitu pun lama-kelamaan dia terdesak juga. Kakinya tertebas parang. Dia tersungkur tapi cepat bangkit, lalu terpincang-pincang berlari. Tiba di tepi sungai, ketika para pengeroyok menyangka dia sudah terjebak, laki-laki-laki itu mendadak melentingkan tubuh lantas melompat ringan dari batu ke batu. Namun luka di kaki agaknya mempengaruhi keseimbangan. Dia terpeleset, tercebur ke sungai dan digulung arus.
**
Togu mengempas napas lagi. Dari balik kabut yang makin tebal bukit itu kelihatan seperti bayang-bayang punggung raksasa yang tertidur. Kelam dan muram.
Kematian Guru Saut, Marsilam, Amangboru dan dua tulang Togu, serta empat orang lainnya secara beruntun selama sembilan hari pasca-kejadian, membuat warga percaya dari alam kematian Laung dan keluarganya menjalin persekongkolan dengan begu ganjang untuk melakukan pembalasan. Beberapa jam setelah penemuan mayat kesembilan, sejumlah warga yang menemui datu-datu dari desa lain kembali dengan nasihat yang sama: lantaran perdamaian dengan Laung dan begu ganjang tak mungkin dilakukan, maka satu-satunya cara untuk memutus pembantaian adalah dengan memalingkan pandangan. Bilang mereka, jangan pandang bukit itu! Memandang berarti mengundang begu ganjang datang.
Warga menurut dan kematian beruntun memang berhenti. Kematian kembali jadi kabar sedih tanpa kengerian. Termasuk kematian Amang yang menggiring Togu memboyong keluarganya pulang untuk mengurus ladang dan lapo peninggalannya tiga tahun lalu. Namun sejak itu pula kematian-kematian terjadi lagi. Kematian yang didahului gejala aneh: sulit bicara, sulit berjalan, ingatan melemah, pandangan kabur dan telinga jadi pekak. Ada yang sering kejang, mual, dan sakit kepala berkepanjangan. Ada juga yang tangannya kerap kesemutan hingga bahkan sulit untuk sekadar memasang kancing baju sendiri.
Sejumlah perempuan melahirkan bayi tak normal. Ada yang ususnya di luar perut. Ada yang ukuran kepalanya kecil. Ada yang matanya hanya satu. Bayi-bayi ini tak berumur panjang. Rata-rata hanya bertahan kurang dari tiga hari.
Tipikal kematian-kematian ini sebenarnya berbeda. Ada tenggat waktu. Ada tahapan gejala, dari ringan ke berat sampai akhirnya meninggal dunia. Namun warga terlanjur menaruh curiga dan menuding Togu melanggar nasihat datu. Bukan tanpa sebab. Sejak kepulangannya Togu berulang kali menyebut begu ganjang cuma tipu-tipu.
”Kau jangan sok tahu, Togu!”
Togu tidak merasa sedang sok tahu. Di perantauan ia mendalami antropologi. Begu, termasuk begu ganjang, memang ada dan jadi bagian kepercayaan. Namun berbagai naskah yang dipelajarinya mencuatkan satu benang merah: kemunculan begu ganjang nyaris selalu diawali perseteruan berlatar cemburu dan dendam.
Togu sebenarnya menyimpan satu rahasia. Hanya Togu yang tahu bahwa 21 tahun lalu keponakan menantu Laung yang bernama entah Parulian entah Pandapotan itu tidak mati tergulung arus. Malamnya dia kembali ke desa, mengendap-endap mendatangi rumah Togu untuk menghabisi Amang yang disangkanya sebagai penggerak massa. Togu memergokinya saat melompati jendela belakang dan sempat bergelut dengannya dan tentu saja ia kalah. Saat hampir kehabisan napas lantaran lehernya dicengkeram jari-jari sekuat besi, Togu menyebut Amang tak bersalah. Amang justru hendak mencegah pembantaian. Adalah Guru Saut, Marsilam, Amangborunya, juga dua tulangnya, yang jadi otak penyerbuan.
Laki-laki itu percaya dan urung menghabisi Amang. Dia melompati jendela dan segera menghilang ke balik kegelapan, dan esoknya, terbetik kabar Guru Saut ditemukan mati di tempat tidurnya dengan mulut ternganga dan mata membeliak.
Hari berikut Marsilam pula yang mati, lalu beruntun Amangboru Togu, kedua tulangnya, dan empat laki-laki yang konon ikut mengeroyok laki-laki itu di hutan. Kemudian kematian terputus. Bukan lantaran nasihat para datu, melainkan kedatangan polisi untuk melakukan penyelidikan. Barangkali laki-laki itu takut dan lari bersembunyi ke hutan, lalu memutuskan pergi. Sejumlah warga desa yang bekerja di ibu kota kabupaten mengaku melihat seseorang mirip dia menyetop dan naik truk pengangkut barang tujuan Jakarta.
”Sekarang begu itu minta nyawa lagi, Togu!”
”Matilah kita, Togu!”
Seorang warga menyusul mati sepekan lalu. Setelah beberapa hari tergolek lemas, warga itu, seorang lak-laki paruh baya yang sehari-hari bekerja mencari ikan di sungai, menuntaskan napas penghabisan dengan sengal-sengal yang keras. Togu sempat dibekap ragu. Setelah sekian lama berlalu, apakah ia memang keliru?
**
Togu duduk di lapo, menatap ke bukit dengan penuh kesal dan marah, sedih, tapi sekaligus lega juga. Pagi tadi tersiar lagi kabar kematian. Delapan perempuan, enam dewasa dua usia remaja, terkubur dalam lubang yang ambruk di pinggang bukit itu. Togu tidak mengenal mereka. Pun warga lain. Kasak-kusuk terdengar nyaring.
”Mereka penambang!”
”Apa yang ditambang?”
”Emas.”
”Sejak kapan di sana ada emas?”
Togu dan sejumlah warga desa, untuk pertama kalinya setelah 21 tahun, menginjakkan kaki kembali di bukit itu, dan mendapati betapa pinggang bukit dan hamparan luas di bawahnya telah berlubang-lubang seperti sarang semut.
Medan, 2020-2022
***
T Agus Khaidir, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, 4 Februari 1977. Menulis beberapa puluh cerpen yang sebagian besar telah tersebar dan dimuat di berbagai media cetak, daring, ataupun sejumlah buku antologi bersama. Kini tinggal di Medan sebagai wartawan. Masih memotret, sesekali melukis, mengerjakan desain grafis, membuat sketsa, ilustrasi. Juga masih bermusik, dan tentu saja bermain sepak bola.
***
(4)
Lelaki yang Membunuh Gorila

Oleh KARISMA FAHMI Y. 24 Januari 2023
Ia bangun dan bertanya pada diri sendiri mengapa tangan dan kausnya berlumur darah. Sebagian sudah mengering dan membuat kaus putihnya kaku. Darah siapa ini?. Sebagian bercak darah mengenai selimut dan seprai. Ia melepas kaus putihnya dan mencuci tangan di keran. Harusnya ia mengusap wajah dengan air untuk menyegarkan diri. Namun itu tak dilakukannya. Demam semalam masih menyisakan keringat dingin di tubuhnya.
Ia memanggil Bi Inah, pembantu yang mengurusnya selama ini. Orang tuanya meninggal lima belas tahun lalu. Sebuah kecelakaan beruntun merenggut orang tua dan dua adiknya. Saat itu ia berada di luar kota, baru saja lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Kehilangan yang begitu tiba-tiba itu membuatnya terguncang. Ia memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah itu bersama Bi Inah. Bi Inah bekerja di rumahnya sejak ia masih SD. Ia tak punya anak maupun keluarga lain. Bi Inah sudah dianggapnya seperti orang tuanya sendiri. Meski geraknya sudah semakin lamban, namun perempuan tua itu masih kuat membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuknya.
Ia masih bertanya-tanya mengapa aroma anyir darah masih tercium di udara meski ia sudah mencuci tangannya dengan sabun. Ia kembali memanggil Bi Inah. Bi Inah tak menyahut. Mungkin ia sedang membeli sayur, pikirnya. Beberapa waktu ini pendengaran dan penglihatan Bi Inah mulai berkurang. Sering ia tak mendengar panggilannya meskipun mereka berada di jarak dekat.
Ia duduk di kursi makan. Bi Inah biasanya sudah membuatkan kopi untuknya di meja. Namun pagi itu tak ada kopi atau makanan apapun di meja. Ia membuka koran kemarin yang tergeletak di meja sambil mengingat-ingat kejadian semalam. Semalam ia pulang kantor dalam keadaan demam tinggi. Cuaca memang sedang tak menentu. Perubahan cuaca bisa terjadi sewaktu-waktu. Matahari sangat terik di siang hari, tapi lantai dan air yang mengalir dari keran terasa sangat dingin layaknya air es. Ia minum obat flu dan menyerahkan diri untuk tidur lebih awal. Hanya tidur yang membebaskannya dari demam dan kepala yang berputar-putar.
Ia merapatkan selimut hingga ke dada. Sesekali ia membuka mulut untuk bernapas, hidungnya pun buntu dan tenggorokannya kering. Ia ingin segera memejamkan mata. Namun dilihatnya seekor laba-laba raksasa di langit kamar. Benar-benar raksasa, karena besarnya melebihi antena parabola. Laba-laba yang tenang dengan kaki dan sungut panjang seperti di film-film. Ia acuh saja. Tubuhnya lemas seolah tak punya tenaga. Serangga itu berayun-ayun, lalu meluncur ke arahnya. Ia terjingkat dari tempat tidur dengan jantung yang berdegup kencang.
Ia salah, yang dilihatnya bukan laba-laba, melainkan gorila. Rumbai yang semula terlihat seperti kaki laba-laba ternyata adalah rumbai bulu-bulu gorila. Dari mana datangnya gorila ini? Ia berpikir keras. Rumah ini berada di tengah kota. Hutan terdekat tujuh mil ke selatan, kebun binatang tiga mil ke arah tenggara. Tak ada kelompok sirkus yang berkunjung di kota ini. Lalu dari mana datangnya primata purba ini?
Gorila itu mengerang, mengingatkannya pada ekspresi wajah bosnya yang brengsek. Mulutnya terus mendengus, mengingatkannya pada peristiwa siang tadi di kantor. Lelaki gemuk itu berteriak keras padanya di hadapan semua karyawan. Apa saja kerjamu? Tumpukan kertas ini kau sebut sebagai laporan? Suaranya menggaung ke seluruh ruangan. Ia membayangkan dinding-dinding akan runtuh karena suaranya. Tapi tidak. Harga dirinyalah yang seketika runtuh. Dalam hati ia hanya bisa merutuk. Tak hanya itu, lelaki itu mengoceh tentang kinerjanya di hadapan semua orang di kantor.
Gorila itu tampak tak bersahabat. Wajah berbulunya menyeringai seolah memiliki rencana menghabisinya. Seketika ia bergidik ngeri, seolah berada di film Jumanji yang sudah ratusan kali tayang di televisi.
Ia mencoba mengingat benda-benda di sekitarnya. Benda yang bisa digunakannya untuk melawan gorila itu. Di atas meja ada pisau lipat. Ia mengupas mangga sebelum tidur karena buah itu mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk meredakan flu. Kulit dan biji buah mangga masih berserakan di atas meja. Biasanya Bi Inah yang membereskannya. Mungkin aroma mangga itu yang mengundang primata ini, pikirnya.
Ia masih mengingat-ingat benda-benda yang ada di sekitar jangkauannya. Ia menggeleng, tak mungkin bertarung melawan primata raksasa itu dengan pisau lipat. Ia teringat peristiwa beberapa bulan lalu saat ia duduk di taman untuk melepas lelah sepulang kantor. Seekor monyet kecil merebut donat yang dimakannya. Ia terlonjak kaget dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan, menggegerkan orang-orang yang sedang pacaran, sementara munyuk itu melonjak kegirangan. Ia segera pergi dan tak mau berurusan lagi dengan monyet itu. Hingga beberapa waktu ia menghindari taman dan lebih memilih duduk di kafe untuk melepas penatnya.
Ia menggeleng. Tak mungkin mengalahkan gorila dengan pisau lipat, sementara teringat munyuk kecil itu saja ia sudah gentar. Ia masih mengingat-ingat benda-benda di sekitarnya yang bisa digunakannya sebagai senjata. Lalu ia ingat gulungan plastik sampul buku di pojok ruangan. Ia memiliki banyak buku dan dengan telaten menyampulinya sebelum membaca. Gulungan plastik itu satu-satunya benda yang bisa diharapkan untuk menghadapi primata besar itu. Namun kembali ia menggeleng. Benda itu terlalu berat, dan binatang itu sangat kuat. Bisa jadi aku celaka saat menggunakannya untuk menyerang. Gulungan plastik itu memiliki diameter yang besar. Cukup merepotan menggunakannya.
Ia terus berpikir dan mengingat benda-benda di sekitarnya. Kamus, album foto, gunting kecil, penggeret solasi. Ia mulai menyebutkan satu persatu benda-benda di dekatnya. Ia mulai putus asa. Tak ada benda yang bisa dijadikannya senjata.
Ia menyerah. Seharusnya ia memiliki satu senjata api. Senjata yang bisa digunakan untuk saat-saat seperti ini. Lalu ia teringat tombak dan senapan yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia pernah bertanya pada kakek untuk apa memajang senjata itu di sana. Ada senapan dan tombak yang dipajang di dinding ruang tamu.
Kakek tersenyum lebar memamerkan gigi tembakaunya. Kakek memang suka mengisap tembakau. Tak seperti rokok-rokok keluaran pabrik, rokok tembakau yang digulung kakek mempunyai aroma yang khas. Kesukaannya merokok itu membuat giginya sewarna tembakau yang diisapnya. Untuk berjaga-jaga dari apa saja yang menyerang tiba-tiba, kata Kakek. Ia tak mengerti. Ujung tombak yang runcing dan berkilat itu membuatnya ngeri membayangkan tubuh-tubuh yang ditembus senjata itu. Dan meskipun senapan itu tak lagi terisi peluru, ia sering membayangkan tubuh-tubuh yang ditembus peluru. Entah sejak kapan ia tak menyukai bayangan itu. Bayangan kisah perang ataupun tragedi pembunuhan membuatnya bergidik ngeri. Sekali lagi kakek terkekeh. Justru harusnya kita merasa nyaman, karena tak ada yang berani mengusik kita.
Ia tetap menggeleng tak mengerti, dan memahami bahwa kakek memasang senjata itu di sana hanya karena alasan nostalgia. Kakek seorang pejuang. Ia mengikuti perjuangan merebut Merah Putih di bawah komando Jenderal Sudirman. Dua senjata itu menjadi saksi masa-masa perjuangannya. Kakek meninggal di usia delapan puluh, saat itu ia masih kelas dua SMA. Hingga kakek dikuburkan, kekhawatiran kakek tak pernah terjadi. Atau mungkin juga kakek benar, tak ada maling atau sejenisnya yang berani mengusik mereka karena tahu bahwa senjata itu masih tersimpan apik di sana. Ia tak tahu. Sampai saat ini tombak dan senapan itu masih dipajang di dinding ruang tamu. Mungkin memang sedikit berdebu dan berkarat karena waktu, namun keberadaan dua benda itu sebagai senjata di rumah ini masih sama. Kini ia tahu mengapa setiap orang harus memiliki senjata. Ia baru menyadari kakeknya benar, pentingnya memiliki senjata di rumah untuk menjaga dari hal-hal yang tidak terduga seperti saat ini.
Ia terus menatap gerak-gerik gorila itu. Kepalanya berat dan pandangannya mulai berputar-putar. Gorila itu mendengus, cuping hidungnya mengendus-endus udara. Ia berpikir keras cara untuk bergerak cepat, meski tubuhnya terlalu lemah untuk melakukannya. Tak mungkin menggunakan tombak maupun senapan untuk melawan gorila itu. Tombak dan senapan di ruang tamu terlalu jauh dari jangkauan. Gorila itu akan menyerangnya sedetik setelah ia turun dari tempat tidur. Kepalanya semakin pening. Ia menyerah dan memutuskan akan menggunakan gulungan plastik sampul di pojok kamar kalau monyet besar itu menyerang. Belum sempat meraih gulungan plastik, gorila itu sudah mengambil pisau lipat di atas meja. Gorila itu melihat ke arahnya layaknya kelinci percobaan. Entah kekuatan dari mana, ia bangkit dan merebut pisau lipat dari tangan kera raksasa itu. Ia mengayunkan pisau lipat itu ke sembarang arah, melindungi diri.
Gorila itu terus menghindar dari tikaman yang dilayangkannya. Ia kembali mengayunkan pisau lipat, menyerang timbunan lemak di perutnya. Gorila itu berlari keluar kamar. Entah keberanian dari mana, ia mengejar dan menangkap gorila itu tanpa ampun, menarik bulu-bulu panjangnya dan berusaha menikamnya. Ia menikam tubuh gorila itu dengan pisau lipat sambil membayangkan menikam tubuh besar bosnya yang brengsek di kantor. Akhirnya gorila itu rubuh. Ia terengah-engah. Gorila itu tak lagi bergerak. Ia meninggalkan gorila itu di ruang tengah dan membiarkannya tetap di sana.
Kepalanya berat berputar namun perasaannya berangsur lega. Ia berjalan kembali ke kamar, menuju dipan dengan tubuh terhuyung. Angin masih bertiup kencang di luar. Tangannya berlumuran darah. Ia membayangkan air keran yang dingin dan mengurungkan niat mencuci tangan dan tubuhnya. Dirapatkannya selimut hingga menutup kepala. Di sanalah gorila dan bayangan bosnya menghilang.
Pagi itu ia bangun dengan kepala lebih ringan meski masih ada hawa dan keringat dingin di sebagian tubuhnya. Ia sudah mengganti kaus dan mencuci tangannya, namun aroma anyir darah masih mengikutinya. Ia duduk di meja ruang makan. Angin masih bertiup dari jendela, meniupkan anyir darah ke seluruh ruangan. Lelaki itu kembali memanggil-manggil Bi Inah, dan memintanya membawakan secangkir kopi seperti biasanya.
Agustus 2022
****
Karisma Fahmi Y, lahir di kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Aktif mengajar di SD Takmirul Islam Inovatif Surakarta. Esai, cerpen, dan puisi-puisinya pernah dimuat di harian Kompas, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Majalah Sastra Horison, Koran Tempo, harian Media Indonesia. Buku kumpulan cerpennya adalah Pemanggil Hujan dan Pembaca Kematian diterbitkan oleh Penerbit Basabasi, dan satu cerpennya ada dalam buku Antologi Kumpulan Cerpen Koran Tempo 2016.
***
(5)
Kisah Wanita-Wanita Tanpa Nama

Oleh MIE S, 19 Januari 2023
Kutatap halaman aplikasi curhat online itu dengan mata basah. Haru bercampur sakit, menciptakan derai yang kian mengalir deras. Haru membaca kisah-kisah pernikahan mereka yang terkesan sangat bahagia. Walau entah siapa, tanpa tertera nama, namun pengalaman nyata mereka membuatku tersenyum tanpa sengaja. Namun, beberapa menit berikutnya, rasa sakit menyeruak, mengingat pernikahan yang terkadang mencipta rasa muak.
Aku tertegun, salah satu dari mereka mengatakan, suaminya sangat cuek, dingin. Bahkan dalam 7 tahun pernikahan hanya sekali memberinya buket bunga dan hadiah. Tersenyum ketir, masih lebih baik dari suamiku yang tak pernah sekali pun memberi bunga.
Kutelusuri beberapa akun lainnya. Tulisannya terlihat sangat panjang, berisi semua hal tentang kebaikan suaminya. Tentang suami yang jago masak dan selalu memasak untuknya setiap hari saat hamil, tentang gaji suami yang sangat layak untuk tinggal di Jakarta, tentang isi saldo ATM kecil suami yang berisi 10 juta, tentang isi ATM besar untuk segala keperluan. Aku termenung. Pikirku, beruntung sekali dia, dengan segala kelebihan dan kebaikan suaminya. Lalu teringat saldo ATM sendiri yang hanya berisi 67 ribu rupiah. Sedang suamiku, dia tak memiliki kartu itu. Kartu ATM milikku pun hanya digunakan saat suamiku mentransfer uang untuk keperluan sehari-hari, yang jumlahnya tak lebih dari 250 ribu rupiah per minggu.
Anganku mulai berkelana, berandai jika aku menjadi wanita dengan saldo ATM berjumlah besar itu. Akan kubeli banyak camilan, agar saat terbangun tengah malam dan perut terasa lapar, tak perlu mengorek-ngorek makanan sisa semalam.
Akan kubeli kompor dua tungku, agar saat repot dan buru-buru bisa mengefektifkan waktu. Akan kubeli minyak goreng untuk persediaan satu bulan, agar tak pernah terjadi lagi kejadian adonan gorengan sudah siap tapi ternyata minyak telah habis.
Lamunanku buyar, karena pergerakan jagoan kecil yang tidur di sisi ranjangku. Kutatap ia lekat, dia salah satu alasan aku bertahan. Penyemangat hari-hari yang kian sepi. Hubungan jarak jauh membuat terkadang pernikahan makin terasa hampa. Tak ada canda tawa apalagi kehangatan raga. Aku kembali menitikkan air mata.
Masih belum berniat menghentikan pencarian. Kuusap kembali layar ponsel melanjutkan bacaan. Salah satu akun itu kali ini bicara tentang suaminya yang berpendidikan tinggi, dan ia yang hanya lulusan SMA. Dia bilang suaminya tak pernah merendahkan, sangat menghormatinya. Suaminya sangat romantis, hingga setiap hari memanggilnya ‘Cantikku’ padahal ia tahu, dirinya tak secantik itu. Setiap hari suaminya mengatakan ‘I love you’ dan dia selalu bahagia mendengarnya. Tersenyum pahit, entah kapan kata keramat itu ia ucapkan secara langsung. Dalam kilasan-kilasan chat pun, hanya sesekali di akhir chat. Itu pun jika aku memulai lebih dulu, mengungkap isi hati kalau aku mencintainya.
Kuusap air mata. Lalu bertanya perlahan pada hati, masihkah cinta itu ada? Atau telah menghilang bersama kehampaan?
Aku masih mencintainya, hanya saja keadaan rumah tangga yang terasa monoton, sikapnya yang terasa biasa, dan masih banyak hal lain yang sering kali membuatku ragu. Apakah aku berarti baginya? Sebagai teman hidup dan seseorang yang akan menua bersamanya? Bukan sekedar teman tidur atau pemuas keinginan saja. Pernah kulukis impian, menjadi seseorang yang ia banggakan. Seorang istri yang dibanggakan karena kesabaran dan kesetiaan, yang menerima segala keterbatasan suami dalam perihal ekonomi dan apa pun yang belum ia mampu. Pernah pula mendamba, menjadi seseorang yang dia inginkan, memberi sedikit pujian dan kejutan, tak perlu mahal, sederhana tapi buat bahagia.
Kuhela nafas dalam. Dia pilihanku saat itu, tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun. Apa pun yang terjadi saat ini, itu konsekuensi atas pilihanku sendiri.
Terkadang cinta memang perlu ditunjukkan, tapi mungkin dia bukan tipe laki-laki pengumbar puji atau rayuan. Tanggung jawab dan kebaikannya menjadi satu-satunya keyakinan, mungkin dia masih mencintaiku. Tak peduli keyakinan itu salah atau tidak, aku hanya berusaha membuat hati lega agar ia tak terlalu hampa. Mataku tak lagi basah. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Kututup aplikasi curhat itu dengan senyum kecil. Itu hidup mereka, dengan kebahagiaan mereka, dan ini kehidupanku. Sampai kapan pun dua hal itu tak akan pernah bisa ditukar, tak akan pernah bisa. Jadi, kenapa tak kujalani saja semuanya, tanpa repot berangan menjadi seperti mereka?
Kutatap jam di ponsel, lewat tengah malam. Pertengkaran beberapa saat lalu dengannya kembali berputar, membuat rasa kantuk tak kunjung datang. Utang yang menumpuk menjadi akar permasalahan, karena aku yang disalahkan. Kuhela nafas dalam. Berpikir keras, memikirkan cara bagaimana agar hidup kami berubah. Setidaknya, walau tak banyak harta, bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Pernah terpikir untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri. Namun, saat ingat wajah mungil anakku, pikiran itu lekas kuusir.
Beban hidup yang kian mengimpit, membuat hati kian sempit. Kenapa kita mesti bertengkar? Haruskah aku pergi dan menyerah? Dengan begitu, kamu akan tahu tak mudah menemukan wanita sepertiku.
Pernah pula terbayang perceraian, namun ketakutan menghantui, takut kasih sayang ayah sambung tak sama dengan kasih sayang ayah kandung. Walau nyatanya, ada ayah kandung yang tega menelantarkan anaknya.
Semua beban hidup dan pikiran itu membuat kepala pening. Belum lagi otot paha yang menegang dan sakit karena terlalu lelah bekerja di sawah. Aku lelah. Perlahan kupejam mata, berharap kantuk segera datang. Dengan tidur, setidaknya semua hal yang berada dalam pikiran dan angan akan berhenti, kecuali denyut nadi.
***
Mie S, wanita sederhana penyuka cerita. Saat ini hanya mengurus rumah tangga. Cerpen dimuat di Kompas.id, Dua Lamaran, dan Ikan-ikan yang Tersesat. Cerpen yang terbit dalam Antologi bersama, Raina, Terkurung Sesal. Novel fiksi yang terbit, Pasangan Hidup Terakhir (2019), Dia Mencuri Mahkotaku (2020).
***
(6)
Batavia yang Tak Sesuai Rencana Lucretia

Oleh SASTI GOTAMA, 15 Januari 2023
Selasa pagi 7 Juni 1898, seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Lucretia van der Maas. Ia berencana menyiram gladiol jingganya yang baru berbunga, menerima kiriman sayur segar dari Catia, dan memanggang roti kismis bagi Bastiaan van der Maas, suaminya. Hidupnya selalu tertata dan ia tak ingin menyesali setiap detiknya. Karena itu, ia selalu merencanakan semua yang ia anggap penting dan melaksanakannya tanpa cela, tak terkecuali untuk hari Selasa ini. Namun, itu sebelum ia menerima surat yang dikirim ke rumah oleh jongos Westzijdsche Pakhuizen atau bekas gudang barat VOC yang telah diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Sejak itu, Lucretia merasa semua rencananya tak lagi penting.
Dengan kepala tegak, Lucretia van der Maas berjalan ke dapur, memilih pisau buah paling tajam, dan menyimpannya ke dalam tas tangan yang terbuat dari kulit buaya. Tanpa tergesa ia berjalan ke ruang depan, mengenakan sarung tangan, dan meraih topi bundar kesayangannya di gantungan. Bastiaan selalu mengingatkannya untuk menggunakan topi dan sarung tangan agar kulit pualamnya tak digosongkan matahari Batavia yang garang.
”Kulitku pucat seperti mayat. Biarkan matahari membuatku sedikit coklat,” begitu Lucretia pernah merajuk, tetapi Bastiaan tetap kukuh pada pendiriannya. ”Matahari tropis itu berbahaya. Bukankah dulu kulitmu pernah merah dan gatal karenanya? Sudahlah, kamu apa adanya sudah membuatku jatuh cinta,” ucap Bastiaan dalam bahasa Belanda yang terdengar lembut di kuping Lucretia. Lucretia tahu, kata-kata Bastiaan sarat tipu daya, tetapi tak mengapa baginya terjerat di sana. Itu dulu. Sekarang, Lucretia tentu tak akan terperangkap semudah itu.
Usai mematut tubuhnya di cermin bulat—dan merasa puas melihat pantulannya—Lucretia van der Maas meminta bujang rumah memanggil kereta kuda. Sayang, yang tersedia hanya dokar dengan kuda yang tak terlalu kekar dan tampaknya kurang makan. Sebetulnya saisnya pun tampak kurang makan seperti pribumi-pribumi lainnya. Tapi itu tak masalah bagi Lucretia, karena baginya yang terpenting mereka bisa mengantarkannya ke Koningin Emma Ziekenhuis atau Rumah Sakit Ratu Emma.
Sepanjang jalan, sais itu hanya bungkam dan menghentakkan tali kekang, sedangkan si kuda yang kurus itu melenggang dengan tenang. Itu lebih baik bagi Lucretia karena ia pun malas berbincang dengan kaum pribumi yang penyakitan. Toh ia tak pernah tahu apakah di setiap ucapan si pribumi itu akan disertai embusan udara yang sarat kuman tuberkulosis. Membayangkan itu Lucretia bergidik. Batavia memang kubangan penyakit. Seharusnya para pribumi itu bersyukur ketika Belanda datang ke bumi mereka dan membawa peradaban modern dan menyelamatkan mereka dari gempuran penyakit mematikan. Jika tidak, tentu mereka sudah habis dibabat wabah karena hanya mengobati sakitnya dengan dedaunan dan kembang setaman.
Tiga bulir keringat sebesar bulir gabah muncul di pelipis Lucretia, tetapi ia tak memedulikannya karena kepalanya sedang sibuk memutar kembali kisah lamanya di Leidseplein, Amsterdam. Masa-masa ketika ia berdiri di atas ujung jari yang mengenakan pointe shoes di panggung Stadsschouwburg dan dihujani cahaya lampu. Ia menjelma Marie Taglioni yang berputar, memantul, dan terbang seolah-olah malaikat Mikael telah meminjamkan sayapnya dan lupa memintanya kembali. Ia berencana pergi ke teater di Itali, Inggris, atau Rusia dengan kapal uap. Sayangnya, ia melakukan kesalahan fatal: bertemu Bastiaan van der Maas dan jatuh cinta dan pergi bersamanya ke Batavia.
Di Batavia, tentu saja tak ada gedung teater seperti Stadsschouwburg. Lucretia van der Maas harus melupakan cahaya terang dan nyeri di ujung jempol kaki dan harus berkonsentrasi bagaimana menakar tepung, gula, dan mentega untuk membuat roti kismis. Bastiaan van der Maas benci nasi, dan di Batavia tak ada roti seenak roti kismis buatan ibunya. Syukurlah ada aku, pikir Lucretia. Tanpa dirinya, tentu Bastiaan akan mati kelaparan. Walaupun begitu, Lucretia tak pernah mencicipi secuil pun roti kismis buatannya karena Bastiaan berkata ia ingin pinggang Lucretia tetap seramping ranting bugenvil. Jadi Lucretia van der Maas tak pernah sekali pun makan kukis, roti kismis, atau gula-gula. Lucretia van der Maas hanya makan pepaya, pisang, dan sayur-sayuran.
Untuk masalah suplai buah dan sayuran ini, ia tak perlu khawatir. Ada Catia de Rozario, seorang Mardijker yang tinggal di wilayah Ommeladen. Sayur dan buah yang ia bawa selalu segar. Sebagaimana kaum Mardijker yang lain, Catia terbiasa berbicara dalam bahasa Kreol Portugis sehingga sering kali terbata-bata ketika berbincang dalam bahasa Belanda. Nenek buyutnya memang berasal dari Bengala dan mendarat di Malaka sebagai budak. Setelah dibawa oleh VOC ke Batavia, akhirnya ia dibebaskan dan menjadi orang merdeka dengan syarat ia bersedia berpindah agama dari Katolik menjadi Kristen Protestan sebagaimana kebanyakan warga Belanda di Batavia. Walaupun berasal dari Belanga dan berkulit gelap seperti orang Tamil, ia selalu merasa bagian dari bangsa Portugis dan berpakaian ala Portugis. Untuk menyambung hidup, ia bertanam sayuran di Ommeladen dan usahanya itu diturunkan kepada anak cucunya hingga kini jatuh kepada Catia.
Sebetulnya Lucretia tidak ingin terlalu akrab dengan Catia. Baginya, Catia tetaplah kaum budak dan tak sejajar dengannya. Namun, sebagai penganut kasih Kristus, tentu ia harus berbelas kasih kepada kaum rendahan, dan sudah sepatutnya Catia bersyukur karena Lucretia sudi berbincang dengannya.
”Mevrouw, wortel-wortel jingga tentu akan membuat mata Mevrouw yang indah itu semakin berbinar. Senin kami panen raya. Mau saya bawakan Selasa besok?” ucap Catia Jumat lalu.
”Kenapa tak kamu panen lebih awal dan bawakan untukku hari Minggu saja? Kebetulan aku ada rencana membuat keik wortel.”
”Saya… ada janji, Mevrouw,” ucap Catia malu-malu. Lucretia bisa melihat semburat merah di pipi Catia yang cokelat matang dan itu tak membuatnya lebih cantik. Mirip tomat busuk saja.
”Baiklah. Selasa saja. Bawakan yang segar satu keranjang.” Dan Lucretia berpikir, betapa murah hati dirinya. Karena dirinyalah, Catia dan keluarganya bisa makan.
Namun, surat yang Lucretia baca tadi pagi seketika melibas semua rencana. Surat itu ditulis dalam bahasa Belanda yang sederhana dan ditujukan kepada suaminya. Lucretia bisa membayangkan seseorang itu menulis dengan hati-hati sambil diterangi lampu ublik. Tampak tekanan pena pada kertas yang menunjukkan ia menulis dengan rasa kecewa yang pekat.
”Saya menunggu. Mengapa Anda tak datang? Kamar Stads Herberg ini terasa sepi walau Pelabuhan Sunda Kelapa sudah ramai dengan penjual ikan. Anda di mana? Kabari segera.’
Kalimat-kalimat itu sudah membuat hati Lucretia cedera, tetapi nama di bagian paling bawahlah yang membuatnya jejas parah. Catia. Bagaimana mungkin perempuan sekelas budak hitam legam, bahkan lebih hina dari pribumi, mampu mencuri miliknya. Miliknya.
Lucretia ingat, Sabtu lalu, suaminya berkata bahwa ia harus pergi ke Syahbandar Sunda Kelapa. Ada masalah perdagangan yang harus ia selesaikan mendadak. Namun, Sabtu itu juga Lucretia mendapat kabar kereta suaminya mengalami kecekaan, terperosok ke dalam kanal. Syukurlah Bastiaan baik-baik saja, hanya mengalami patah kaki kiri dan harus dirawat di rumah sakit Ratu Emma. Saat itu Catia tentu tengah menunggu Bastiaan di ranjang Stads Herberg, lalu lelaki itu tak pernah datang, lalu Catia mengirim surat yang ia kirim ke kantor perdagangan tempat Bastiaan bekerja, lalu kacung kantor mengirimkannya ke rumah Lucretia. Tentu itu tak sesuai rencana Catia.
Di atas kereta kuda, Lucretia teringat semua rencana dalam hidupnya yang telah menjelma debu di udara: beasiswa sekolah balet St Petersburg, lampu terang panggung Stadsschouwburg, dan keriangan ketika ia berputar, meloncat, dan terbang. Ia pertaruhkan itu semua dalam perjudian bernama pernikahan. Dan kini, ia hanya punya pisau dalam tas buaya.
”Kita sudah sampai, Mevrouw.” Sais itu berucap dalam bahasa Melayu, tetapi Lucretia paham maknanya. Lucretia membayar beberapa keping gulden yang membuat sais itu keheranan dan kegirangan dan membungkuk beberapa kali di belakangnya. Lucretia menyukai sensasi ketika orang menghamba kepadanya, dan seharusnya Bastiaan pun seperti itu.
Lorong sepi. Suara langkah sepatu Lucretia menggema di langit-langit yang tinggi. Lucretia sampai di pintu kamar rawat Bastiaan. Jeda. Lucretia membuka pintu. Bastiaan terbaring sambil menutup mata. Lucretia merogoh tas kulit buaya. Bastiaan menggeliat lemah. Lucretia menggenggam pisau buah. Bastiaan membuka mata. Lucretia berkata, ”Kau lapar, Sayang?”
Lucretia duduk di dipan Bastiaan dan meraih apel di meja. Dengan perlahan, ia mengupasnya.
”Aku tidak lapar. Oh, kaki ini seperti bukan kakiku. Nyeri sekali. Mungkin membusuk. Oh, Lucretia, bagaimana kalau aku nanti mati?”
”Kau tidak akan mati. Di Batavia, orang lebih gampang mati karena kolera atau malaria. Paling kau hanya pincang saja. Omong-omong, aku menerima surat yang ditulis Catia untukmu. Katanya, ia menunggu di Stads Herberg.”
Raut wajah Bastiaan mengapas. ”Sepertinya aku lapar sekarang. Bisa kau mintakan bubur ke Sust—”
”Sssh, tenanglah. Aku tidak marah. Aku paham itu hanya serangga kecil yang menyusup dalam ruang makan kita yang hangat. Dengan mudah aku, maksudku kita, akan menyingkirkannya.” Lucretia memotong apel-apel itu hingga menjadi potongan kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil hingga seukuran pil kina. ”Jika kau lapar, makanlah apel ini.”
Bastiaan menelan ludah. ”Terima kasih. Itu sepertinya mudah ditelan.”
Bersamaan dengan itu, Bastiaan merasa pijar dalam jiwanya berangsur lindap. Hidupnya akan kembali gudang pengap yang penuh asap. Semua harus sesuai rencana Lucretia, seolah dunia tak akan berputar jika bukan karena campur tangan Lucretia. Sedangkan Catia adalah teka-teki penuh letupan. Tak ada yang harus teratur. Setiap detik adalah kejutan. Catia tak pernah mengarahkannya untuk ini-itu. Matanya selalu berpijar setiap Bastiaan menceritakan rencana hidupnya. Catia membuatnya merasa ada. Catia adalah napasnya.
Lucretia bangkit dari dipan, merapikan gaunnya, dan berkata, ”Aku pulang dulu. Aku harus menyiram gladiol dan memanggang roti kismis.”
Lucretia melangkah tanpa menengok ke belakang. Batavia memang tak seperti impiannya. Tapi ia percaya, jika opera tak memainkan lagunya, ia hanya perlu menyanyikan lagunya sendiri. Dan semua yang rusak hanya perlu diperbaiki seperti ayahnya mereparasi kursi makan mereka yang patah. Menurut ayahnya, jika kursi rusak, kau tak perlu membeli yang baru, cukup betulkan saja yang lama, dan Lucretia pun mengimani keyakinan yang sama. Kini, Lucretia hanya butuh merencanakan kejutan untuk Catia.
***
Sasti Gotama. Emerging Writer UWRF 2022. Pemenang I Hadiah Sastra ”Rasa” 2022.
Rahardi Handining, Sarjana Arsitektur lulusan Universitas Pandanaran, Semarang. Mendapat beberapa penghargaan, antara lain The 4 th Shanghai International Contemporary Art; China pada 2019; Special prize Mellow Art Award Japan, 2020; dan Finalis UOB Painting Of The Year 2021, Kategori profesional.
***
(7)
Kiai Makdum Datang Memburu Tuhan

Oleh A. RANTOJANTI, 14 Januari 2023
Pada hari yang tak disangka-sangka, Diman, seorang pemuda berperawakan kurus tinggi dengan dua gigi seri atas yang menonjol, mendatangi Kiai Makdum. Dengan suaranya yang sengau, Diman mengeluh kepada sang Kiai. Betapa Tuhan itu menyebalkan. Ia, pemuda itu, merasa diolok-olok Tuhan yang memberinya dua gigi seri atas yang menonjol dengan bibir sumbing. Selain membuat tampangnya begitu lucu bagi kebanyakan orang di Jatimaras, dua bagian tubuhnya itu membikin suaranya sengau. Orang-orang yang berbicara dengannya pasti akan menyunggingkan senyum geli bahkan menahan tawa, meskipun Diman sama sekali tidak melawak atau bertingkah lucu. Gigi seri, bibir sumbing, dan suara khasnya membuat Diman ditertawai sejadi-jadinya oleh seisi kampung, terutama anak-anak dan gadis-gadis yang ia goda ketika lewat. Maka jadilah Diman dijuluki Diman Sumbing.
Dengan senyum seorang sepuhnya yang khas, sang Kiai mengangguk-angguk tatkala mendengarkan Diman berbicara. Sebagai seorang pemuka agama yang disegani di Jatimaras, tentu Kiai Makdum sebisa mungkin berusaha mengendalikan sikapnya di depan Diman. Akan tetapi entah apa yang ada dalam pikirannya, Kiai Makdum terus-terusan menyunggingkan senyum. Barangkali senyumnya merupakan bentuk keramahan dan kebijaksanaan seorang sepuh? Atau barangkali pula Kiai Makdum juga tergelitik oleh suara sengau lawan bicaranya? Tak ada yang tahu. Diman sendiri tak ambil pusing. Yang Diman tahu, Kiai Makdum pasti punya jalan keluar. Dengan suara sengaunya yang membikin orang mengernyitkan dahi dan menahan tawa, Diman mengajukan satu pertanyaan kepada Kiai Makdum: di manakah Tuhan berada. Diman ingin betul bertatap muka dan menuntut pertanggungjawaban Tuhan yang telah memberinya gigi seri atas yang menonjol, bibir sumbing, dan suara sengau. Ia tidak ingin jadi bahan lelucon orang lagi.
Tentu pertanyaan Diman yang begitu berani dan menantang membuat Kiai Makdum berhenti menyunggingkan senyum. Bibir Kiai Makdum terkatup rapat. Kelopak matanya yang keriput begitu saja memejam. Dengan satu tarikan napas panjang, Kiai Makdum kembali membuka kelopak matanya dan menatap Diman lekat-lekat. Sebagai seorang pemuka agama yang disegani di Jatimaras dan telah berpengalaman menjawab berbagai pertanyaan keagamaan, terutama tentang Tuhan, Kiai Makdum merasa berkepentingan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Diman. Meski demikian Kiai Makdum cukup paham, orang seperti Diman, meskipun polos, tak akan puas begitu saja jika diberikan jawaban berupa ayat-ayat kitab suci atau riwayat nabi karena perlu bukti nyata yang bisa diindera. Kiai Makdum pun memerlukan sedikit waktu untuk berpikir, sedikit saja.
”Betul kau ingin tahu, Man?”
”Sungguh, Yai.”
Setelah satu tarikan napas panjang, Kiai Makdum bangkit dari duduknya dan menepukkan tangan kanannya ke bahu kiri Diman. Matanya yang mulai redup karena usia memandang jauh ke luar melintasi deretan pohon randu alas di tepi jalan menuju persawahan yang berjarak 100 meter dari rumahnya.
Dari beranda depan rumahnya, Kiai Makdum mengarahkan pandang matanya pada satu-satunya pokok trembesi yang menjulang di antara deretan randu alas di sisi jalan itu. Kiai Makdum berkata bahwa di pokok trembesi itu Diman bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Hanya saja butuh keberanian tingkat tinggi untuk bertemu dengan-Nya. Untuk bertemu Tuhan, Diman hanya perlu memanjat pohon setinggi 12 meter itu sampai pucuk dan memberanikan diri mengempaskan tubuhnya ke tanah. Demikianlah petunjuk sang Kiai sambil mengembangkan senyum pada wajah sepuhnya yang teduh. Kiai Makdum berharap Diman bakal memahami maksud ucapannya. Kiai Makdum bermaksud menghentikan Diman untuk menanyakan keberadaan Tuhan dan berkeinginan menemui-Nya sebab barangkali satu-satunya cara bersitatap dengan Tuhan adalah melalui kematian. Sayang yang di hadapannya adalah Diman, pemuda kampung yang tak paham isyarat. Yang Diman tahu, Kiai tahu segala hal dan bisa dipercaya.
Seperti kebanyakan orang Jatimaras, Diman begitu mempercayai Kiai Makdum sebab kiai adalah ulama, para pewaris nabi. Ia percaya begitu saja dan bermaksud melakukan apa yang disarankan oleh Kiai Makdum tanpa perlu timbang pikir. Maka tepat ketika bulan sabit bertengger di puncak langit dan membentuk bayangan terkecil dari setiap wujud yang disinarinya, Diman memanjat pohon itu sampai pucuk dan mengempaskan tubuhnya ke tanah. Karena sarungnya yang belum dibasuh selama satu minggu dan berlubang di sana-sini tersangkut dahan trembesi, tubuh Diman tak langsung jatuh ke tanah. Hanya saja kepalanya terbentur batang pohon. Diman tak sempat meringis kesakitan sebab benturan keras membuatnya langsung tak sadarkan diri dan tergantung di dahan trembesi.
Dalam ketidaksadarannya, ia merasa bertemu tuhan. Entah tuhan yang mana, ia sendiri tak pernah tahu. Yang Diman tahu, Kiai Makdum tak mungkin berbohong. Maka, apa dan siapa pun yang ia temui tepat setelah jatuh dari pucuk pokok trembesi adalah tuhan, seperti kata Kiai Makdum.
Esok harinya, orang-orang Jatimaras geger. Diman si pemuda sumbing mengaku telah bertemu Tuhan. Ia mengatakan bahwa Kiai Makdumlah yang telah memberinya petunjuk untuk bertemu Tuhan. Karena membawa-bawa nama Kiai Makdum, orang-orang Jatimaras tak berani membantah. Maklum, bagi orang-orang Jatimaras, kiai bukanlah sembarang orang. Sebagai pewaris nabi, perkataan kiai mengandung tulah dan nubuat. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi rumah Kiai Makdum dan memintanya untuk membeberkan cara bertemu Tuhan. Sang Kiai tak habis pikir, isyaratnya kepada Diman telah membuat seisi kampung geger. Kiai Makdum hanya diam. Orang-orang semakin penasaran. Dengan senyum seorang sepuh, Kiai Makdum meminta salah satu warga memanggilkan Diman untuknya.
Diman, pemuda yang dikabarkan telah bertemu Tuhan di pokok trembesi, menghadap sang Kiai tak lama kemudian. Kedatangannya diiringi sorak sorai orang-orang yang menganggapnya sebagai seseorang yang mendapat karunia dan keajaiban karena bertemu Tuhan atas petunjuk sang Kiai. Entah karomah apa, tak seorang pun yang Tahu. Yang orang-orang Jatimaras tahu hanyalah Diman jatuh dari pucuk trembesi tanpa mati dan bersitatap dengan Tuhan seorang diri. Kenyataan bahwa Diman masih hidup dengan kepala benjol pun sudah cukup bukti. Itu cukup ajaib. Sebagai orang yang mengalami peristiwa ajaib atas petunjuk Kiai Makdum, Diman mendapat julukan baru: Wali Sumbing. Diman dianggap sebagai seorang sumbing yang memperoleh pencerahan di pucuk pokok trembesi. Betul wali atau bukan, orang-orang Jatimaras tak betul-betul tahu. Yang mereka tahu bahwa Diman berhasil bertemu tuhan berkat petunjuk Kiai Makdum.
Di hadapan Kiai Makdum Diman menampakkan senyum bangga. Pandang matanya berbinar. Dua gigi seri atasnya yang menonjol terlihat berkilat memantulkan sinar matahari yang masuk melalui celah atap beranda rumah Kiai Makdum. Sorot mata Diman menyiratkan kebanggaan sekaligus rasa terima kasih yang dalam kepada Kiai Makdum. Dalam hatinya, Diman menganggap Kiai Makdum sebagai seorang yang ajaib. Barangkali semacam guru para wali atau mursyid. Atas petunjuk Kiai Makdum, Diman berhasil bertemu tuhan. Entah tuhan yang mana. Tak seorang pun tahu. Yang Diman tahu hanyalah Kiai Makdum tidak mungkin berbohong.
Kiai Makdum tersenyum mendapati Diman di hadapannya. Diman dipersilakannya duduk di kursi beranda. Warga yang penasaran dengan percakapan Diman dan Kiai Makdum terus berdatangan. Halaman rumah Kiai Makdum mendadak penuh sesak seperti pasar malam. Di luar, orang-orang hanya berani berbisik sebab takut suara dari dalam tak kedengaran. Di dalam, Kiai dan Diman saling berhadapan. Tanpa aba-aba Diman bersungkur di hadapan Kiai Makdum dan mencium tangannya. Tanpa Diman katakan, Kiai Makdum paham betul bahwa Diman berterima kasih kepadanya. Kiai Makdum menarik napas dalam-dalam dan menepuk pundak Diman.
”Betul kau bertemu Tuhan, Man?”
”Tidak salah, Yai,” jawab Diman penuh keyakinan.
Kiai Makdum tertegun melihat sorot mata Diman. Betapa Diman yakin betul itu Tuhan. Kiai Makdum merasa dadanya mendadak begitu sesak. Dalam hatinya ia merasakan perasaan yang begitu rumit. Ia ingin betul menyangkal pengakuan Diman bahwa yang ditemuinya belum tentu Tuhan. Pada satu sisi, jika ia lakukan itu tentu Diman dan orang-orang Jatimaras bakal kecewa betul sebab petunjuk dari dirinya tidak seampuh yang mereka harapkan. Pada sisi yang lain mereka juga tidak akan percaya begitu saja perkataan Kiai Makdum sebab yang dialami Diman sesuai petunjuk Kiai Makdum sendiri. Bagaimana mungkin Kiai Makdum tega membohongi Diman, seorang pemuda sumbing yang sekadar bertanya soal Tuhan. Pada sisi lain lain lagi membiarkan Diman dan orang-orang Jatimaras meyakini bahwa Tuhan menemui Diman di pokok trembesi pun tidak mungkin ia benarkan meskipun ia sendiri tidak tahu itu tuhan atau bukan. Selidiknya soal wujud tuhan kepada Diman pun tak akan membuahkan apa-apa.
Dalam kepala Kiai Makdum berpusing berbagai pikiran. Membenarkan pengakuan Diman yang bertemu tuhan merupakan suatu kebohongan. Akan tetapi mengungkap ketidakbenaran pengakuan Diman pun akan dianggap kebohongan. Orang-orang akan menganggap petunjuk Kiai Makdum adalah kebohongan. Dan itu tidak kalah mengegerkan.
”Betul itu Tuhan, Man?” Raut wajah Kiai Makdum menyelidik.
”Yai sendiri yang bilang,” jawab Diman penuh keyakinan.
Baca juga: Bocah di Jembatan Sungai Ular
Wajah Kiai Makdum yang biasanya teduh dan penuh kedamaian mendadak pucat tegang setelah mendapati jawaban Diman yang penuh keyakinan. Butiran keringat dingin mulai menetes dari dahi Kiai Makdum yang keriput dan kusam. Sebagai seorang pemuka agama yang disegani di Jatimaras dan telah berpengalaman menjawab berbagai pertanyaan keagamaan, terutama tentang Tuhan, Kiai Makdum merasa berkepentingan untuk membuktikan sendiri pengalaman Diman.
”Bagaimana caramu bertemu Tuhan, Man?” Tanpa sadar Kiai Makdum melontarkan pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan Diman kepada dirinya sendiri. Yang ditanya ternganga. Diman menjawab persis seperti yang dikatakan Kiai Makdum kepada dirinya tempo hari. Dalam hatinya, Diman betul-betul heran mendapati pertanyaan Kiai Makdum. Bagaimana mungkin Kiai Makdum lupa bahwa ia sendiri yang memberitahu Diman cara bertemu Tuhan. Diman bertemu sosok yang dijanjikan Kiai Makdum. Apa atau siapa pun yang ditemuinya dalam mimpi adalah Tuhan. Sebab ia dan orang-orang Jatimaras percaya, Kiai Makdum tidak akan bohong dan menyesatkan mereka. Kiai adalah pewaris para nabi bagi orang-orang Jatimaras.
Maka tepat ketika bulan sabit hampir menyentuh puncak langit dan menimbulkan bayang-bayang deretan pohon randu alas di sisi jalan menuju persawahan Jatimaras, pintu rumah Kiai Makdum terbuka. Dengan satu tarikan napas panjang, Kiai Makdum meneguhkan hatinya untuk bertolak menuju pokok trembesi itu. Ia ingin membuktikan pengakuan Diman yang bertemu Tuhan atas petunjuknya sendiri. Ia ingin mencapai puncak pohon trembesi dan mengempaskan tubuhnya sendiri. Ia ingin tersangkut dahan dan tak jadi mati. Ia ingin memburu tuhan atas petunjuknya sendiri.
Angin malam yang berembus menjadi saksi tirakat Kiai Makdum memburu tuhan yang ditemui Diman. Keteguhan hati Kiai Makdum membuat tubuhnya serasa muda kembali. Tanpa tarikan napas dalam dan ancang-ancang lebih dahulu, tubuh Kiai Makdum begitu saja menyatu dengan pokok trembesi. Yang mengherankan bahwa dengan tubuh sepuhnya Kiai Makdum berhasil sampai di pucuk pokok trembesi. Sesampainya di sini, tak ada yang tahu apa yang bakal terjadi.
***
A Rantojati, lahir di Cirebon pada 15 Agustus 1992. Ia menulis cerita pendek dan puisi. Selain membaca, ia juga gemar menatap langit dari balik kaca jendela. Sejumlah puisinya terhimpun dalam Buku Nasib (2015) dan Merayakan Pagebluk (2020). Ia bisa disapa melalui akun Instagramnya, @anto.rantojati.
***
(8)
Mengapa Bumi Mengelilingi Matahari

Oleh AVEUS HAR, 12 Januari 2023
Dia telah mengepak semua barang-barang yang hendak dibawanya. Ada dua tas jinjing besar dan satu ransel, semuanya tampak gemuk. Sepertinya hampir semua barang yang dimilikinya telah masuk. Yang tersisa barangkali hanya kenangan: pakaian yang sudah kekecilan, wadah kosmetik tanpa isi, atau perlatan memasak dan rumah tangga yang menjadi dunianya selama di rumah ini. Dia akan pergi, aku tahu, tetapi aku tidak berpikir seserius ini.
Sekarang, dia berdiri di hadapanku dengan wajah tanpa cahaya. Wajah tanpa cahaya itu sudah cukup lama terpasang di sana, dan selama itu aku sering berpikir bagaimana dulu aku melihat cahaya di sana. Barangkali cinta memang menipu.
Ketika aku tidak lagi menemukan cahaya di wajahnya, aku menemukan cahaya di wajah perempuan lain. Kau pasti akan memakiku sebagai laki-laki brengsek, tetapi mengertilah bahwa dalam hal ini aku juga korban penipuan cinta.
Kami menikah karena cinta dan kami berpisah karena menyadari—meskipun tanpa saling menyatakan—betapa cinta itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya letupan gairah, dan letupan itu pun pada akhirnya akan berhenti seperti kembang api kehabisan mesiu.
Sekarang, mesiu kembang api kami telah habis.
Dia melihat gawai, menghela napas panjang, lalu berkata bahwa mobil daring yang dipesannya telah menunggu di luar. Lalu dia menyeret satu tas jinjingnya, membawanya keluar, dan melakukan hal yang sama untuk tas jinjing ke dua, dan masuk lagi untuk mencangklong ransel di punggungnya. Sementara dia melakukan semua itu, aku hanya diam sambil merokok. Aku tidak berkata apa-apa. Semua ini memang sudah direncanakan dan mencegah pun percuma.
Lalu dia menghilang.
Aku masih menghabiskan batang rokokku dan kemudian meletakkan puntungnya di dasar asbak. Rumah ini terasa sunyi. Sejak cahaya di wajah istriku hilang, rumah ini terasa sunyi.
Aku menyalakan sebatang rokok lagi.
Lima tahun lalu kami menikah. Kami bertemu di museum sains. Perempuan itu mengawal anak-anak PAUD dan aku memperhatikan caranya menjelaskan fenomena sains dengan bahasa sederhana. Aku memperhatikan gestur tubuh dan pijar wajahnya. Aku tertarik oleh gravitasi yang besar dalam dirinya. Kami berkenalan, dan tiga bulan kemudian menikah.
***
Aku mencintainya. Dia mencintaiku. Kawan-kerabat banyak berkomentar kami pasangan yang harmonis dan sangat intim. Aku dan dia seperti logam dan magnet dan tidak ada celah untuk lainnya.
Dia keluar dari pekerjaannya sebagai guru PAUD—atas permintaanku, dan aku kemudian keluar dari pekerjaanku sebagai guru honorer sekolah dasar—dengan gaji ala kadarnya, dan kami sepakat membuka kafe. Dia suka memasak dan aku suka jajan—perpaduan yang klop untuk membangun usaha kuliner ini. Kafe kami bernama Orbit—gabungan dari nama kami: Orka dan Bita.
Kafe kami tidak terlalu ramai, tetapi cukup untuk membuat kami bertahan dan bisa membayar beberapa karyawan. Sesekali kami pergi menonton bioskop. Sesekali kami mengunjungi perpustakaan. Aku menyukai menonton bioskop dan dia menyukai membaca; kami melakukan semua bersama.
Dia kemudian hamil. Kami bahagia dan mempersiapkan kehadiran bayi kami—tetapi dia keguguran. Itu peristiwa traumatis baginya, tetapi aku selalu di sisinya dan menghiburnya dan menguatkannya dan mengatakan bahwa segala yang terpenting adalah aku dan dia dan hubungan kami.
Ketika kedua kalinya dia hamil, kami melakukan segala cara untuk membuat janin itu kuat sampai kelak saatnya lahir. Kami berkonsultasi ke dokter dan melakukan apa pun yang disarankannya.
Aku katakan kepadanya untuk tidak mencemaskan apa pun; kami akan tetap bersama dan selalu bersama. Dia tampak memahami maksudku, tetapi cahaya di wajahnya tampak meredup.
Dia keguguran lagi; kali ini dia tampak lebih terpukul dari yang pertama. Kali ini dia tampak putus asa. Namun, aku katakan bahwa semua baik-baik saja selama terus bersama.
Lalu pandemi Covid 19 membubarkan keramaian. Kafe kami tutup dan tidak mampu melanjutkan kontrak tempat usaha. Kami bangkrut. Namun, kami masih bisa membuka layanan antar dari rumah.
Pembatasan aktivitas luar rumah yang diterapkan pemerintah membuat kami mempunyai lebih banyak waktu bersama di rumah, tetapi kuingat justru sejak itu cahaya di wajahnya semakin memuram dan kemudian padam.
Seperti kukatakan sebelumnya, aku menemukan cahaya di wajah perempuan lain dan tertarik oleh gravitasinya dan berhubungan diam-diam. Apakah istriku mengetahuinya atau tidak, tidak bisa kupastikan karena, meskipun kami masih berhubungan seksual sebagai kewajiban, tetapi aku tahu ada yang terasa dingin dan kemudian membeku.
Aku menemukan kehangatan perempuan lain, dan itulah barangkali yang membuat reaksiku terlalu datar ketika dia berkata, ”Aku ingin pergi.”
”Ke mana?” tanyaku.
”Aku tidak tahu.”
”Seusai pandemi mungkin kita bisa pergi.”
”Aku ingin sendiri.”
Aku mengangguk begitu saja.
Itulah yang dilakukannya kini. Sejak pagi dia berkemas tanpa bicara dan hanya mengatakan ’akan pergi’. Lalu dia pergi, benar-benar pergi, lepas begitu saja seperti daun kering ditiup angin.
***
Setelah dia pergi, aku keluar untuk makan. Rasanya seperti berjalan dengan tubuh separuh mati. Makan dengan mulut separuh katup. Duniaku menjadi dunia separuh, tidak utuh.
Meskipun aku sebelumnya berhubungan dengan perempuan lain, setelah dia pergi aku justru tidak ingin melanjutkan hubungan dengan perempuan lain lagi.
Selama hampir dua bulan aku menjalani hidup dengan perasaan asing pada duniaku. Pada hari ke-56, seorang kawan lama mendatangiku. Dia bertanya siapa yang membuat desain gambar dinding kafe kami dulu dan aku menjawab itu kubuat sendiri. Dia bilang aku berbakat dan dia menyukai itu. Dia mempunyai usaha daring dan membutuhkan tukang desain untuk konten media sosial. Lalu dia memintaku mengisi lowongan itu jika mempunyai waktu luang.
”Aku menganggur,” kataku.
”Bayarannya mungkin tidak banyak,” katanya.
”Tidak apa-apa; aku suka mengerjakan desain.”
Pekerjaan membuatku sedikit melupakan kekosongan dalam diriku. Kemudian beberapa orang lain juga memberiku pekerjaan lepas mendesain sehingga aku cukup sibuk, tetapi aku menikmatinya.
Saat-saat tertentu aku berkumpul dengan mereka dan membicarakan gagasan-gagasan kreatif untuk konten berikutnya. Saat-saat lain aku bertemu teman-teman lama dan kami melewatkan waktu bersama: bermain biliar, menonton bioskop, mengunjungi pameran otomotif, menyaksikan pertandingan bola.
Sejauh itu, tidak ada yang bertanya tentang istriku. Apakah mereka sesungguhnya tahu tentang kepergiannya dan tidak menyinggungnya demi perasaanku? Mungkin demikian; aku juga tidak peduli. Yang terpenting adalah aku telah kembali seperti dulu.
Benar bahwa dalam diriku masih ada lubang oleh kepergiannya. Namun, aku pikir sebelum kami menikah hidupku baik-baik saja. Artinya, sesungguhnya setiap kita mempunyai lubang itu, tetapi sebelum bertemu orang yang tepat dan kemudian kehilangan, kita tidak merasa mempunyai lubang.
Meskipun demikian, aku masih sering mengunjungi museum sains itu sekadar untuk kenangan.
***
Lima bulan setelah dia pergi, aku melihatnya lagi di museum sains. Dia bersama sekelompok kecil remaja tanggung, menjadi pemandu mereka. Dia menolehiku sekilas, tetapi tidak ada perubahan apa pun pada roman mukanya seolah aku hanya orang asing seperti pengunjung lainnya. Aku memperhatikan roman wajahnya, ekspresinya, gestur tubuhnya, dan cara bicaranya ketika menerangkan fenomena-fenomena sains pada sekelompok remaja itu.
Aku melihat cahaya di wajahnya. Aku merasakan gravitasi yang besar dari dirinya. Aku berada dekat dengannya sekarang, tetapi dirinya hanya untuk sekelompok remaja itu, menerangkan mengapa gravitasi matahari tidak membuat bumi menubruknya, alih-alih hanya mengelilingi.
”Karena bumi mempunyai inersia,” katanya. ”Gaya ini akan menjauhkannya dari matahari, tetapi ditahan oleh gravitasi sehingga terciptalah orbit yang membuat bumi hanya mengelilingi matahari—tidak menjauh, tidak pula menubruk.”
Dia menoleh padaku sesaat, tanpa ekspresi, lalu kembali pada sekelompok remaja itu.
”Dalam bahasa hubungan,” katanya lagi, dalam nada yang lebih lambat,
”Bumi mencintai matahari, tetapi ia juga mencintai diri sendiri.”
Aku memperhatikan perutnya yang buncit. Kami akan mempunyai anak, pikirku, jika tidak keguguran lagi.
***
Aveus Har, tinggal di Pekalongan. Kesehariannya adalah seorang pedagang mi ayam sembari bereksperimen di Laboratorium Ide dan Cerita (LABITA). Novel terbarunya berjudul FORGULOS.
***
(9)
Ciu dan Durian Tembaga

Oleh WIDJAYA HARAHAP, 8 Januari 2023
Tanak sudah rindu didendam, masak sudah sesal diperam.
Lelaki paruh baya itu menyesali nasihat yang pernah ia berikan kepada anak sulungnya. Kalau tahu bakal begini jadinya…, gumamnya dalam hati. Berulang kali.
Tiga bulan terakhir ini orang-orang lebih sering melihatnya duduk mengarca di sudut kebun sayur. Tempayan berlumut jadi temannya berdiam diri. Ia selalu duduk di tempat yang sama, di sisi tempayan itu. Yang mengenalnya, merasa ganjil melihat kejadian ini. Bukan kebiasaan Akong menyendiri begitu.
Lepas tengah hari setelah rampung pekerjaan mengurus dan memanen tanaman di kebun sayur, biasanya ia duduk-duduk di bawah rimbun pohon angsana di halaman gudang asap. Makan angin dan berbual-bual dengan siapa saja yang berada di situ. Ketika musim bunga angsana mengorak warna, meski tanpa sesiapa pun yang diajak bicara, ia tahan berjam-jam menengadah memandangi tajuk pohon yang disepuh warna kuning. Pesona alam yang umurnya hanya sekelebat. Tiga hari setelah mekar, gerumbul kuning itu pun berguguran. Menyisakan kenangan. ”Bunga angsana itu menampil tamsil hidup,” ujarnya sekali waktu. ”Dunia ini keindahan yang sementara.”
Sementara itu, sudah tiga bulan pula tak ada lagi ritual duduk di bawah rimbun angsana.
Makin dekat Imlek menjelang, makin risau Akong mengenang. Hari raya Imlek nanti genap tiga tahun putra sulungnya tidak pulang. Mudik, berhari raya bersamanya. Bertumpuk-tumpuk rindunya kepada sang cucu. Sekarang pasti ia sudah tinggi. Sudah tujuh tahun umurnya. Semenjak istrinya meninggal dunia lima tahun silam, tinggal anak dan cucunyalah yang menjadi tempat dirinya menumpang kasih menggantungkan sayang.
Hasrat ingin bertemu cucu laki-lakinya bagaikan terjangan air bah. Setiap saat tanggul jiwanya bisa terban karena tak kuasa menahankannya. Tapi kenapa Kim Tek tidak memedulikan perasaan ayahnya? Apa dia tak tahu, kalau rindu anak serasa mabuk, rindu cucu serasa sakau? Tunggulah nanti kalau ia sudah bercucu, baru dia tahu rasa.
Akong sedih anaknya tidak membalas guna. Kasih sayangnya kepada mereka sia-sia belaka. Pedih hati mengenang pengorbanannya membesarkan dan mendidik. Ia rela bertahun-tahun makan bubur yang hanya bercampur sayuran pakcoy dan bawang putih asalkan Kim Tek dan adiknya Kim Eng bisa bersekolah hingga SMA. Sekarang balasan apa yang kudapat? Kim Eng, sudahlah. Dia mengikuti suaminya bermukim di Taipei. Jauh dan mahal ongkos pulangnya. Sudah bagus lima tahun yang lalu bisa menyempatkan pulang ketika ibunya meninggal. Biarpun tidak sempat melihat jenazahnya. Tapi Kim Tek? Jarak 500 kilometer saja sudah jadi penghalang. Padahal tidak harus tergantung kepada kendaraan orang lain.
Beberapa kali pernah ia mendengar Kim Tek mengeluhkan betapa membesarkan usaha merampas segenap waktunya. Semenjak lima toko mini market Hokimaret, yang dibangunnya bermodalkan sebuah kedai sampah kecil, menyebar hingga ke pinggir kota, dia tertungkus lumus mengurusnya. Kim Tek berdalih dia tidak berani meninggalkan usahanya barang sekejap, semata-mata karena mengamalkan nasihat ayahnya.
Akong mengenang dulu—sewaktu putra sulungnya itu baru jadi toke sebuah kedai sampah—sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun Kim Tek menggiring istri dan anaknya pulang mengunjungi ayah ibunya. Ketika itu Kim Tek sering berkeluh kesah tentang usaha kedai sampahnya yang dirasakannya kok tidak maju-maju. Ia memberikan petuah untuk dipatuhi oleh Kim Tek kalau dia bertekad memajukan usaha. Usaha adalah bayi yang wajib dirawat sendiri. Jangan pernah percayakan mengurusnya kepada orang lain. Sekecil apa pun usaha itu. Apalagi kalau sudah besar. Kepada Kim Tek Akong mengisahkan bagaimana dulu, sewaktu kedua anaknya masih bersekolah ia berjualan sendiri sayuran hasil kebunnya ke kedai-kedai nasi dan menjajakannya di hari-hari pekan.
Sekarang nasihatnya itulah yang diamalkan oleh Kim Tek, tampaknya tuntas sampai ke titik komanya. Sehingga kini, dalam syak wasangka Akong, malah dijadikan Kim Tek sebagai dalih tidak sempat menjenguk ayahnya. Apakah dulu aku salah menyampaikan nasihat itu sehingga anakku keliru memahami maksudnya? Pikiran itulah yang terus-terusan mengganggu Akong.
Memang setelah A Bu (panggilan anak-anaknya kepada ibu mereka) meninggal dunia, dua kali hari raya Imlek, Akong masih ditemani anak, menantu, dan cucu. Sekarang sudah lain ceritanya. Sudah tiga Imlek, Akong hanya termangu-mangu mengharapkan kedatangan anak-cucunya yang tidak kunjung tiba.
Untunglah ada Awang yang sedikit jadi pelipur lara. Awang, anak bungsu Pak Alang penjaga gudang asap. Akong merasa kehadiran Awang yang sebaya dengan cucunya, jadi penawar rindu kepada cucunya yang jauh. Bocah laki-laki ini sudah nampak lasaknya sejak dia mulai bisa berjalan. Rumah mereka yang berdekatan memudahkan Awang sering datang merecokinya. Awang gemar menyerakkan sayuran hasil panen yang sudah disusun Akong menunggu dijemput pembeli. Tak pernah ia jengkel, apalagi marah atas ulah si Awang. Sebaliknya ia merasakan kehadiran bocah itu menjadi penghibur. Serasa cucunya sendiri yang menemani. Sampai Awang berumur lima tahun, setiap pagi setelah terjaga, Akong selalu berteriak memanggilnya. Awang pun berlari menuju kebun sayur. Akong akan mengangkatnya agar Awang bisa tegak di atas bangku di sisi tempayan. Setelah tutupnya dibuka, memancurlah air kencing Awang menambahkan bau pesing ke dalam tempayan itu. Sesudah diperam berbulan-bulan, nanti Akong menggunakannya untuk memupuk sayuran.
Ketika Awang berusia dua tahun Akong memberanikan diri mengajuk hati pak Alang. Memohon agar diperbolehkan mengakui Awang sebagai cucunya. Cucu pungut, begitulah istilahnya. Memahami kesepian Akong, Pak Alang tidak berkeberatan. Begitulah ceritanya lima tahun sudah Awang berbaju baru bukan hanya waktu hari raya Lebaran, tapi di hari raya Imlek juga. Dua hari sebelum Imlek, Akong akan mengantarkan dua setel celana dan kemeja baru bersama satu nampan selebar tampah berisi manisan buah-buahan. Manisan buah kana kesukaan Awang tak pernah ketinggalan. Tak ada yang lebih menggembirakan Akong selain melihat senyum lebar yang menjepit mata Awang menjadi sipit tatkala menerima angpao di hari Imlek. Satu-satunya penghiburan meringankan kesedihan dan kesepian di ambang senja usia.
Hari raya Imlek tinggal dua hari lagi. Seperti lazimnya pagi itu Akong datang ke rumah Pak Alang membawakan bungkusan berisi pakaian baru dan nampan penuh berbagai jenis manisan untuk diserahkan kepada Awang. Sejenak setelah duduk, Akong menarik keluar sesuatu dari saku kemejanya. Angpao! Diangsurkannya kepada Awang.
”Kenapa sekarang, Kong?” selidik Awang diliputi rasa heran.
”Nggak apa-apa. Janji jangan dibuka dulu! Bukanya lusa pas Imlek ya!” Anak kecil itu mengangguk, tapi masih melanjutkan bertanya,
”Kenapa tidak dikasihkan lusa saja?”
”Siapa tahu Akong tidak sempat.”
”Akong mau ke mana?”
”Oh, tidak ke mana-mana.”
Awang mendekat, menjemba tangan kanan Akong dan menciumnya. Akong mencium ubun-ubun Awang, melepas kacamata dan menyeka kedua pelupuk matanya. Pak Alang dan istrinya terdiam bagai tunggul kayu, menyaksikan adegan itu. Keduanya lalu mengusap mata yang basah.
Imlek tinggal sehari. Akong melangkah menuju pekan. Ia mencari keramaian yang mungkin bisa jadi perintang-rintang rasa sepi. Tampak olehnya sekelompok orang yang mulai berkumpul mengitari seorang pedagang. Tak salah lagi, pikirnya: tukang koyok. Dengan terhuyung-huyung Akong menghampiri. Kepalanya disergap pening hingga telinganya berdenging. Lehernya terasa kaku dan rahangnya menegang. Ia menyelusup di antara penonton dan berdiri di barisan depan. Di sebelah kiri dilihatnya Awang berjongkok. Ia pun ikut berjongkok.
”Haiyya, Awang bolos sekolah ya?”
”Kan hari Minggu, Kong.”
Sejenak kemudian ia bersendawa. Aroma yang tajam, dari barang yang baru saja dimakan dan diminum, menikam hidungnya. Menguar dari semburan napasnya. Ia berusaha memalingkan wajah dari Awang ketika menyadari usahanya terlambat.
”Akong mabuk ya?” tanya Awang khawatir.
”Tidak.”
”Muka Akong merah, macam udang direbus!”
Ada dua tiga kali lagi ia bersendawa, sebelum menengadah ke langit. Agak lama. Dadanya terasa bagai diimpit batu besar. Dari mulutnya yang menganga ia mendengar suaranya sendiri serupa paduan sendawa dan dengkur. Setelahnya ia tidak ingat apa-apa lagi.
***
Awang dan beberapa orang lain terpekik melihat Akong tergelimpang di antara kaki-kaki orang-orang yang tengah menonton. Orang ramai membopong dan melarikannya ke puskesmas. Saat dokter tiba, Akong sudah tiada.
***
Kim Tek termenung selepas mendengar penjelasan dokter. Hasil pemeriksaan: Akong mendapat serangan jantung. Dia tahu, hingga di usia ayahnya yang menginjak enam puluh tahun itu, tidak pernah mengidap sakit selain pilek dan batuk. Tak ada gaya hidup Akong yang berakibat merongrong kesehatan. Tidak merokok, tidak pula meminum ciu. Tentang ciu malah Akong yang mewanti-wanti dirinya, ”Jangan coba-coba makan durian bersamaan minum ciu. Itu namanya cari mampus. Sudah banyak kawanku yang mati.”
Darah Kim Tek berdesir. Dia bangkit dan menuju dapur. Di salah satu sudutnya berlampar kulit dan biji-biji durian. Dia membuka lemari tempat ayahnya menyimpan makanan. Di dalamnya duduk botol ciu yang isinya nyaris tandas. Dan piring, yang menyisakan satu lunas buah durian tembaga.(*)
Catatan:
Akong: Kakek, tutur bahasa Hokian.
Gudang asap: Bangunan tempat mengeringkan getah karet dengan cara mengasapinya.
Makan angin: Berleha-leha, bersantai.
Kedai sampah: Sebutan untuk toko kelontong di Tanah Deli.
***
Tukang koyok: Tukang jual obat keliling. Koyok dalam bahasa dialek Melayu Deli artinya membual.
Widjaya Harahap, dilahirkan 65 tahun silam di sebuah kampung di pesisir timur Sumatra Utara. Kini bermukim di Ciamis, Jawa Barat. Menekuni penulisan cerpen dan puisi.
Bonie Sudarso, lahir di Bandung 14 Mei 1974. lulus Kriya Tekstil-STISI Bandung (2000), Selain dikenal sebagai desainer pada 16 pabrik tekstil dikawasan Bandung, juga vendor beberapa Distro. Beberapa penghargaan yang diperoleh antara lain Juara Ke 2 Lomba Desain Motif Batik Komar (2013) dan Juara Harapan 1 Sayembara Desain Motif Bandung (2014). Sejak 2017 sudah lima kali pameran tunggal, dan sekali pameran bersama.
***
(10)
Bocah di Jembatan Sungai Ular

Oleh ABUL MUAMAR, 7 Januari 2023
Sebuah mobil SUV hitam berjalan lambat. Kacanya ditutup rapat-rapat. Pengemudi di dalamnya tak menghiraukan bocah yang mengikutinya dengan setengah berlari, dan tetap menginjak pedas gas mobilnya dengan pelan seraya menghindari lubang di sana-sini. Begitu tiba di seberang jembatan, mobil itu melaju sekencang-kencangnya. Si bocah menatap mobil itu mengecil diremas jarak, dengan cangkul yang ditopang di atas pundaknya.
Jembatan itu menghubungkan jalan lintas Sumatera di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Sekitar 200 meter di sebelah selatan, paralel dengan jembatan jalan itu, ada jembatan jalur kereta api dengan ornamen besi melengkung membentuk separuh oval. Dari atas jembatan itu, corong pabrik kelapa sawit Adolina tampak menjulang di sebelah timur. Corong pabrik itu mengepulkan asap pekat saban pagi dan petang. Di bawah jembatan, air Sungai Ular tampak keruh.
Bertahun-tahun yang lalu, hanya anak-anak yang tak takut pada sabetan ranting kayu ibunya yang berani bermain di bawah jembatan itu. Sering anak-anak hanyut karena nekat mandi di situ dan menjadi mayat ketika ditemukan. Orang-orang bilang bahwa mereka menjadi santapan sepasang buaya putih yang bermukim di sana. Kenyataannya, buaya putih itu hanyalah mitos yang disebarluaskan untuk mengaburkan fakta sejarah mengenai pembantaian orang-orang yang menjadi korban politik Orde Baru—mereka yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia dan para pendukungnya.
Selama ratusan tahun, sungai itu menjadi sumber kehidupan bagi warga puluhan desa di wilayah Deli Serdang, sebelum Serdang Bedagai mekar. Banyak warga menggantungkan hidup pada sungai itu, terutama para petani. Di sungai itu juga, dulu warga sering menangkap ikan atau udang. Sekarang, kecuali airnya yang masih tetap dipakai untuk mengaliri sawah dan menyirami ladang singkong yang ditanam oleh para petani penggarap di sepanjang bantaran, sungai itu nyaris sepenuhnya beralih fungsi menjadi lahan tambang pasir illegal. Tambang pasir itu beroperasi dengan leluasa atas izin dari pejabat setempat.
Para penambang pasir itu semula mengeruk pasir secara tradisional dengan menggunakan tapisan yang biasa dipakai untuk menyiangi beras. Belakangan, keberadaan pasir yang melimpah di sungai itu membuat pemodal tergiur, lalu mereka menyediakan puluhan mesin penyedot berbahan bakar minyak. Dengan alat itu, dalam sekejap berton-ton pasir menggunung di pinggir sungai. Puluhan truk hilir mudik setiap hari mengangkut pasir yang masih setengah basah. Berat beban truk-truk itu membuat akses jalan menuju sungai menjadi rusak tak karuan. Residu minyak yang merembes keluar dari mesin penyedot pasir membuat air sungai berminyak dan kian keruh dari hari ke hari. Daratan-daratan kecil terbentuk di sana-sini di tengah sungai akibat penambangan tak berkesudahan.
Sudah sejak pagi bocah itu berada di jembatan itu. Ia belum makan. Yang ia telan hanyalah dua buah ciplukan setengah matang yang ia petik di pinggir sungai di bawah jembatan. Perutnya semakin keroncongan karena pengaruh asam ciplukan. Ia ingin makan, tapi ia belum mendapatkan uang.
Bocah itu memakai kaos berwarna hitam kelabu yang sudah belel dan kerahnya mengeriting karena terlalu sering dicuci. Celana pendek merah yang memadu kaosnya adalah celana yang dulu ia pakai saat sekolah. Ia bertelanjang kaki dan memakai topi sekolah dasar berlambang Tut Wuri Handayani yang telah kumal dan tak lagi berwarna merah. Topi itu terakhir kali ia pakai saat upacara bendera lewat setahun yang lalu sebelum ia berhenti sekolah. Ibunya tak sanggup membiayai sekolahnya. Iuran bulanan di sekolahnya terus naik dan buku-buku paket pelajaran terus berganti setiap tahun mengikuti perubahan kurikulum, dan ia diwajibkan membeli jika ingin mendapat nilai bagus.
Bocah itu menunggui kendaraan yang melintas. Dengan cangkul yang lebih tinggi dari badannya, ia menimbun lubang-lubang yang ada di jembatan itu dengan tanah. Jembatan itu sebenarnya sudah berkali-kali diaspal, namun kondisinya tak pernah bertahan lebih dari tiga bulan. Aspal akan segera terkelupas seperti lapisan cokelat yang lepas dari kue brownies.
Ketika ada kendaraan yang melintas, bocah itu akan mencangkul dan meratakan tanah untuk menutupi lubang, lalu cepat-cepat menadahkan topinya. “Pak, seikhlasnya, Pak… Bu, seikhlasnya, Bu…,” katanya.
***
Bocah itu melakoni pekerjaan sebagai penambal lubang di jembatan Sungai Ular sejak setahun yang lalu, saat masih berstatus sebagai siswa di sebuah SD negeri di Desa Sukamandi Hulu, Pagar Merbau. Suatu siang, dalam perjalanan pulang dari sekolah, ia menyingkirkan batu-batu kerikil dan pecahan aspal yang berserakan di jembatan dengan kakinya, dan menutupi lubang dengan pasir yang tumpah dari bak truk pengangkut pasir. Terharu melihat penampilan kumalnya melebihi tindakan heroiknya, seorang pengendara mobil Starlet lawas berwarna merah menghentikan laju dan memanggilnya, memberinya selembar uang Rp 50 ribu.
“Jangan main di sini, Dik. Bahaya!” pesan pengendara itu seraya mengulurkan uang. Bocah itu mengangguk dengan wajah polosnya. Senyum riangnya menampakkan gigi ompongnya.
Saat tiba di rumah, ia tak mempermasalahkan ibunya yang belum memasak lauk. Dengan uang itu, ia mengisi perut keroncongannya dengan bakso bakar—jajanan kesukaannya. Sisa uang yang ia pegang ia berikan kepada ibunya yang lantas memeluknya erat sambil menangis.
Keesokan harinya, ia mengulangi tindakannya. Namun kali itu, tak ada pasir yang tumpah dari bak truk pengangkut pasir sehingga ia tak bisa menutupi lubang. Siang itu, ia memang memperoleh pemberian dari seorang pengendara motor Astrea Star setelah berjam-jam berdiri di sana, namun hanya Rp10.000. Pemotor itu memberinya uang karena kasihan melihatnya celingak-celinguk seorang diri di jembatan seperti anak pengemis yang ditinggal ibunya.
Setelah siang itu, ia sempat berhenti mencari uang di jembatan itu selama dua minggu. Sampai pada suatu pagi, dalam perjalanan berangkat ke sekolah, gagasan cemerlang melintas di kepalanya. Di bantaran sungai, terlihat olehnya tanah gembur. Tanah itu menjadi gembur seusai petani penggarap memanen singkong yang mereka tanam dan bersiap-siap memulai untuk menanam yang baru. Di ujung sebelah barat tanah gembur itu ada plang bertuliskan ‘Tanah Ini Milik Pemerintah’, namun ia tak peduli. Dalam benaknya, ia mengira pemerintah adalah manusia, tetapi manusia yang bernama pemerintah itu tak pernah ia rasakan kehadirannya. Karena itulah, ia tidak takut sama sekali dengan peringatan di plang itu.
Bermodal cangkul yang biasa dipakai oleh ibunya untuk menimbun tahi selepas buang hajat di samping gubuk mereka, siangnya ia berangkat dengan membawa karung bekas kosong. Karung bekas itu ia isi dengan tanah gembur yang ia ambil dari lahan di pinggir sungai berstatus milik pemerintah itu. Tubuh kecilnya mengangkut karung berisi tanah ke atas jembatan. Itulah awal mula ia berhenti sekolah. Ia masih duduk di bangku kelas 5 saat namanya dicoret dari daftar siswa.
Tanah itu kemudian ia tuang ke beberapa lubang yang ada di jembatan. Melihat jumlah dan ukuran lubang yang ada, satu karung tanah jelas tak cukup. Bahkan, satu lubang saja pun tak bisa ditutup dengan pejal hanya dengan satu karung tanah. Menyadari hal itu, ia tersenyum karena itu berarti ia bisa terus bekerja di jembatan itu selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dan memperoleh banyak uang dari para pengendara yang lewat. Pada akhirnya, ia benar-benar melupakan sekolahnya. Ibunya, yang tak bisa bekerja apa-apa karena diserang penyakit lupus semenjak ditinggal mati oleh ayahnya, tak bisa melarangnya untuk mencari uang.
***
Setahun menjadi penambal lubang di jembatan itu, pengendara yang bermurah hati padanya semakin sedikit. Dalam sehari, tidak tentu ada pengendara yang memberinya uang. Sementara bocah penambal lubang di jembatan itu semakin bertambah. Anak-anak lain itu mengikuti jejaknya karena tergiur dengan uang yang bisa mereka peroleh. Setiap hari, setidaknya ada empat hingga lima bocah penambal lubang di jembatan itu selain dirinya. Namun, bukan karena kehadiran pesaing yang membuat penghasilannya berkurang. Penyebabnya lebih karena para pengendara yang melintas di jembatan itu lama-lama tahu bahwa bocah-bocah itu tak sungguh-sungguh menimbun lubang. Di jembatan itu, masih banyak lubang lain yang sama sekali tak ditutupi. Bocah-bocah itu hanya sekadar mengulang-ulang menutup dan membongkar tanah di lubang-lubang yang sama setiap hari. Dan semakin hari, bocah-bocah itu semakin tak sungkan meminta-minta uang, membuat para pengendara kehilangan rasa iba.
Suatu petang, ketika ia baru memperoleh Rp4.000 dan hanya tinggal ia seorang di jembatan itu, ia bertemu dengan beberapa pria yang mengenakan pakaian dan helm proyek. Mereka tampak sedang melakukan pengukuran di jembatan itu.
“Hei, sedang apa kau di situ?” bentak salah seorang dari mereka.
“Untuk apa kau pegang-pegang cangkul?’ timpal rekannya.
“Untuk menutup lubang, Pak.”
“Tidak perlu! Ini jalan mau diperbaiki. Pergi sana!”
Dibentak begitu, nyalinya menciut. Ia pun pergi dari jembatan itu, tertunduk lesu memanggul cangkul dan karung bekasnya. Sinar matahari petang menyorot langkah kaki gosongnya menuju gubuk beratap daun rumbia di bantaran sungai yang ia tempati bersama ibunya.
***
Tak sampai sebulan kemudian, jalan aspal di jembatan itu sudah mulus seperti disulap. Kali ini, material yang digunakan lebih berkualitas daripada biasanya lantaran presiden dan rombongannya akan datang berkunjung pekan depan. Trotoar dan besi pembatas di sisi kiri dan kanan jembatan itu juga dicat ulang dengan warna hijau-kuning cerah khas Tanah Deli.
Dari atas jembatan jalur rel kereta api, mata bocah 11 tahun itu berkaca-kaca menyaksikan jembatan jalan itu mulus dan cantik. Tidak ada lagi lubang-lubang yang bisa ia tutupinya dengan tanah. Kendaraan-kendaraan melaju dengan kencang. Melamun menatap jembatan itu di sebelah utara, bayangan ibunya yang terbaring tak bergerak di dipan bambu melintas di kepalanya. Ia kini hidup sebatang kara. Dari arah barat, kereta api jurusan Medan-Tanjungbalai mendekat. (*)
***
Abul Muamar, lahir di Perbaungan, Serdang Bedagai. Menulis beberapa cerpen sejak 2013.
***
(11)
Ramalan

Oleh RISEN DHAWUH ABDULLAH, 5 Januari 2023
Kematian Mat Sumbing memang sudah diramalkan sebelumnya oleh Ali Sudiyono. Lelaki berusia tiga puluh lima tahun itu meramalkan, jika kematian Mat Sumbing terjadi akibat terseret arus sungai yang deras di musim hujan, tetapi tidak dijelaskan mengapa Mat Sumbing sampai bisa terseret. Orang yang pertama kali mendengar ramalan Ali Sudiyono ialah Yu Giwang, seorang perempuan pemilik toko kelontong di kampungnya. Itu dikatakannya setelah Yu Giwang sedikit jengkel dan mengeluhkan Mat Sumbing yang berutang padanya dan tidak dibayar-bayar. Ali Sudiyono mengatakan hal itu, bukan karena ia ikut merasakan kejengkelan Yu Giwang. Ramalan itu tidak didorong hal tersebut.
Kebenaran ramalan Ali Sudiyono memang tidak hanya kali itu saja. Ali Sudiyono memang sudah terkenal sebagai ”tukang ramal”, dan hampir semua ramalannya tidak meleset. Jika ia meramalkan sesuatu yang buruk—apalagi akan terjadi di kampungnya—orang-orang akan siaga mempersiapkan antisipasinya meski akhirnya tidak berarti apa-apa. Ramalan Ali Sudiyono seperti tidak lebih dari sebuah takdir. Bila hal-hal baik, tentu tidak akan menimbulkan kegelisahan. Meski begitu, bukan berarti semua orang percaya. Tidak sedikit yang menganggap jika ramalan Ali Sudiyono hanya kebetulan belaka, apalagi mereka yang beragama kuat.
Dari banyaknya ramalan Ali Sudiyono, yang paling diingat oleh warga ialah ramalannya pada tahun lalu. Mungkin karena ramalannya terjadi di hari kemerdekaan, yang kemudian mengendap begitu lama di hati warga. Ali Sudiyono meramalkan kalau di hari kemerdekaan akan ada maling di kampungnya. Benar. Si maling memanfaatkan situasi, para warga yang sebagian besar hadir dalam acara tirakatan. Sebuah sepeda motor antik milik salah satu warga berharga ratusan juta raib. Ali Sudiyono mengucapkan ramalannya pada seorang tetangga yang tinggalnya dekat dengan pemilik sepeda motor antik yang hilang itu. Ada yang menyalahkan Ali Sudiyono; tidak memberi tahu semua warga, bila hal itu akan terjadi.
”Itu sudah takdir,” dalih Ali Sudiyono. ”Kehendak Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi, sekalipun aku mengatakannya pada semua orang.”
”Setidaknya ada usaha, dan tidak semengecewakan ini.”
Ali Sudiyono memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Pemiliknya sendiri yang teledor, tidak mengunci setang sepeda motor dan gerbang rumah dalam keadaan terbuka. Ali Sudiyono terkadang takut juga menyampaikan apa yang ada di kepalanya—ia bahkan pernah mengambil kemungkinan terburuk; dikeroyok warga kampungnya bila yang ia sampaikan hal buruk—tapi ia lebih kerap tidak bisa memendamnya.
Sebelum meramal kematian Mat Sumbing, Ali Sudiyono meramal jika kandungan Maria, perempuan dua puluh tahun yang hamil setelah diperdaya pacarnya, akan mengalami keguguran. Pacar Maria tidak bertanggung jawab dan hilang ditelan bumi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan pacar Maria. Banyak warga yang mencemooh Maria; bagi mereka permasalahan ada, Maria sendirilah yang menciptakannya. Namun, ada yang menyambut dengan gembira ramalan Ali Sudiyono. Orang yang gembira tersebut tak lain orang yang kasihan dengan Maria. Keguguran janin Maria benar terjadi. Maria dikuasai dua perasaan, sedih dan senang.
”Aku sendiri tidak tahu, kenapa bisa begini. Aku bahkan tidak merasa memiliki kemampuan ini. Aku hanya menyampaikan apa yang tergambar dalam kepala. Jadi kukira agak aneh aku disebut peramal, sebab aku sudah melihat bayang-bayang di kepala,” ucap Ali Sudiyono kepada Markun, tukang roti keliling yang lewat kampungnya.
”Kau indigokah?” tanya Markun.
”Entah,” kata Ali Sudiyono. ”Yang jelas orang-orang tetap menyebutku tukang ramal.”
Ali Sudiyono juga tidak tahu, sejak kapan kemampuan itu bersemayam padanya. Orangtua Ali Sudiyono yang bergelar tukang ibadah karena rajin sekali ke masjid tidak terlalu peduli dengan kemampuan Ali Sudiyono dan omongan tetangga. Orangtua Ali Sudiyono berada di pihak orang yang menganggap apa yang diramal Ali Sudiyono hanya kebetulan belaka.
Untung pihak keluarga Mat Sumbing tidak berbuat macam-macam terhadap Ali Sudiyono. Keluarga Mat Sumbing banyak berterima kasih kepada Ali Sudiyono telah melayat, turut berbelasungkawa atas kepergian Mat Sumbing. Ya. Keluarga Mat Sumbing benar-benar tidak mengapa-apakan Ali Sudiyono. Misalnya Ali Sudiyono dituduh membunuh Mat Sumbing karena suatu hal, sebelum itu telah meramalkan kalau matinya Mat Sumbing terbawa arus sungai yang deras. Lalu keluarga Mat Sumbing yakin, jika ramalan itu hanya tameng atas perbuatannya. Sama sekali tidak. Keluarga Mat Sumbing benar-benar tidak melakukan apa pun terhadap Ali Sudiyono.
Entah ucapan apa lagi yang keluar dari mulut Ali Sudiyono, dan akan terjadi di kemudian hari. Beberapa orang setia menunggu, dan diam-diam mengagumi Ali Sudiyono. Mereka hanya ingin mendengar Ali Sudiyono meramal—bagi mereka, mendengar Ali Sudiyono meramal seperti mendapatkan suatu kepuasan.
Ada orang yang sampai ingin anaknya kecipratan kemampuan Ali Sudiyono, sampai-sampai si orangtua menyuruh anaknya untuk sering bergaul dengan Ali Sudiyono, dengan alibi tertentu. Membenarkan mainan yang rusak, menyuruh Ali Sudiyono untuk mengajari mengerjakan pekerjaan rumah, atau hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan untuk bisa ketemu dengan Ali Sudiyono. Dengan sendirinya, bila sering ketemu akan tercipta keakraban. Dari situ, si orangtua yang menaruh harap pada anaknya agar menguasai kemampuan sebagaimana Ali Sudiyono, yakin kalau Ali Sudiyono bakalan menurunkan ilmunya. Ali Sudiyono bukan orang yang pelit. Setiap ada yang datang padanya, dan sedang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apa pun jarang ia tolak, selama ia bisa mengerjakan.
Entah apalagi ucapan yang keluar dari mulut Ali Sudiyono, dan akan terjadi di kemudian hari. Sudah dua minggu Ali Sudiyono tidak meramalkan apa-apa. Sebulan pun lewat. Ali Sudiyono tidak mengeluarkan satu ramalan pun. Orang-orang yang menunggu Ali Sudiyono gereget menunggu.
”Telingaku sudah sangat ingin menangkap ramalanmu.”
”Iya. Meramal apa sajalah. Masa tidak ada? Meramal masa depan negeri ini juga bisa.”
”Iya, apa saja.”
Ali Sudiyono terus didesak untuk berujar. Ia tetap tidak meramal. Sekali lagi, Ali Sudiyono tidak pernah merasa meramal.
”Jangan dipaksa, kalau memang Ali Sudiyono tidak mau meramal.” Ada seseorang yang membela Ali Sudiyono. Kepada orang itu, Ali Sudiyono mengeluhkan—keluhan itu tidak hanya datang hari ini saja—orang-orang yang antusias dengannya.
”Aku cari cara dari dulu, supaya mereka tidak mengejar-ngejarku meramal, tapi tidak kunjung kutemukan caranya. Aku ini tidak merasa meramal. Aku nyata melihat. Susah menerangkan pokoknya. Yang jelas, demi Tuhan aku tidak pernah merasa meramal.”
Apabila Ali Sudiyono hidup beratus-ratus tahun yang lalu, mungkin sebutan ”nabi” sudah tersemat padanya. Ali Sudiyono dianggap orang suci. Ke mana pun banyak orang yang mengikuti. Orang-orang melayaninya, memenuhi segala permintaannya. Kemungkinan paling gila, Ali Sudiyono disembah layaknya Tuhan. Ali Sudiyono bisa hidup enak, bahkan seumur hidup. Makan dan keperluan-keperluannya ditanggung orang. Semua itu hanya modal meramal.
Suatu ketika, sepuluh hari setelah orangtua Ali Sudiyono pergi ke tanah suci—dua hari sebelumnya tetangganya juga ada yang ke tanah suci—lelaki itu berbincang dengan Yusuf Mahfud, pemuda seumurannya yang tinggal di dekat salah satu gang masuk kampungnya, jika sebentar lagi akan ada empat orang diseret ke kantor polisi karena terlibat perdagangan gelap obat-obatan, sekaligus mengonsumsi. Hanya saja Ali Sudiyono tidak menyebutkan siapa saja yang bakalan tertangkap oleh polisi. Mendadak wajah Yusuf Mahfud berubah menjadi masam, tatapannya seperti tidak tenang. Itu yang membuat Ali Sudiyono tidak berkata lebih lanjut. Dan Yusuf Mahfud juga tidak menanyakannya siapa saja, keempat orang itu.
Hanya Yusuf Mahfud yang sedang bersama Ali Sudiyono. Ada rasa bersalah jatuh di hatinya. Ali Sudiyono menyesal telah mengatakan. Ia tahu apa yang akan terjadi setelah pertemuannya dengan Yusuf Mahfud. Ali Sudiyono secara tidak langsung telah memberikan jalan agar orang itu menyusun rencana supaya aman dari kejaran polisi, jika memang sungguh memercayai kata-katanya.
”Aku juga punya ramalan,” kata Yusuf Mahfud tiba-tiba, dengan nada memendam kejengkelan. ”Kurang lebih sebulan lagi, di kampung kita akan ada yang meninggal dunia setelah bepergian dengan jarak yang begitu jauh.”
Ada perubahan di wajah Ali Sudiyono dalam sekejap.
”Kok kau bisa meramalkan seperti itu?”
Yusuf Mahfud tidak mengucapkan alasannya. Kata-katanya terus mengganggu pikirannya, meski dalam tebakannya, Yusuf Mahfud berkata begitu hanya dilandasi rasa jengkel atas ucapannya. Dan dalam pikirannya, ia tidak ada gambaran apa yang akan terjadi sebulan kemudian.
Apa yang Ali Sudiyono katakan kepada Yusuf Mahfud memang terwujud. Yusuf Mahfud terkena kasus itu. Ia tahu kesehariannya. Ia orang yang tidak setengah-setengah dalam beragama. Ia termasuk orang penting di kampungnya. Dalam menilai seseorang, memang jangan hanya melihat apa yang tampak saja, pikirnya. Terlepas dari ramalannya, apa yang disampaikan Yusuf Mahfud padanya menemui kenyataan. Sebuah pesawat yang berangkat dari ”Negeri Kurma” terjun ke laut. Ali Sudiyono segera teringat dengan perkataan Yusuf Mahfud yang meramalkan akan ada yang meninggal sebulan lagi saat pertemuannya di hari itu. Namun ternyata bukan orangtuanya yang meninggal. Melainkan tetangganya yang juga berangkat haji hampir bersamaan dengan orangtua Ali Sudiyono. Lelaki itu sama sekali tidak kepikiran tentang hal itu, sebab hatinya telanjur dikuasai rasa marah terhadap Yusuf Mahfud.
Jejak Imaji, 2020-2022
***
Risen Dhawuh Abdullah, lahir di Sleman, 29 September 1998. Alumnus Universitas Ahmad Dahlan 2021. Bukunya yang sudah terbit berupa kumpulan cerpen berjudul Aku Memakan Pohon Mangga (Gambang Bukubudaya, 2018). Alumnus Bengkel Bahasa dan Sastra Bantul 2015, kelas cerpen. Anggota Komunitas Jejak Imaji. Bermukim di Bantul, Yogyakarta. Bila ingin berkomunikasi bisa lewat @risen_ridho.
***
(12)
Tarian Kelelawar Biru

Oleh RISDA NUR WIDIA, 31 Desember 2022
/1/ Tangisan Sebutir Peluru
Semua orang di Rafah, wilayah sekitar Gaza, mengenal baik Abu Hasaant. Ia orang baik, tapi sering berpikiran tak masuk akal setelah putrinya, Ammal, terkena peluru nyasar seorang Tzahal di suatu siang. Dari kejadian itu, setiap kali selesai serangan mendadak dari Tzahal ke permukiman penduduk, Abu Hasaant akan datang memeriksa tempat serangan. Di sana Abu Hasaant tidak berusaha menyelamatkan penduduk yang terluka. Ia malah mengumpulkan selongsong peluru yang ditembakkan tentara Tzahal.
Orang-orang di Distrik Rafah tidak mengerti mengapa peluru-peluru itu dikumpulkannya. Padahal selongsong itu tidak laku dijual di pasar loak mingguan yang tidak jauh dari kamp-kamp pengungsian Nusseirat.
”Apa gunanya mengumpulkan selongsong peluru kosong?” Ismail pernah bertanya kepada Abu Hasaant. ”Kau hanya memenuhi dirimu dengan sampah.”
”Ini bukan sampah,” jawab Abu Hasaant. ”Ini harapan.”
”Harapan?” Ismail kebingungan. ”Harapan bagaimana?”
”Harapan yang disalah gunakan manusia,” lanjut Abu Hasaant.
”Kau gila!” Ismail sedih melihat kawannya itu.
”Sulit menjelaskannya kepadamu,” Abu Hasaant menjawab dengan senyum. ”Aku ingin mengurus ceceran harapan ini, lalu menguburnya.”
”Jadi kau mengubur peluru-peluru itu layaknya manusia?” tanya Ismail lagi.
”Oh, terserah apa yang akan kau katakan nanti,” pekik Abu Hasaant. ”Tapi aku sering mendengar mereka menangis.”
Ismail tidak peduli dengan penjelasan Abu Hasaant. Ismail menganggap kalau Abu Hasaant sudah senewan seperti yang sering dikatakan oleh penduduk Distrik Rafah.
Ismail berlalu dengan mengumpat-umpat melihat tindakan Abu Hasaant yang konyol. Sedangkan Abu Hasaant tenang mengumpulkan ceceran selongsong peluru, sambil menahan pedih di hatinya mendengarkan tangisan pilu para selonsong dan mata peluru.
/2/ Permintaan Maaf Sebutir Peluru
Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa ia sering mendengar peluru-peluru itu menangis. Pertama kali Abu Hasaant menyadari kalau peluru itu juga memiliki perasaan seperti manusia terjadi setelah putrinya tertembak secara tidak sengaja tak jauh dari Masjid Abu Alif Rafah. Putrinya waktu itu baru saja pulang dari toko kue yang berada di Jalan Al-Imam Ali, setelah sebelumnya membeli kue baklava. Putrinya tertembak di bagian dada.
Dokter yang mengurus tubuh Amal berhasil mengeluarkan peluru tersebut. Cuma dokter itu tidak mampu menyelamatkan nyawa anaknya dari kehabisan darah dan kerusakan organ.
”Tuhan lebih mencintai putrimu untuk menghuni surga,” jelas si dokter.
Abu Hasaant segera menangis mendengar putrinya meninggal. Bahkan tangisan itu tidak berhenti setelah pemakaman putrinya selesai di kompleks makam Al-Hikmah.
Abu Hasaant sangat terpukul dengan kematian anaknya. Ia merasa bersalah tidak mengantarkan anaknya untuk mencari kue kesukaannya tersebut—karena sebenarnya si anak sempat minta diantarkan, tapi Abu Hasaant malah sibuk mengecat dinding rumahnya.
Setelah sepanjang hari mengikuti upacara pemakaman anaknya, Abu Hasaant mengurung dirinya di kamar. Di tengah rasa sepi hatinya, Abu Hasaant mendengar tangisan lain dari dalam sakunya.
”Apakah benar peluru ini menangis?” Abu Hasaant kebingungan. ”Aku salah dengar?”
”Kau bisa mendengar tangisanku?” tanya si peluru.
Abu Hasaant tercenung cukup lama dengan kejanggalan itu. Apalagi kini peluru itu berbicara dengannya.
Abu Hasaant seketika berpikir: kesedihan membuatnya gila. Ia pun segera meletakkan peluru itu dengan hati-hati di depannya. Kemudian Abu Hasaant menampar wajahnya sebanyak tiga kali.
”Apakah aku benar-benar bisa mendengarkan peluru ini menangis?” Abu Hasaant bingung.
”Ya tangisan itu adalah tangisanku,” sahut si peluru. ”Jadi kau bisa mendengarkan suaraku?”
”Aku bisa mendengarkannya,” Abu Hasaant merasa berhalusinasi.
”Maafkan aku,” segera peluru itu memekik keras. ”Maafkan aku telah membunuh anakmu. Tapi aku tak pernah ingin membunuhnya.”
Peluru itu kemudian menceritakan kepada Abu Hasaant apa yang sebenarnya terjadi.
Peluru itu memang sengaja ditembakkan untuk menciptakan keributan di tengah keramaian pada Jalan Al-Imam Ali di tengah pasar tradisional Al-Burjh. Salah seorang Tzahal yang waktu itu ditugaskan untuk menyamar menjadi masyarakat sipil, menembakkan secara serampangan peluru tersebut, hingga akhirnya mengenai Amal. Si bandit kemudian pergi dengan mobil kapsul hitam bersama kawannya.
”Aku memang diciptakan untuk membunuh,” ungkap si peluru. ”Tapi aku tidak pernah ingin membunuh.”
”Kau tidak bersalah.” Abu Hasaant tiba-tiba mengatakan itu. Padahal hatinya sangat sedih. ”Manusialah yang bersalah. Mereka berperang demi kepentingan pribadinya.”
Peluru itu sekali lagi meminta agar Abu Hasaant memaafkannya. Abu Hasaant segera mengabulkan permintaan itu.
”Tangan manusialah menciptakan kehancuran,” desis Abu Hasaant begitu murung.
”Dan tidak ada yang salah dari seluru benda ciptaannya.”
Peluru itu menangis cukup lama dengan Abu Hasaant. Tangisan mereka terdengar begitu menyedihkan bagi siapa saja yang mendengarnya dari luar pintu apartemen Abu Hasaant.
Setelah cukup lama mereka menangis, si peluru meminta kepada Abu Hasaant untuk menguburnya di suatu tempat agar dapat istirahat dengan tenang. Selain itu, si peluru juga meminta kepada Abu Hasaant untuk mengubur peluru-peluru lainnya bila kelak ia bertemu di suatu tempat.
”Dengan menguburnya, semua rasa bersalah dari kekejaman yang telah kami ciptakan dapat sedikit teredam,” jelas si peluru. ”Jadi mohon kabulkanlah permintaanku ini.”
Abu Hasaant mengangguk dan melakukannya.
/3/ Peluru dan Kepak Kelelawar
Hari berikutnya, setelah Abu Hasaant mengubur peluru yang membunuh anaknya, secara ajaib dari gundukan kuburan peluru itu keluar seekor kelelawar bercahaya biru. Kelelawar itu terbang ke langit Gaza.
”Apa aku tidak salah lihat?” desis Abu Hasaant. ”Peluru itu berubah menjadi kelelawar.”
Dari kejadian tidak masuk akal tersebut, Abu Hasaant mulai mengumpulkan selongsong atau mata peluru sisa peneyerangan yang ditemukannya secara tak sengaja. Demikianlah malam itu adu tembak antara Tzahal dan kelompok perjuangan lokal di dekat kompleks apartemennya kembali terjadi.
Memasuki pukul 12 malam, rentetan tembakan mulai sayup terdengar. Tidak segaduh sebelumnya. Tapi suara-suara menyedihkan lain dari para peluru mulai terdengar.
”Aku mulai mendengarkan tangisan peluru,” desis Abu Hasaant. ”Pasti ada ratusan peluru yang secara terpaksa membunuh seseorang malam ini.”
Sebuah peluru tiba-tiba nyasar mengenai kaca apartemen Abu Hasaant. Ia kemudian mendengar sayup-sayup pekik tangisan dari peluru itu. ”Kau baik-baik saja bersamaku,” tenang Abu Hasaant.
”Aku sumber petaka!” peluru itu merengek. ”Dunia ini hancur karena aku.”
”Tidak,” Abu Hasaant menenangkan. ”Kau adalah harapan manusia yang disalahgunakan.”
Setelah menunggu sekitar satu jam, hingga Abu Hasaant sendiri tertidur di kolong kamarnya, pertempuran dua kubu itu berakhir. Abu Hasaant pun pelan-pelan mulai keluar dari apartemennya. Ia mencoba mengais-ngais peluru yang dapat dijangkaunya dengan mudah di sekitar apartemen.
”Seharusnya para pasukan itu sudah pergi meninggalkan tempat ini,” Abu Hasaant tetap memasang sikap hati-hati. ”Malam ini aku akan menolong kalian.”
Abu Hasaant saksama mencari mata peluru atau selonsong peluru di bawah kakinya. Setiap kali Abu Hasaant menemukannya, ia selalu mendengar tangisan dan kutukan sesal.
”Aku telah membunuh orang,” tangisan sebuah peluru. ”Aku membunuhnya.”
Abu Hasaant menghampiri sisa mata peluru itu. Ia kemudian berusaha menghiburnya.
”Kau adalah sosok baik,” lerai Abu Hasaant. ”Kau tidak pernah salah.”
Ia dengan lembut memasukkan mata peluru itu ke kantong merah yang selalu dibawanya ke mana-mana.
Setelah kantong itu penuh dengan selongsong atau mata peluru, Abu Hasaant membawanya pulang. Namun malam itu, tanpa disadari oleh Abu Hasaant, ada sesuatu yang menunggu nasibnya. Seorang mata-mata zionis yang sudah membaca kisah hidupnya di koran lokal Knesset, berusaha mencari tahu perbuatan Abu Hasaant.
”Ada yang mengikutimu,” kata salah satu peluru dari kantung merahnya. ”Mereka mungkin ingin berbuat jahat kepadamu.”
Abu Hasaant yang mengetahui segera berlari menuju apartemennya. Mata-mata yang mengikutinya kaget. Si mata-mata akhirnya menembak mati Abu Hasaant.
/4/ Para Peluru Mengantar Abu Hasaant ke Surga
Sepanjang malam, mayat Abu Hasaant hanya dibiarkan teronggok—setelah tertembak—tanpa ada yang mengetahuinya. Anjing-anjing liar bahkan sempat ingin memakannya. Seluruh peluru yang dikumpulkan Abu Hasaant segera melindunginya dan menangis histeris mengetahui Abu Hasaant mati.
”Dunia ini bukanlah tempat bagi orang-orang sepertinya,” kata setiap peluru di sana.
”Ia lebih pantas di surga.”
”Kita harus mengantarkannya ke surga,” tambah para peluru lain. ”Kita harus menempatkannya di dekat Tuhan.”
Selonsong dan mata peluru yang jumlahnya puluhan seketika menjadi kelelawar bercahaya biru. Kelelawar itu syahdan merubung mayat Abu Hasaant, hingga tubuh itu menjadi serpihan abu berwarna biru yang perlahan-lahan hanyut diembus angin ke langit dengan para kelelawar.
***
Risda Nur Widia. Kini sedang kuliah S-3 di Pendidikan Bahasa Indonesia UNY. Buku kumpulan cerpen tunggal Berburu Buaya di Hindia Timur (2020).
***






